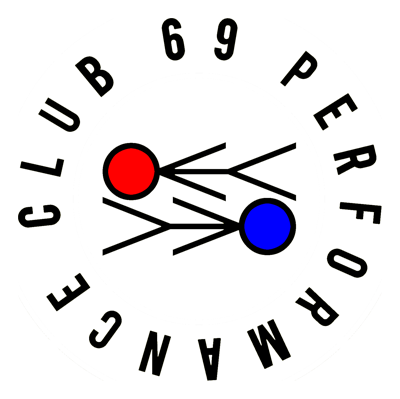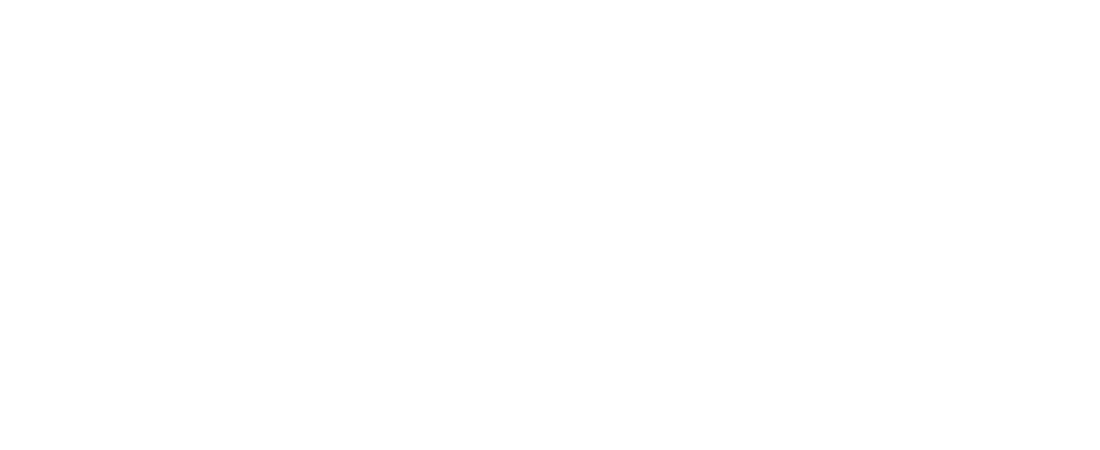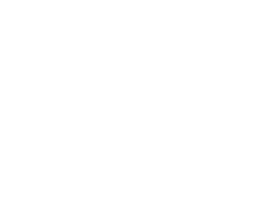Silakan baca edisi Bahasa Inggris dari artikel ini pada link berikut: From Outside to Inside the Screen, then to Outside the Screen
SAYA PRIBADI MENYETUJUI pandangan-pandangan yang menganggap bahwa cerpen Franz Kafka yang ditulis pertama kali tahun 1914, In The Penal Colony, adalah alegori dari detik-detik keruntuhan sistem hukum lama yang serba fisik, ritualistik, dan gigantik. Di akhir cerita itu, kita seolah dihadapkan pada suatu keadaan baru yang belum (dan sangat mungkin akan sulit) diuraikan; Kafka agaknya menawarkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana kita mengandaikan diri kita di tengah situasi yang serba tak terdefinisi dan tak tersentuh—tetapi secara nyata hadir sebagai suatu rutinitas keseharian baru—di saat kuasa-kuasa terpusat membelah diri menjadi pecahan-pecahan pengetahuan dan bahasa yang memungkinkan produksi-produksi difusional berupa kontrol alam bawah sadar.
Sebagaimana Deleuze menambahkan catatan untuk pandangan teoretik Foucault, bahwa Masyarakat Disiplin (Disciplinary Societies) telah bertransformasi menjadi Masyarakat Kontrol (Societies of Control), inilah saatnya kita harus mengakui pandangan Deleuze tentang bagaimana ritus-ritus berpembatas (‘sites of confinement’) telah menjadi “dunia tanpa dinding” (‘infinite world’), tetapi justru sedang melipatgandakan “energi pemenjaraan” (‘panoptic energy’) dalam bentuk tergaibnya; era analog digeser oleh era digital yang mengakumulasi sengkarut sirkulasi komunikasi hingga ke alur terumitnya. Aparatus teknologis pun kini melompat dalam jarak yang tak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya.
Namun, satu hal: konon, menurut Manovich (1995), kita belum juga beranjak dari dunia layar (the era of the screen).
Layar, kiranya, adalah kandidat yang paling mungkin menjadi “penjara abadi” (‘imperishable enclosure’)[1] di kehidupan manusia. Ketimbang berbicara tentang sistem hukum dan penghukuman lewat bahasa deskriptif yang naïve, upaya untuk mendisrupsi kemapanan sistem kontrol tanpa akhir itu barangkali akan membuahkan inspirasi-inspirasi yang lebih menyegarkan lewat refleksi estetik atas elemen-elemen yang membangun konsep “aparatus”—jejala yang dibangun, muncul dari, dan berada dalam sebuah hubungan kekuasaan dan jaringan/rezim pengetahuan.
Di Luar Ruang Suaka Hukuman (atau Out of in The Penal Colony, 2017) adalah proyek seni performans yang digagas oleh Forum Lenteng, yang menjadi bagian dari 69 Performance Club—sebuah platform yang mendorong studi kolaboratif berkelanjutan tentang performativitas, yang diinisiasi oleh organisasi tersebut sejak awal tahun 2016 dengan melibatkan sejumlah seniman di Indonesia. Karya performans yang diniatkan sebagai presentasi khusus ini mencoba mengambil inspirasi dari cerpen Kafka itu dalam rangka meluaskan kajian Forum Lenteng sendiri tentang situasi media dan seni pada masa sekarang.
Saya mengamini beberapa pemikir yang cenderung tidak berniat untuk mendefinisikan “aparatus” secara terang-terangan, lurus, dan tegas—sebagaimana yang dipercayai oleh Agamben bahwa “…terminology is the poetic moment of thought” (Agamben, 2006, “What Is an Apparatus?”). Alasannya tentu saja karena adanya beragam kompleksitas (baik yang terkandung di dalam maupun yang terhubung dari luar) istilah itu. Sejalan dengan itu, saya kira Di Luar Ruang Suaka Hukuman dikembangkan sebagai proyek seni performans yang bukan dalam rangka menanggapi secara ilustratif, apalagi eksplanatoris, cerpen In The Penal Colony. Akan tetapi, mengacu kepada beberapa poin dari cerita itu—yang oleh para senimannya dianggap paling signifikan membentuk impresi kita mengenai sebuah sistem/mekanisme pengaturan (‘a kind of regulatory mechanism or system’)—yang telah dipilih sebagai materi yang kemudian diinterpretasi ke dalam bentuk performans, saya berpendapat bahwa karya ini lebih sebagai upaya untuk mendeklamasikan artikulasi-artikulasi puitik tentang perubahan-perubahan yang sedang berlangsung pada masa sekarang—yaitu, era modulasi dan serba-berlayar ini—di mana praktik multikorporasi lintas wilayah akibat globalisasi, digitalisasi, dan ekspansi jaringan dunia maya adalah keadaan faktual yang membangun situasi multi-kontrol-diri masyarakat dunia.
Deklamasi atas hal itu pada karya ini, sebagaimana dapat dilihat kemudian, dipertunjukkan melalui suatu dramaturgi teknologis yang mencoba merefleksikan posisi tubuh manusia (i.e. para performer) di dalam situasi riil-nya sekaligus keterhubungannya dengan realitas citraan (atau dunia representasional), yang mana citraan-citraan itu pada masa sekarang telah dapat ditransmisikan secara langsung lewat suatu sirkuit elektronis yang diatur sedemikian rupa sehingga membuka kemungkinan tentang komposisi bahasa artistik yang secara sadar melibatkan perangkat-perangkat media saat ini—yang bisa dibilang, merupakan aparatus kontemporer—sebagai bagian utama dari langgam bahasa ataupun gaya ungkapnya.
Para seniman yang menciptakan karya ini, yaitu Otty Widasari, Prashasti Wilujeng Putri, Ragil Dwi Putra, dan Hanif Alghifary—keempatnya adalah partisipan 69 Performance Club—dengan sengaja mengimprovisasi terjemahan mereka sendiri mengenai konsep aparatus, baik yang mengacu kepada gagasan-gagasan yang terkembang di era lama (analog; fisik) dan yang terbangun di era [media] baru (digital; tak dapat disentuh), serta hubungan timbal balik di antara keduanya.
The Man, Decipher, The Wound, dan The Script adalah empat kata kunci yang mengandung gagasan dan semangat untuk mendekonstruksi sistem regulatoris. Di satu sisi, keempat kata kunci ini adalah tapal-tapal batas yang menunjukkan bagaimana mekanisme regulatoris bekerja; jampi-jampi yang mengantarkan imajinasi tentang kekudusan hukum dan penghukuman, tentang aparatus yang—mengadopsi kalimat Agamben—melepaskan segala hal (termasuk kita, manusia) dari kewaran-kewajaran profan dan menempatkannya ke lingkungan yang terpisah (terisolasi).
Di sisi yang lain, jika kita menyetujui pandangan Agamben bahwa hal-hal yang telah dipisahkan lewat suatu aktivitas ritual semacam itu (termasuk, menurut saya, adalah peristiwa penjatuhan vonis, ataupun penerapan kontrol dan disiplin oleh para penguasa terhadap pihak-pihak yang didominasi oleh mereka) dapat dipulihkan dan dikembalikan ke ruang wajarnya melalui suatu aksi penggunaan atau penciptaan kontra-aparatus—yakni, Profanation (‘hujatan atas yang suci’), dalam istilah Agamben—maka, deklamasi berulang-ulang dari keempat kata kunci tersebut yang dilakukan oleh para seniman dengan memanfaatkan distrosi-distorsi elektronis dalam performans ini—turut serta di dalamnya ialah [re]produksi langsung dari gambar dan suara yang dihasilkan melalui gerak konstan tubuh mereka sendiri, bahkan diperluas efeknya dengan teknologi internet—tidak lain adalah tindakan performatif konkret yang dilakukan secara intens dalam rangka mengganggu kemapanan sistem kontrol dari aparatus itu sendiri. Sebagaimana Kafka yang melalui cerpennya mencoba mengalegorisasikan sejauh apa suatu sistem hukum, penghukuman, dan pengaturan mampu bertahan, Di Luar Ruang Suaka Hukuman adalah artikulasi subjektif para performernya dalam rangka niat yang sama. Bahwa, imajinasi tentang keruntuhan sistem yang kini ada, dan kedatangan sebuah era dengan sistem yang baru, barangkali, perlu diandaikan lewat suatu teror yang puitik.
Namun sepertinya, pengandaian-pengandaian yang demikian, yakni imajinasi tentang penggeseran suatu mekanisme lama oleh mekanisme yang baru, selalu akan tetap menuntut keseimbangan. Dalam pandangan yang ekstrem, sebagaimana tergambarkan dalam cerpen Kafka, kiranya peruntuhan mesin ritual yang gigantik itu (masih) membutuhkan suatu martir yang secara sadar mengamini kesezamanan sang aparatus—dan hal ini mengindikasikan bahwa “kejatuhan” sebuah aparatus akan tetap terjadi dengan mengikuti sifat dan karakter elemen-elemen yang membangunnya.
Jikalau Kafka menganggap penghancuran yang fisik membutuhkan pengorbanan fisik pula dalam peristiwa yang sakral—The Officer yang dengan detail mengorasikan kemegahan sang mesin (aparatus), lantas menyerahkan tubuhnya sebagai subjek penghukuman terakhir untuk sang mesin sebelum menuju kehancurannya—para seniman performans Di Luar Ruang Suaka Hukuman adalah subjek-subjek yang merayakan kelindan teknologi media masa kini. Mengikuti sifat dan karakter aparatus kontemporer, maka bukan lagi fisik, tapi mereka memilih untuk “memerangkapkan” citra tubuh mereka ke dalam layar—entitas yang menjadi “aparatus abadi” kita itu—dengan maksud untuk mendorong ke titik terjauh imajinasi mereka sendiri tentang bahasa media yang lebih eksperimental, jikalau bukan tentang dunia media (atau aparatus-aparatus) yang lebih baru.
Karena kita masih akan tetap berada di bawah “kungkungan gaib” dunia layar itu, yang berarti mekanisme regulasi masih akan tetap eksis hingga waktu yang tak dapat diduga ujungnya, peristiwa-peristiwa ritualistik kiranya bisa didapuk dan sekaligus diempang lewat permainan bahasa seni—dalam konteks karya ini, ialah seni performans. Atau setidaknya, dengan cara menguatkan kesadaran kita tentang bagaimana subjektivikasi (‘peng-identitas-an’—dalam pengertian saya) itu diproduksi dan ditentukan definisinya oleh aparatus kekuasaan.
Di Luar Ruang Suaka Hukuman adalah bagian dari upaya para seniman tersebut untuk mencari kemungkinan baru bagi cara pandang kita terhadap dunia yang “divonis” sebagai era layar ini. Bagaimana kita kemudian—subjek yang berusaha melepas belenggu aturan demi aturan yang ada—jika tak lagi berada di bawah “kuasa” layar? ***
Endnotes:
[1] “Penjara Abadi” adalah istilah dari saya sendiri untuk mengabstraksikan keadaan faktual yang perdebatannya “diprovokasi” oleh Lev Manovich ketika ia menjelaskan “arkeologi layar komputer” (lihat Lev Manovich, 1995, An Archeology of a Computer Screen). Menurutnya, kultur layar sudah ada bahkan jauh sebelum kamera dan teknologi layar ditemukan, termasuk sejak era lukisan gua. Sekarang ini, “layar” barangkali adalah entitas kontemporer yang tak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari; hanya karena interaksi dengan layar, interaksi antarmanusia pun bisa tereduksi hingga ke situasi yang cukup mengkhawatirkan—kita seakan-akan terpenjara dan teralienasi dari kawajaran-kewajaran atau bahkan hakikat kemanusiaan. Layar secara tidak langsung “mengontrol” alam bawah sadar manusia Tentunya, gagasan ini tidak serta merta membuat kita memilih kata ‘prison’ sebagai diksi dalam bahasa Inggris. Saya merasa kata ‘enclosure’ lebih tepat karena kata tersebut secara kultural membawa narasi-narasi historis yang berhubungan dengan bagaimana “teknologi itu kemudian berkembang” hingga ke titik tercanggihnya pada masa sekarang (dan mungkin terus ke masa depan).
Referensi:
Agamben, G. (2009). What Is an Apparatus?. Dalam G. Agamben, What Is an Apparatus? and Other Essays (D. Kishik, & S. Pedatella, Penerjemah., hal. 1-24). Stanford, California: Standford University Press.
Deleuze, G. (1992). “Postscript on the Societies of Control”. October , 59 (Winter), 3-7.
Hildebrand-Nilshon, M., Motzkau, J., Papadopoulos, D. (2001). Reintegrating sense into subjectification. Dalam J. R. Morss, N. Stephenson, H. van Rappard, (Editor), Theoretical issues in psychology. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Kafka, F. (2003, October). In the Penal Colony (terj. Ian Johnston). Diperoleh tanggal 8 November 2017, dari situs web The Kafka Project: http://www.kafka.org/index.php?aid=167
Manovich, L. (1995). An Archeology of a Computer Screen. Diperoleh tanggal 8 November 2017, dari situs web Lev Manovich: http://manovich.net/content/04-projects/011-archeology-of-a-computer-screen/09_article_1995.pdf

Dokumentasi latihan dalam rangka karya “Di Luar Ruang Suaka Hukuman” (2017) di Forum Lenteng. (Foto: Forum Lenteng).

“Di Luar Ruang Suaka Hukuman” (2017) dipresentasikan di S.M.A.K., the Municipal Museum of Contemporary Art Ghent, Belgia, tanggal 22 November 2017. (Foto: Forum Lenteng).


“Di Luar Ruang Suaka Hukuman” (2017) di presentasikan di TranzitDisplay Gallery, Praha, Republik Ceko, tanggal 28 November 2017. (Foto: Forum Lenteng).





“Di Luar Ruang Suaka Hukuman” (2017) dipresentasikan di Embassy of Foreign Artists, Genewa, Swiss, tanggal 2 Desember 2017. (Foto: Forum Lenteng).






“Di Luar Ruang Suaka Hukuman – Partisant Edition” (2018) dipresentasikan di Teater Garasi, Yogyakarta, tanggal 14 Januari 2018. (Foto: Forum Lenteng).