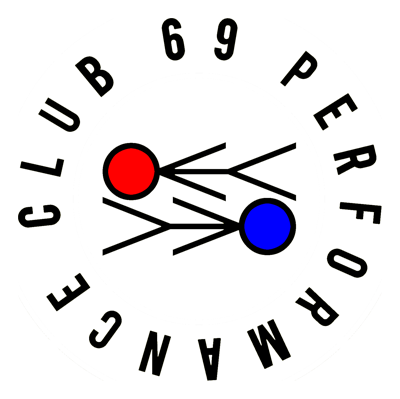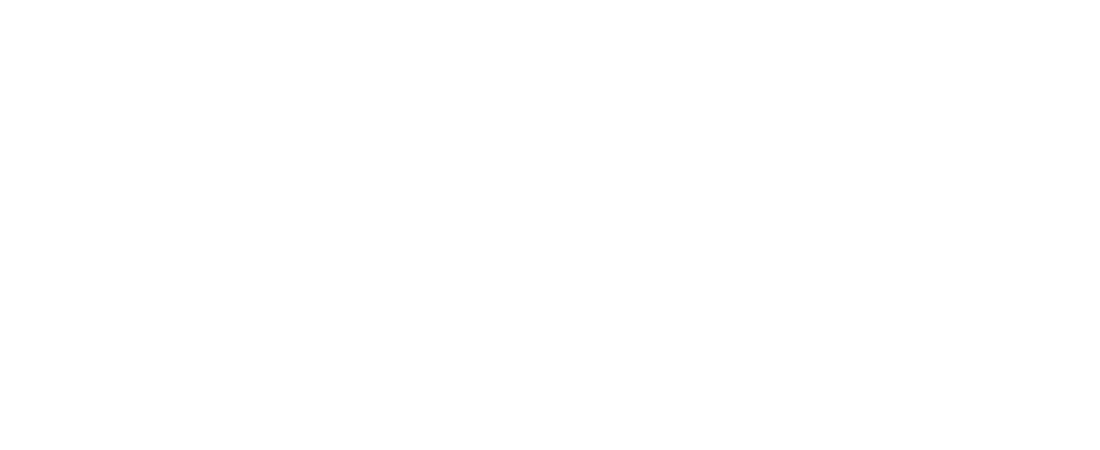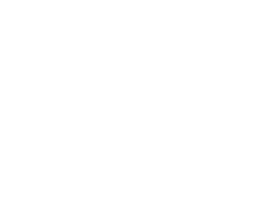Forum Lenteng menyelenggarakan pertemuan kelas dalam rangka platform 69 Performance Club dua kali seminggu, setiap hari Senin dan Sabtu. Tulisan ini merupakan hasil resume dari pertemuan kelas 69 Performance Club pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2019
PADA SETIAP PERTEMUAN kelas dalam rangka platform 69 Performance Club di Forum Lenteng, setiap partisipan biasanya melakukan latihan dan praktik olah tubuh di dalam sebuah area di ruang tamu Forum Lenteng yang dibatasi oleh garis (dari lakban hitam) yang direkatkan di atas lantai. Dalam kerangka latihan dan belajar seni performans di kelas ini, garis lakban hitam tersebut dibuat untuk menegaskan batas imajiner antara “dunia nyata” dan “dunia representasi”. Di dalam “dunia representasi” yang disiapkan itu, tubuh dan geraknya dibingkai menjadi sesuatu yang di luar keseharian dunia nyata. Bahkan, gerak keseharian yang dilakukan dalam ruang representasi pun menjadi non-keseharian, karena ia dijadikan suatu pernyataan. Tubuh, dalam ruang representasi, tampil seperti goresan cat di atas kanvas.

Ahmad Humaedi ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 23 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Hafiz).

Maria C. Silalahi ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 23 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Hafiz).

Robby Octavian ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 23 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Pingkan Polla).

Kegiatan latihan olah tubuh pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Dini Adanurani).
Lantas, perlu kita pertanyakan, dalam konteks seni performans, bagaimana posisi tubuh dalam ruang representasi tersebut?
Pertanyaan tersebut berusaha diselidiki lebih jauh dalam pertemuan kelas 69 Performance Club pada hari Sabtu, 6 April 2019. Unsur pertama, yaitu subjektivitas, dieksplor secara kolektif saat para partisipan berjalan secara bersamaan di ruang representasi. Ruang tersebut dihidupkan melalui ritme dan gerakan yang simultan, saat setiap partisipan melakukan gestur “berjalan” yang sudah menyehari, dalam beragam pola yang mereka telusuri masing-masing, sesekali bertabrakan dengan temannya yang melintas dengan rusuh. Hafiz, yang berperan sebagai fasilitator 69 Performance Club, menginstruksikan para partisipan untuk berjalan seakan-akan mereka berada sendirian di dalam ruangan tersebut.

Kegiatan latihan olah tubuh pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Dini Adanurani).
Secara fisik maupun mental, setiap partisipan tidak mungkin mengabaikan keberadaan orang lain di dalam ruang tersebut, dan hal ini terlontarkan dalam komentar masing-masing partisipan pada sesi diskusi setelah melakukan praktik tersebut. Gerakan yang dilakukan masing-masing partisipan akan selalu antisipatif terhadap apa yang ada di depannya: bagaimana membentuk pola berjalan agar tidak menabrak orang lain, atau justru bagaimana tubuh subjek bereaksi saat menabrak atau ditabrak orang lain—tak ubahnya tabrak-menabrak yang cenderung terjadi di tempat umum sehari-hari.

Dhuha Ramadhani ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 30 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Hafiz).

Pingkan Polla ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 30 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Hafiz).

Theo Nugraha ketika melakukan latihan olah tubuh pada pertemuan 69 Performance Club tanggal 30 Maret 2019 di Forum Lenteng. (Foto: Hafiz).
Hafiz menegaskan bahwa inti latihan tersebut memang bukan untuk mengabaikan keberadaan orang lain, namun tentang bagaimana masing-masing partisipan, sebagai subjek yang melakukan tindakan seni performans, bisa fokus ke dirinya sendiri. Saat sedang berjalan, subjek harus berkonsentrasi pada apa yang sedang ia lakukan, ia harus mampu membangun batas antara dirinya dengan hal-hal di luar dirinya. Hal itu sama seperti bagaimana garis lakban ruang representasi bekerja: ada batas antara “ruang yang dibingkai” dan “ruang yang tak terbingkai”. Namun, dalam konteks latihan di 69 Performance Club, garis lakban tersebut hanya alat bantu semata untuk menegaskan imajinasi tersebut. Sebab, pada akhirnya, sebuah karya seni performans bergantung kepada bagaimana si subjek (si seniman) membingkai dirinya sendiri melalui tubuh yang ia gunakan sebagai medium. Dalam performans yang sadar akan bingkaian diri, gestur-gestur keseharian pun akan mampu menjadi sebuah performans yang non-keseharian.
Unsur kedua yang dieksplor pada hari itu adalah estetika tubuh. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, para partisipan menjadikan tubuh mereka sebagai “bentuk lain”, atau merelasikannya dengan objek-objek lain di luar tubuhnya. Pada pertemuan hari itu, fokus ajarannya ialah bagaimana tubuh bisa berdiri sebagai tubuh itu sendiri? Tubuh yang lepas dari embel-embel si empunya, bukan lagi tubuh si A atau tubuh si B. Tubuh di sini berdiri sebagai objek: bagaimana mengeksplor cara tubuh bekerja, beraksi, bereaksi, dan merespon lingkungan sekitarnya, serta bagaimana dampak dari kerja tubuh itu bisa disimak dari segi visualnya.
Dengan maksud menyelidiki kemungkinan itu, setiap partisipan kemudian diminta untuk melakukan performans di dalam ruang representasi tersebut. Pemahaman mengenai tubuh sebagai objek pun berevolusi dari penampil pertama sampai terakhir. Bagaimana subjek mengobjektifikasi tubuhnya—apakah cukup sekadar menampilkan tubuh apa adanya? Hal tersebut dilakukan oleh Dhanurendra Pandji, yang tampil pertama kali. Namun, apakah itu cukup? Ia telah mencari kemungkinan bagaimana tubuh itu ditempatkan dalam ruang, namun fokus terhadap tubuh itu sendiri belum ada dalam penampilannya. Lantas, apakah dengan menyingkapkan tubuh yang telanjang dan menampilkannya begitu saja seperti yang dilakukan Syahrullah, tubuh telah menjadi objek? Yang ia lakukan, kurang lebih sama dengan Pandji: berdiri di beberapa titik, seperti di tengah ruangan, menempel ke tembok, dan menempel ke jendela. Namun, Ule mampu membingkai tubuhnya sebagai objek yang karakteristiknya dapat diamati secara visual.
Kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki tubuh dieksplor lebih jauh dalam performans-performans lainnya. Manshur Zikri, misalnya, menampilkan bagaimana tubuh dapat melontarkan dirinya ke atas, dan reaksi tubuh atas tindakan itu adalah napas yang tersengal-sengal. Tubuh yang awalnya berpakaian lengkap pun ditanggalkan satu per satu: semakin tampak tubuhnya, semakin dapat diobservasi bagaimana tubuh itu bekerja, dari rusuk yang naik turun saat napas tersengal, sampai gerakan-gerakan anggota badan saat tubuh meloncat-loncat. Penjelajahan lain dilakukan pula oleh Theo Nugraha, yang menampilkan bagaimana bunyi adalah salah satu reaksi yang tercipta saat setiap bagian tubuh tanpa berlapis pakaian ditampar oleh tangan. Theo juga memberikan jeda untuk menampilkan reaksi selanjutnya, yaitu bekas pukulan yang perlahan memerah di sekujur tubuhnya.

Maria C. Silalahi mencoba mengeksplorasi tubuh dengan menjelajahi kemungkinan bentuk pada kulit (lemak) tubuh sebagai caranya untuk mengobjektifikasi tubuh; pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Pingkan Polla).
Lain pula dengan Maria C. Silalahi, yang menggerakkan lemak yang terbungkus kulit di anggota-anggota tubuh tertentu. Di mata saya, tindakan ini seakan menjadi sebuah pernyataan yang emansipatif: yakni pengakuan terhadap lemak sebagai anggota tubuh si subjek—Maria.

Pingkan Polla mencoba mengeksplorasi tubuh dengan melihat reaksi tubuh ketika melakukan endurance tertentu, sebagai cara untuk mengobjektifikasi tubuh, pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Taufiqurrahman).
Sebuah pengamatan muncul dari penampilan para partisipan, yaitu bahwa mengobjektifikasi tubuh dalam konteks performatif adalah tindakan yang subjektif. Apakah cukup jika memajang tubuh layaknya memajang benda-benda di etalase, dan menghilangkan ke-diri-an kita di dalamnya? Tubuh mungkin akan menjelma sebagai objek, namun ia akan seketika berhenti di sana, tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain mengenai tubuh itu sendiri yang dapat dijelajahi lebih dalam, pun tidak ada kekhasan performatif yang membuatnya menarik sebagai sebuah penampilan seni performans.

Theo Nugraha mencoba mengeksplorasi tubuh lewat penciptaan bunyi dengan memukul kulit tubuhnya, sebagai cara untuk mengobjektifikasi tubuh, pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Pingkan Polla).

Syahrullan mencoba mengeksplorasi tubuh dan ruang dengan membekukan dirinya kebalik warna kuning baju kaos yang ia kenakan; pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Pingkan Polla).
Seni performans justru akan menjadi utuh saat ia dibingkai melalui subjektifitas si penampil. Hal ini berhubungan dengan latihan yang dipelajari sejak awal: bagaimana si subjek, yaitu si seniman, dengan penuh kesadaran menjadikan ruangan tersebut miliknya, menjadikan tubuh tersebut miliknya, dan membingkai interaksi antara keduanya melalui cara yang sangat subjektif, sebagai suatu proses penciptaan seni. Hal ini dapat dilihat melalui penampilan Theo, misalnya, sebagai seniman noise yang konsisten mengeksplor bunyi di setiap karyanya; ia menerapkan eksplorasi tersebut ke tubuhnya sendiri. Pun dengan penampilan Zikri, yang memperhitungkan pembabakan yang konstruktif. Ketepatan yang sama, kerap ia terapkan dalam menyusun karya-karya seni dan tulisan-tulisan miliknya, yang terkonstruksi secara sistematis dan berorientasi pada proses. Melalui dua contoh itu, dapat dipahami bahwa tubuh bisa berada dalam dualitas dimensi, subjek dan objek: kemampuannya membingkai diri, dan dirinya sebagai sesuatu yang dibingkai. Seni performans bermain dalam tarik-menarik antara dua dimensi tersebut.
Dalam sesi terakhir, ditambahkan unsur ketiga, yaitu ruang dan objek eksternal. Pada sesi ini, posisi ruang dibalik: “ruang representasi” dipindahposisikan dari ruang kosong ke ruang penonton yang penuh dengan objek-objek. Di sini, para tubuh penampil harus menjelajahi kemungkinan dirinya sebagai objek, sekaligus berinteraksi dengan ruang beserta objek-objek lain yang sudah ada di dalamnya. Elemen tambahan ini dipadukan dengan baik dalam penampilan Syahrullah. Ia menempati titik-titik tertentu dalam ruang tersebut dan berusaha mendeformasi tubuhnya dengan cara memasukkan anggota tubuhnya ke dalam kaos kuning yang tampil mencolok di ruang tersebut, di antara benda-benda yang ada. Ia menciptakan interaksi dengan sekelilingnya saat berusaha mengonstruksi posisi yang tepat bagi dirinya, layaknya sebuah sculpture. Intensi itu dilakukan, antara lain, saat ia menarik papan tulis untuk menciptakan latar berwarna putih, atau menaikkan kursi ke atas meja untuk ia tempati. Di ujung penampilannya, ada kejutan menarik, yaitu saat tubuh yang sejak awal muncul sekaligus tiada akhirnya menghilang, tereduksi dalam kaos kuning semata. Syahrullah bersembunyi ke balik pintu sehingga tak terlihat, lantas melempar kaos kuningnya ke depan para penonton.


Syahrullan mencoba mengeksplorasi tubuh dan ruang dengan membekukan dirinya kebalik warna kuning baju kaos yang ia kenakan; pada pertemuan kelas 69 Performance Club tanggal 6 April 2019. (Foto: Pingkan Polla).
Tarik-menarik yang saya sebutkan sebelumnya semakin tampak dalam sesi terakhir tersebut. Temuan ini dapat menjawab pertanyaan yang saya lontarkan di awal: dalam konteks sebuah seni performans, bagaimana posisi tubuh dalam ruang representasi? Kita kembali lagi kepada dualitas tubuh, yakni tatkala ia diposisikan sebagai objek, namun, pada saat yang sama, ia juga subjek yang menjelajahi dirinya sendiri, juga menjelajahi ruang, dan berinteraksi dengan objek-objek lain. Elemen eksternal yang ditambahkan di sesi terakhir itu membuat penampilan para partisipan bertambah kompleks. Namun, pada saat yang sama, semakin jelas bahwa kompleksitas itu menyerupai cara tubuh berada dalam dunia: tubuh memperoleh pengalaman melalui interaksi dengan hal-hal di sekitarnya. Tanpa disadari, kita telah menjalani mekanisme timbal-balik tersebut dalam kenyataan sehari-hari. Pembingkaian yang dilakukan melalui seni performans dapat mengeksplisitkan mekanisme tersebut, sehingga kerja tubuh tak lagi asing bagi para partisipan. Kelak, mereka dapat menafsirkan tubuh dengan keyakinan penuh seseorang yang memiliki tubuhnya sendiri. ***