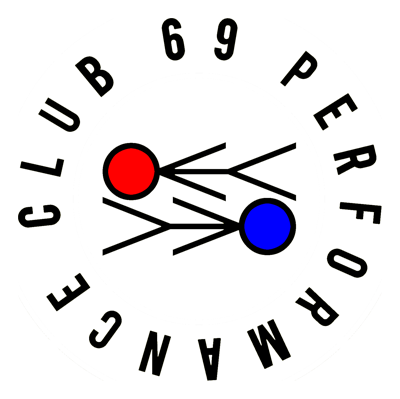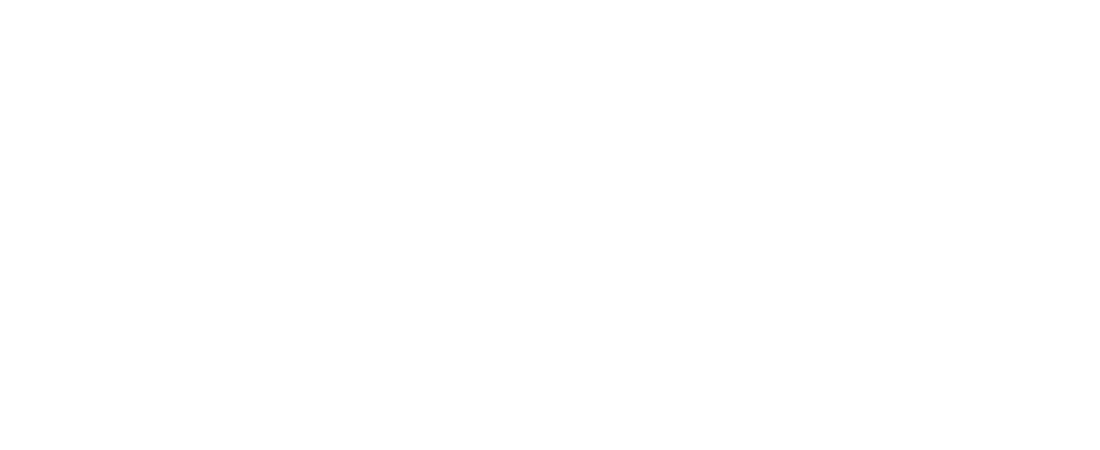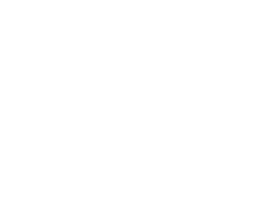Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan arsip pribadi dari Linda Mayasari, berisikan refleksi artistiknya terhadap proses dan hasil kuratorial IDF 2020. Tulisan ini belum pernah diterbitkan sebelumnya. Dengan mengambil studi kasus Indonesian Dance Festival 2020, tulisan yang merefleksikan penyelenggaraan acara seni Tari ini diharapkan dapat memperkaya wawasan kita mengenai kajian-kajian di ranah seni performans dan performativitas secara umum, sekaligus merupakan catatan penting tentang gejala-gejala peristiwa kesenian di masa pandemi. Redaksi performanceart.id menyunting dan menerbitkan tulisan ini atas izin dari penulis. (Editor tulisan: Manshur Zikri).
Prolog
Keterbatasan ruang gerak membawa tantangan tersendiri bagi para pelaku seni tari dan turut memengaruhi pilihan medium, gagasan penciptaan, moda presentasi, dan pola interaksi. Mayoritas dari praktisi tari menjatuhkan pilihan pada fitur teknologi komunikasi yang memberikan peluang untuk tetap mencipta, dan berinterkasi secara virtual lantaran kehadiran langsung, meski di dalam pembatasan jarak fisik, tetap menjadi pertaruhan. Fitur digital di dalam konteks praktik tari, di satu sisi, memberikan beragam perspektif, metode, dan kemungkinan bahasa ungkap baru dalam upaya membaca dan menafsirkan tubuh dan koreografi. Namun, di sisi lain, getaran pengalaman estetik ketika menyaksikan karya tari mungkin akan hilang dan atau digantikan oleh getaran lain yang diperoleh dari “ketakhadiran” atau pengalaman termediasi yang dihadirkan oleh teknologi komunikasi.[1] Tidak hanya moda praktik penciptaan, tetapi cara orang mengalami, menghargai, dan bahkan memandang tari mungkin akan sangat berubah. Istilah “pengalaman termediasi” kini menjadi semakin ambigu jika digunakan untuk merujuk pada jenis pengalaman yang berasal dari dunia daring, karena dunia daring sudah menjadi bagian dari realitas kita.
Ihwal perpindahan ruang presentasi karya seni dari luring ke daring, telah menjadi perdebatan beberapa bulan terakhir ini, tidak hanya di skena tari tetapi kesenian secara luas, baik di Indonesia maupu di skena global. Merespon dinamika perdebatan tersebut, tulisan ini disusun untuk melihat kembali seluk-beluk situasi dan pertimbangan etik-estetik di dalam fenomena ini. Mengambil studi kasus pengalaman praktik kuratorial saya di IDF2020.zip, hal yang akan digali di dalam tulisan ini adalah memetakan strategi artistik para koreografer dalam mempergunakan teknologi digital untuk membingkai karya koreografi ke dalam layar. Pengalaman praktik kuratorial saya di dalam IDF2020.zip akan diletakkan sebagai lanskap pengalaman pribadi yang akan dibaca ulang melalui metode penelitian tindakan (action research). Paula Saukko (2013) menekankan bahwa, di dalam metode penelitian tindakan, transformasi diri perlu selalu dipahami sebagai bagian dari perubahan sosial dan kolektif. Selanjutnya, Saukko menjelaskan cara analisa ini tidak hanya menganalisis atau mendiagnosis bagaimana kekuasaan diskursif bekerja untuk menentukan pengalaman hidup kita, tetapi juga bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan, baik di lingkungan sosial maupun di wilayah penelitian itu sendiri.[2] Dengan demikian, selain untuk memenuhi tugas akhir semester “Kajian Estetika Seni Pertunjukan”[3], tulisan ini juga merupakan uji coba bagi diri saya sendiri untuk mempertemukan pengalaman praktik dengan pengetahuan dan perspektif baru yang saya pelajari di bangku akademik ini. Selain itu, tentunya, untuk mengkritisi praktik saya sendiri yang selalu berada di dalam ruang negosiasi berbagai kepentingan dan kuasa.
Tari di dalam Persimpangan Estetik dan Etik
Teknologi komunikasi digital memungkinkan seniman terus berkarya di tengah pandemi global ini. Ruang-ruang baru dengan bingkai terbatas dan jarak fisik menggerakkan para pencipta tari kontemporer mencari strategi baru dalam berkreasi. Di satu sisi, teknologi digital memberikan kemungkinan bahasa baru untuk mengartikulasikan gagasan, tubuh, dan koreografi. Namun di sisi lain, pengalaman keintiman fisik serta kesinambungan ruang-waktu antara pertunjukan dan penonton hilang atau digantikan oleh getaran-getaran lain. Cara penonton mengakses, mengalami, mengapresiasi, dan memandang tari jelas tidak sama dengan saat tari dihadirkan langsung di atas panggung. Tubuh pertunjukan semakin “termediasi” dan pengalaman (menonton) tari menjadi ambigu dalam proses digitalisasi.
(Pernyataan Kuratorial IDF2020.zip)
Nukilan teks kuratorial IDF2020.zip di atas akan menjadi pijakan untuk mengingat dilema besar yang pernah dialami tim kurator IDF (Indonesian Dance Festival) 2020, ketika tiba-tiba pandemi Covid-19 nyaris membatalkan semua rancangan festival yang telah disusun beberapa bulan sebelumnya. Petang hari, tanggal 2 Maret 2020, tim kurator IDF yang terdiri dari Nia Agustina (Yogyakarta), Rebecca Kezia (Jakarta), Arco Renz (Jerman/Belgia), dan saya sendiri saling bertukar kabar yang sangat mengejutkan bahwa Maria Darmaningsih (salah satu direktur IDF) dan putri bungsunya Sita Tyasutami yang juga menjadi bagian dari komite IDF terkonfirmasi sebagai tiga kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Dua hari kemudian, Ratri Anindya, putri tertua Maria Darmaningsih yang menjadi manajer program IDF 2020 dinyatakan positif Covid-19. Kurator, direksi, dan komite sekretariat IDF pun bersepakat untuk menunggu situasi kondusif hingga ketiganya pulih. Selepas masa perawatan di RSPI Sulianti Saroso, ketiganya berjuang tak hanya untuk memulihkan tubuh, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis, lantaran ketidaksiapan media dalam menerapkan etika membuat ketiganya menerima stigma miring dari masyarakat. Di tengah-tengah situasi berat seperti itu, ketiganya bersiteguh untuk tetap turut memperjuangkan keberlangsungan perhelatan tari melalui IDF 2020. Mengingat dalam jarak waktu, saya memaknai peristiwa tersebut sebagai titik di mana kita, di Indonesia, khususnya skena tari, turut serta di dalam koreografi global Covid-19.
Di dalam pandemi, kita mengalami tubuh yang dicurigai, tubuh yang diperebutkan oleh kuasa wacana kesehatan dan farmasi, tubuh yang diatur oleh serangkaian kebijakan-kebijakan formal. Oleh karenanya, di dalam konteks seni tari, tubuh kemudian tak cukup bila hanya dibicarakan sebagai medium artistik, tetapi seni tari ditantang untuk dapat membaca tubuh dan memproduksi wacana ketubuhan yang lebih kritis dan kontekstual. Dengan demikian, kita dapat membangkitkan kesadaran dan gerak dalam memilah dan memilih berbagai strategi bertahan dan memenangkan kedaulatan atas tubuh kita sendiri. Lantas, apa yang bisa dilakukan tari bila ruang geraknya dibatasi?
Berada di dalam koreografi Covid-19, warga Indonesia secara kolektif tengah menjalankan mode bertahan hidup dalam tingkat yang paling objektif, yakni pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan “lock down” pemerintah, pembatasan jam kerja, pemutusan hubungan kerja membawa imbas signifikan pada aspek ekonomi, terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Ketika dua ratus juta lebih warga negara Indonesia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, para orang tua di desa mencari pinjaman uang untuk membeli telepon pintar dan pulsa untuk sekolah daring anak-anaknya, dan seniman-seniman di berbagai wilayah kehilangan panggung yang menopang hidup keluarganya, dilema etik pun muncul di dalam benak kami, para kuraror: layakkah bila IDF turut memperebutkan sumber-sumber ekonomi di saat-saat sulit seperti ini?
Tidak bisa dipungkiri, IDF, sejak didirikan tahun 1992, telah menjadi mercusuar tari kontemporer Indonesia yang memiliki akumulasi modal kultural[4] besar lantaran ini telah terhubung dengan jaringan kerja di dalam dan di luar tari, di dalam lanskap nasional dan internasional. Bila etik tidak dipertimbangkan, tampaknya apa yang dibaca oleh Schwab dan Smadja di dalam Joost Smiers (2009) berikut ini akan terjadi:
Menjadi jelas bahwa mega-kompetisi di mana semua kompetitor berhadap-hadapan secara langsung dan tanpa kompromi ini adalah bagian dan buah tangan globalisasi yang mendorong terjadinya situasi pemenang menyapu bersih semuanya. Mereka yang ada di puncak akan memenanginya secara besar-besaran dan yang kalah akan kehilangan jumlah yang bahkan jauh lebih besar. Jurang antara mereka yang mampu berselancar dengan gelombang globalisasi, terutama karena orientasi mereka dipandu oleh pengetahuan dan komunikasi, dengan mereka yang tertinggal (dalam dua hal tersebut) menjadi jauh lebih lebar pada tingkat nasional, perusahaan, dan perorangan.[5]
Meskipun saya menduduki posisi istimewa sebagai kurator IDF2020.zip yang tidak perlu terlalu pusing dengan urusan keuangan dan logistik produksi, tetapi di sisi lain saya dan kawan-kawan saya di Cemeti[6] juga tengah bekerja keras secara kolektif untuk menopang keberlangsungan hidup ruang seni kami. Bahkan, di tengah gonjang-ganjing program dan keuangan, tim Cemeti telah bersepakat untuk tidak turut memperebutkan dana pemerintah meskipun berjalan dengan logistik pas-pasan. Dilema etik semacam ini tampaknya belum diantisipasi oleh Schechner, baik di dalam Performance Studies (2013) maupun Performance Theory (2004). Melalui beberapa diskusi daring antara kurator dengan komite IDF di Jakarta, peta situasi dan pertimbangan etik pun disusun. Kami pun bersepakat bahwa mempertimbangkan dunia tari, beserta para pelakunya pun juga terdampak misi yang diemban perhelatan tahun ini, adalah berbagi sumber-sumber kehidupan untuk saling menopang keberlangsungan aktivitas produksi baik karya, pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Berpegang pada peta situasi dan misi bersama tersebut, IDF 2020 dirancang kembali untuk format festival virtual, dan DAYA: CARI CARA menjadi pijakan tema IDF2020.zip.
Negosiasi antara Tubuh dan Teknologi Media
Merancang proyek seni virtual tidak cukup hanya dengan mendigitalisasi karya-karya seni lalu menghadirkannya ke publik secara daring, terutama tari dengan medium utama tubuh, yang mengandalkan kehadiran langsung dan kualitas “liveness”. Mempertimbangkan kebijakan pemerintah Jakarta yang telah melonggarkan PSBB demi menjaga perputaran roda ekonomi, awalnya tim kurator IDF2020.zip masih mencoba untuk menegosiasikan kemungkinan mempertahankan format pertunjukan live (nyata; langsung) dengan pembatasan jumlah penonton dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hanya saja, gedung-gedung pertunjukan yang memadai, seperti Salihara dan TIM, ternyata masih belum bisa diakses dan hal itu menjadikan format virtual menjadi peluang paling besar yang dapat kami ambil pada saat itu.
Meskipun kita mewarisi narasi gerakan eksperimental dance film dari kanon tari modernis Amerika tahun 1960-an yang dikembangkan oleh Merce Cunningham dan Yvonne Rainer, dan dance film telah di rayakan di Indonesia, misalnya di Bandung Dance Film Festival 2017,[7] urusan membingkai tubuh ke dalam layar pada konteks kita saat ini jauh lebih pelik. Pasalnya, ketertautan antara tubuh dan media digital tak hanya cukup dibicarakan di seputar artistik tari atau karya “original” atau “reproduksi”. Perspektif feminisme kritis telah membongkar realitas tubuh perempuan yang direpresentasikan tak adil dan eksploitatif dalam media maupun budaya populer. Betty Friedan, misalnya, pada tahun 1960-an melakukan analisis terhadap majalah-majalah perempuan untuk melihat bagaimana iklan menampilkan perempuan dalam citra-citra stereotipikal yang hanya berperan di wilayah domestik.[8] Objektifikasi perempuan oleh tatapan laki-laki (male gaze) di dalam perspektif dominan kamera di industri film Hollywood telah dikritisi oleh Laura Mulvey melalui esainya, Visual Pleasure and Narrative Cinema, yang ditulis tahun 1973.[9] Iklan dan film di sini tidak hanya menempati posisi sebagai produk teknologi media yang kita tonton secara indrawi, tetapi di dalamnya terdapat wacana tertentu yang meskipun kita konsumsi secara termediasi tetap memengaruhi bagaimana pengalaman dan cara pandang kita dibentuk, seperti yang dipaparkan oleh St. Sunardi berikut ini:
Kini perkembangan media dalam bentuknya seperti yang kita alami sekarang telah menempatkan hubungan antara manusia dan media menjadi kompleks. Kita tidak lagi bisa bicara teknologi satu per satu melainkan ada yang disebut realitas media. Akibatnya, kita tidak lagi bisa bicara fungsi media untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan manusia namun juga media yang mengatur gagasan dan menata perasaan manusia. Kita mengalami kemanusiaan kita lewat realitas media, entah mau atau tidak, suka atau tidak.[10]
Ironisnya, di sini saya sendiri harus jujur, bahwa wacana mengenai ketertautan tubuh, teknologi digital, media, dan budaya populer yang terhampar luas dan gampang diunduh dari internet tak sampai diperdebatkan secara mendalam di dalam diskusi kurator IDF2020.zip. Ada banyak faktor yang menyebabkannya: 1) rancangan kerangka kuratorial dan pilihan karya nyaris mengalami bongkar-pasang karena situasi logistik produksi yang tidak pasti; 2) keterbatasan jarak dan waktu, di mana diskusi antarkurator serta antara kurator dan komite Jakarta mengandalkan pertemuan daring, sementara masing-masing dari kami juga mengerjakan hal-hal lainnya untuk bertahan hidup; 3) bekerja secara daring adalah pengalaman pertama IDF sehingga nalar dan kultur dunia daring tidak bisa dipetakan secara optimal.
Membingkai Tubuh ke dalam Layar
Berada di dalam situasi serba terbatas dan selalu berubah-ubah secara fluktuatif, hal utama yang dapat diandalkan IDF2020.zip untuk mendapatkan posisi paling strategis dalam merealisasikan gagasan festival virtual ini adalah kualitas karya-karya koreografer yang dihadirkan di dalam perhelatan ini. Diskusi dengan para seniman pun dilakukan secara virtual untuk mempertajam gagasan, memperkuat strategi artistik di dalam upaya mendekati nalar kerja virtual, sembari dengan hati-hati membaca potensi munculnya bentuk-bentuk representasi yang problematik. Mengambil momentum proses belajar “Kajian Estetika Seni Pertunjukan” dan berada di dalam jarak pengalaman praktik kuratorial IDF2020.zip yang telah usai ini, saya akan berusaha membaca kembali modus operandi artistik dari kegiatan membingkai tubuh di dalam layar yang dilakukan oleh beberapa seniman IDF2020.zip.
Alih-alih menciptakan koreografi bersama penari profesional, Eun Me Ahn Company dari Korea dengan proyek koreografi 1’59” membangun koreografinya bersama 50 pecinta tari Indonesia dari berbagai latar belakang dan usia. Melalui proyek ini, Eun Me Ahn mengajak mereka untuk kembali melihat diri sendiri dan menggali bahasa ungkap untuk mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.[11] Eun Me Ahn mengkoreografi pertemuan di dalam format seri workshop antara para peserta proyeknya dengan praktisi seni lintas disiplin, misalnya dengan Monica Gillette (koreografer, dramaturg Amerika/Jerman), Ismail Basbeth (pembuat film, Yogyakarta), dan Papermoon (teater boneka, Yogyakarta). Seri pertemuan ini bermuara pada presentasi daring kompilasi 50 video gerak, masing-masing berdurasi 1 menit 59 detik yang diciptakan oleh tiap-tiap peserta, berbasis pengalaman tubuh pribadi dan materi-materi yang mereka pelajari secara kolektif di dalam seri workshop.

Dengan diunggahnya rekaman video seri pertemuan secara simultan dan diakhiri dengan diputarnya kompilasi 50 video secara daring sebagai karya pembuka IDF2020.zip, saya menafsirkan pendekatan Eun Me Ahn ini sebagai koreografi partisipatoris, di mana modalitas konvensional peristiwa tari diretas dengan membawa publik untuk turut mencipta alih-alih menonton. Memanfaatkan fitur teknologi komunikasi, Eun Me Ahn menghadirkan diri ke dalam ruang-ruang privat 50 peserta proyek bukan sebagai koreografer tunggal, tetapi mitra dari 50 orang yang tengah menjalankan proyek koreografi kolektif. Saya menyebut “mitra” di sini untuk menunjukkan watak demokratis dari proyek koreografi 1’59”, lantaran Eun Me Ahn sama sekali tidak melakukan intervensi artistik apa pun terhadap 50 video yang dibuat secara mandiri oleh para partisipan. Meminjam kerangka berpikir Schechner, 1’59” layaknya sebuah ritual virtual sekuler, di mana 50 partisipan bersama Eun Me Ahn hadir secara rutin, berkala, untuk mencercap kenikmatan interaksi sosial dan pengalaman estetik secara kolektif.[12]
Pendekatan koreografi partisipatoris juga dapat kita temukan pada proyek #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020) karya Kolektif lintas disiplin Gymnastik Emporium dari Yogyakarta. Gagasan besar proyek koreografi ini berangkat dari penelitian tentang program senam wajib untuk seluruh siswa sekolah dan pegawai negeri di Indonesia yang dimulai oleh Orde Baru sejak tahun 1970, bersamaan dengan lonjakan ekonomi Indonesia. Ragam senam mulai dari SPI (Senam Pagi Indonesia – Gimnasium Pagi Indonesia), hingga SKJ (Senam Kesegaran Jasmani – Gimnasium Penyegar Tubuh) yang mencapai puncak popularitasnya di Indonesia mulai tahun 1984, disebar ke seluruh penjuru negeri, demi menyiapkan tubuh masyarakat yang sehat untuk menyongsong kemajuan Indonesia. Tim Gymnastik Emporium membaca program ini sebagai perangkat kebudayaan Orde Baru untuk mengonstruksi nilai-nilai Indonesia versi pemerintah otoritarian Soeharto pada tubuh pelajar dan aparatur negara.[13] Dengan kata lain, meminjam nalar Althusser, senam ini dibaca sebagai teks kebudayaan yang menunjukkan bagaimana ISA (Ideological State Apparatuses) Orde Baru dioperasikan di dalam wilayah tubuh-tubuh warganya.[14]
Data dan arsip yang telah disusun oleh Gymnastik Emporium sebelumnya, dibaca ulang bersama dengan 5 guru olah raga dari wilayah Yogyakarta untuk kemudian ditafsirkan ulang ke dalam bentuk koreografi yang memadukan unsur-unsur gerak senam dan tari. Selain gerak, musik pengiring pun diciptakan berdasar pada pembacaan mereka terhadap arsip dan data. Proses penciptaan tahapan ini dilakukan melalui kerja studio dengan pertemuan fisik. Berbeda dari presentasi proyek Gymnastik Emporium sebelumnya di pelantar program Karya Normal Baru Jakarta Biennale, di mana video diolah berdasar pada pengamatan pada kultur media sosial TikTok, kali ini mereka memilih menggunakan nalar video sebagai arsip. Gymnastik Emporium bersama dengan 5 guru olah raga kolaboratornya merekam koreografinya layaknya mendokumentasikan pementasan secara konvensional. Panggung, kostum, tata cahaya, ditata sedemikian rupa sebagai unsur pendukung bagi tampilan koreografi #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020). Kamera merekam gerak dan kedalaman panggung dengan sangat sederhana melalui perspektif porsenium. Pola editing videonya pun mengutamakan dinamika gerak dan ekspresi para penampil, saturasi warna dipadupadankan dengan keutuhan komposisi gerak dan musik pengiring dengan sangat bersih dan rapi. Strategi audio visual ini mereka ambil lantaran hasil akhirnya tidak hanya ditujukan untuk dipresentasikan di IDF2020.zip, tetapi juga menjadi modul sayembara yang mereka buka ke publik untuk dikembangkan dan ditafsir ulang menjadi video koreografi senam. Video #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020) ditampilkan di panggung virtual Youtube IDF bersandingan dengan video pemenang sayembara. Mengambil pendekatan penciptaan video koreografi konvensional untuk karya #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020) adalah strategi yang tepat, karena arsip yang menjadi basis dari penciptaan ini hadir dalam bentuk metabahasa dramaturgi di dalam keseluruhan sajian video koreografi.
Selain dua koreografi partisipatoris dengan moda pendekatan media digital yang berbeda tersebut di atas, kita juga akan dapat melihat ragam pendekatan lain di beberapa karya yang ditampilkan di IDF2020.zip. Karya video Sila karya Hari Ghulur (Mohamed Hariyanto), misalnya, dengan sangat jelas kita bisa melihat pendekatan sinematografis. Ghulur memilih lokasi pengambilan gambar di satu ruangan di dalam gedung bertembok putih, lantai marmer dominan putih yang dikelilingi pintu-pintu besar, dan—saya kira—memiliki atap kaca sehingga pencahayaan seolah asli dari sinar matahari. Pilihan ruang tersebut membawa asosiasi kita pada ruang persembahyangan terutama masjid dan gereja. Pilihan lokasi tersebut mendukung gagasan karyanya yang menggali pengalaman spiritual ketika seseorang duduk bersila dan menyanyikan pepujian bagi Tuhan.[15] Gerak, gestur, dan ekspresi tampak ditata untuk ditatap oleh kamera. Bila kamera #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020) hanya mengambil perspektif auditorium dari depan, kamera pada Sila bergerak dengan leluasa dari kanan ke kiri, memutar, dan kadang dari perspektif atas. Gambar tubuh pun sering tak utuh, fokus memilih untuk merekam bagian-bagian tubuh tertentu yang tengah genting bergerak. Di dalam Sila, kamera tidak ditugasi untuk merekam peristiwa, tetapi mencipta peristiwa.
Eksplorasi media digital yang lebih jauh dapat kita simak pada video trayektori KAMPANA, Eka Wahyuni. Meskipun video ini tidak diciptakan sebagai karya, tetapi lebih sebagai sketsa gagasan, bagi saya, di sini Eka tidak hanya menggunakan media video sebagai medium artistik tetapi menjadi bagian dari inti dari gagasan proyek seni dalam proses yang ia tuturkan. “Video saya pahami bukan sekadar teknologi untuk merekam dan memindahkan dokumentasi proses dan karyanya ke dalam format presentasi virtual, tetapi medium artistik. Mengalami video bagi saya nyaris mirip dengan ketika saya menelusuri sejarah tari gong melalui potongan-potongan artefak, gerak, dan ingatan, di mana jarak, pengaturan fokus, dan distorsi berkelindan di dalamnya.” Demikian pernyataan yang ia sampaikan kepada kurator. Eka dengan sangat tajam mengartikulasikan pembacaannya tentang bagaimana video bekerja membentuk pengalamannya. Unsur-unsur fragmentasi dan distorsi video, ia maknai sebagai materi yang dapat dialami justru karena “ketakutuhannya” layaknya potongan-potongan ingatan kolektif warga di sebuah desa Dayak yang ia kumpulkan ketika hendak mencari tahu sejarah utuh tari Gong. Di dalam video KAMPANA Trajectory-nya, alih-alih menyajikan temuan-temuan penelitiannya tentang tari Gong di dalam susunan dramaturgi yang kronologis, ia justru mengekspos distorsi, permainan fokus, fitur efek-efek video untuk menunjukkan lubang-lubang dan retakan narasi tari Gong yang selama ini membuatnya cukup frustrasi lantaran tak pernah menemukan kisah yang utuh. Dengan kata lain, selain menggunakan video sebagai medium artistik, Eka juga telah mengkritisi cara kerja video itu sendiri.
Epilog
Mengunjungi kembali karya-karya tersebut di atas, kita dapat menangkap ragam pendekatan artistik koreografer di dalam membingkai tubuh sebagai siasat tari di masa pandemi. 1’59” oleh Eun Me Ahn dan #SKJ2020 (Senam Keragaman Jasmani 2020) oleh Gymnastik Emporium menggunakan teknologi komunikasi untuk membangun ruang komunal, di mana ritual ketubuhan dirayakan secara demokratis. Bentuk-bentuk proyek seni partisipatoris yang bernuansa “seni demokratis” (demoratic art) semacam ini memang tidak baru. Merunut genealogi seni Barat, gerakan Post-Dada (konseptulalisme), Political Art (realisme sosialis), dan Post- Bauhaus (Seni Kinetik Konstruktivis) membentuk “seni demokratis” melalui partisipasi penonton sejak era 50-an.[16] Di Indonesia sendiri, kita dapat meminjam catatan sejarah seni rupa untuk menemukan praktik serupa, misalnya praktik seni rupa penyadaran Moelyono. Eksperimen “seni demokratis” Eun Me Ahn dan Gymnastik Emporium yang beroperasi melalui moda virtual tidak harus selalu dilekatkan dengan gerakan seni politik dan/atau anti-estetika, tetapi kita harus kembali melihat pada konteks, kesejarahan, penggunaan, dan konvensi lokal untuk menemukan posisi politisnya.[17] Hadir di dalam konteks pandemi yang membawa dampak di segala aspek kehidupan termasuk tubuh dan psikologi, saya rasa kedua karya ini telah menemukan konteksnya.
Pendekatan sinematografis (filmis) seperti yang dilakukan oleh Hari Ghulur, di dalam konteks seni tari di dalam pandemi, menjadi strategi yang paling mudah ditempuh. Terlepas dari perdebatan tentang hilangnya “liveness” dan munculnya “tubuh virtual”, fitur-fitur di dalam perangkat video membuka peluang bagi hadirnya bahasa artistik tertentu bagi koreografi yang bahkan tidak akan mungkin dapat dicapai di dalam format pertunjukan langsung (live). Hanya saja, bila diletakkan di dalam lanskap dinamika budaya populer, pendekatan ini kemudian seakan menjadi terlalu murah karena meskipun media digital digunakan sebagai alat produksi karya tari, di lapis tertentu sebenarnya ini juga bentuk dari praktik konsumsi fitur digital. Pola hubungan produksi dan konsumsi karya tari Sila yang kemudian dipresentasikan di pelantar festival internasional semacam IDF kemudian tetap melanggengkan perputaran roda kapitalisme industri budaya. Meskipun utopis, kritik Eka Wahyuni terhadap moda kerja teknologi digital paling tidak mengingatkan kita pada bagaimana sebenarnya produk dari teknologi digital ini juga telah membentuk pengalaman dan cara pandang kita terhadap dunia. Dengan demikian, saya kira Eka tidak akan hanya mampu menguasai teknik mengoperasikan perangkat teknologi digital, tetapi juga telah bermain-main di wilayah ambang antara alienasi dan kesadaran yang dibentuk oleh nalar dan kultur teknologi digital. Berdebar-debar saya akan menantikan dobrakan koreografi kritis Eka Wahyuni di masa-masa yang akan datang. *
Catatan Kaki
[1] Walter Benjamin menjelaskan bahwa, di dalam zaman reproduksi mekanik, penggandaan objek memungkinkan untuk terjadi, bahkan bagi karya seni. Di dalam mekanisme inilah, demistifikasi seni terjadi, tetapi bagi Benjamin hal ini tidak sama sekali hal yang buruk, karena menghadirkan peluang untuk mentransfer kekuasaan dari elite ke massa (lihat Richard Schechner, Performance Studies: An Introductio, Thrid edition, NY: Routledge, 2013, hlm. 131-132).
[2] Lihat bagian Between Experience and Discource di dalam Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approach, London: Sage Publication, 2003, hlm. 74-95.
[3] Catatan Editor: penulis adalah mahasiswi S2 Kajian Budaya Universitas Sanata Dharma, Kota Yogyakarta.
[4] Bourdieu tidak hanya melihat semua praktik dan tindakan merupakan konstruksi dari habitus, tetapi ada peran agency, yaitu individu itu sendiri yang mampu menegosiasikan posisi serta modal-modal sosial, budaya, ekonomi, maupun simbolik dalam setiap pilihan hidupnya. Untuk lebih memahami konsep tersebut, baca Pierre Bourdieu, Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, yang diterjemahkan oleh Yudi Santosa, diterbitkan oleh Kreasi Wacana, 2010.
[5] Lihat Joost Smiers, Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Global, Yogyakarta: InsistPress, 2009, hlm. 30.
[6] Catatan Editor: penulis juga menjabat sebagai Direktur Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat, Yogyakarta.
[7] Deny Tri Ardianto dan Bedjo Riyanto, Film Tari; Sebuah Hibridasi Seni Tari, Teknologi Sinema, dan Media Baru, MUDRA Jurnal Seni Budaya Volume 35, Nomor 1, Februari 2020, hlm.112-116.
[8] Lihat bab Feminisme dan Budaya Populer, di dalam Dominic Strinati, Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer, Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2016, hlm. 227-228.
[9] Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Film Theory and Criticism: Introductory Readings, eds. Leo Braudy and Marshall Cohen, New York: Oxford UP, 1999, hlm. 833-44.
[10] Tulisan pengantar St.Sunardi untuk Dominic Strinati, Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer, Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea, 2016, hlm.xiii.
[11] Narasi karya 1’59” di dalam buku program IDF2020.zip – Daya: Cari Cara, Jakarta: Indonesian Dance Festival, 2020.
[12] Lihat, Richard Schechner, Performance Studies: An Introductio, Thrid edition, NY: Routledge, 2013, hlm. 32.
[13] Narasi karya #SKJ2020 oleh Gymnastik Emporium di dalam buku program IDF2020.zip – Daya: Cari Cara, Jakarta: Indonesian Dance Festival, 2020.
[14] Lihat Louis Althusser, Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies, Yogyakarta: Jalasutra, 2008 (1984).
[15] Narasi karya Sila oleh Hari Ghulur di dalam buku program IDF2020.zip – Daya: Cari Cara, Jakarta: Indonesian Dance Festival, 2020.
[16] Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso, 2012, hlm. 77-80.
[17] Lihat, Richard Schechner, Performance Studies: An Introduction, Thrid edition, NY: Routledge, 2013, hlm. 114.
Daftar Pustaka
Bishop, Claire, (2012) Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso.
Bourdieu, Pierre (2010) Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, yang diterjemahkan oleh Yudi Santosa, diterbitkan oleh Kreasi Wacana.
Althusser, Louis, (2008). Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies, Yogyakarta: Jalasutra
Mulvey Laura (1999) Visual Pleasure and Narrative Cinema. Film Theory and Criticism : Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP,
Saukko, Paula (2003) Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approach, London: Sage Publication.
Schechner, Richard, (2013) Performance Studies: An Introduction, Thrid edition, NY: Routledge.
Smiers, Joost (2009) Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Global, Yogyakarta: InsistPress.
Strinati, Dominic (2016) Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer, Yogyakarta: Narasi Pustaka Promethea.
Tri Ardianto, Deny dan Riyanto, Bedjo (2000) Film Tari; Sebuah Hibridasi Seni Tari, Teknologi Sinema, dan Media Baru, MUDRA Jurnal Seni Budaya Volume 35, Nomor 1, Februari 2020.
Buku program IDF, 2020, IDF2020.zip – Daya: Cari Cara, Jakarta: Indonesian Dance Festival.