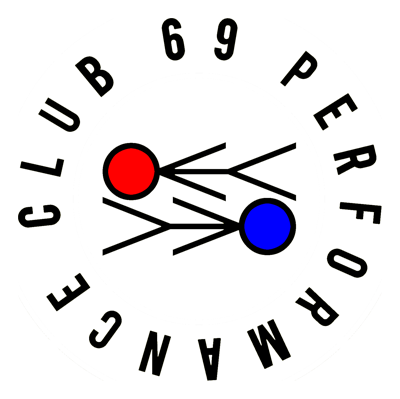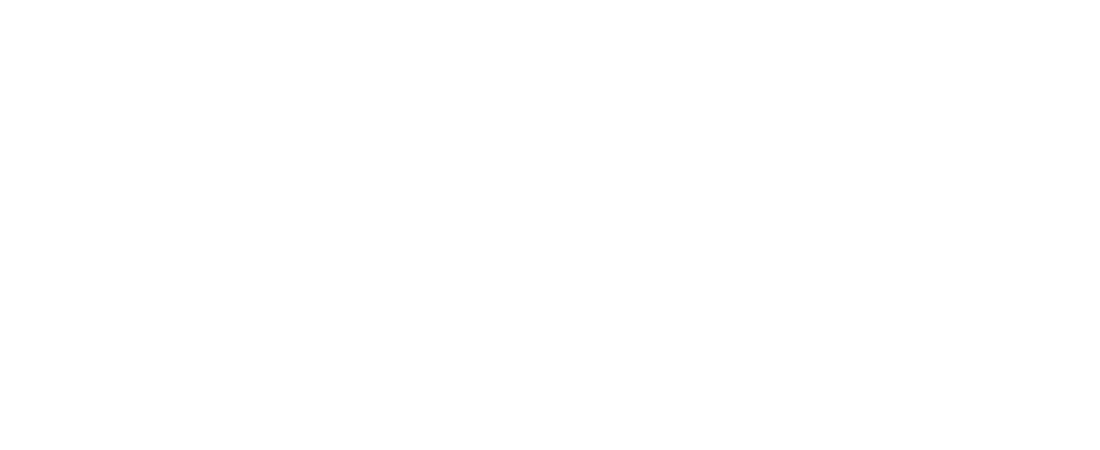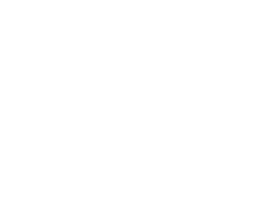JIKA KITA BERBICARA TENTANG GENDER DAN SENI, seketika saya mengingat bentuk seni yang menurut saya paling memiliki kebersituasian yang tinggi, yaitu seni performans. Terkait hal ini, kita bisa mengawali pembahasan tentang performativitas tubuh dalam seni performans dengan pemikiran George Herbert Mead, Erfing Goffman, dan Judith Butler.
Dalam interaksi sosial, Mead melibatkan gagasannya tentang pentingnya konsep diri, yaitu kemampuan seseorang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek; diri adalah kemampuan khas untuk menjadi subjek sekaligus objek. Diri mengalami proses sosial: komunikasi antarmanusia. Diri tumbuh melalui perkembangan serta melalui aktivitas dan relasi sosial. Bagi Mead, mustahil membayangkan suatu diri bisa lahir di tempat di mana tidak tersedia pengalaman sosial.
Terdapat dua aspek dalam proses sosial, yaitu I dan Me. Gagasan Mead ini kemudian dikembangkan oleh Goffman sebagai berikut: I adalah diri yang spontan, yang manusiawi, yang merupakan subjek. Sementara Me adalah diri yang tersosialisasi, yang menjadi objek masyarakat. Kedua konsep ini menyebabkan tegangan antara harapan individu dan harapan orang lain. Tentunya kita sebagai manusia dituntut oleh orang-orang di sekitar kita karena kita telah mempunyai konstruksi status dan peran dalam masyarakat. Negosiasi akan hal ini melahirkan citra diri, bagaimana kita tampil untuk audiens sosial kita.
Jadi, diri adalah produk interaksi dramatis antara aktor dan audiens.
Pembicaraan mengenai citra diri ini merupakan pembicaraan tentang strategi bertahan hidup karena siapa pun yang tidak menjalankan status dan peran yang dilekatkan kepada dirinya akan dihukum oleh masyarakat.
Jadi, tidak ada tubuh yang tidak mengalami konstruksi sosial. Butler dalam hal ini lebih suka memakai istilah “social inscription”. Status dan peran seseorang “dituliskan” atau “ditatokan” dalam tubuh individu. Tubuh manusia sudah diberi gender sejak awal eksistensi sosial mereka (dan tidak ada eksistensi yang tidak bersifat sosial), yang artinya tidak ada “tubuh yang natural” yang bebas dari konstruksi sosial itu.
Butler memakai istilah social inscription karena, menurutnya, gender merupakan akibat dari satu set tindakan yang berulang dalam kerangka peraturan yang sangat kaku. Kerangka peraturan yang sangat kaku itulah yang disebut bahasa. Bahasa dan wacana akan gender dituliskan, atau ditatokan, pada tubuh-tubuh manusia. Bahasa dan wacana men-genderkan tubuh. Oleh karena itu, identitas gender merupakan sesuatu yang performatif—karena menentukan gejala sosial yang ada pada dan dialami oleh tubuh.
Bagaimana bahasa (dan wacana) mengenderkan tubuh, dan bagaimana itu menjadi sesuatu yang performatif, hal itu dapat dijelaskan dengan mengacu konsep yang dikembangkan oleh J. L. Austin.
Austin menggagas konsep performative utterances atau illocutionary acts. Ucapan performatif itu adalah saat ucapan tersebut bersifat transformatif. Ia menciptakan perubahan dalam lingkup pribadi atau lingkungan, yang meggambarkan dunia seperti apa yang mungkin terjadi di masa depan.
Contohnya, saat seseorang mengatakan “saya bersedia dan berjanji setia…”, atau saat penghulu mengatakan “sah” pada upacara pernikahan, ia tidak hanya mendeskripsikan atau melaporkan pernikahannya, tapi ia menuruntukan (indulging) pernikahan itu. Atau, saat seorang suster atau dokter mendeklarasikan bayi yang masih ada di perut sebagai perempuan atau laki-laki maka sebenarnya mereka menentukan seks dan gender terhadap tubuh yang bisa saja tidak mempunyai eksistensi di luar itu.
Hukum bahasa dituliskan pada tubuh kita, dan hukum tersebut terlihat melalui tubuh kita. Ia dituliskan oleh agen-agen yang mempunyai kekuatan, seperti pemerintah, sistem peradilan pidana, akademisi, dan industri sehingga kehidupan dilihat oleh kita seolah-olah sebagai sebuah rutinitas, tidak memungkinkan untuk diubah atau ditransformasi.
Lalu, bagaimana kita mentransformasi hukum yang dituliskan pada tubuh kita tersebut?
Constitutive Criminology (Kriminologi Konstitutif), menurut saya, dalam hal ini dapat memberikan tawaran. Dalam kajian tentang kejahatan, Kriminologi Konstitutif melihat kejahatan bukan ditentukan oleh perbuatan, atau karena sebab tunggal lainnya, seperti kemiskinan. Kejahatan menentukan dan ditentukan oleh narasi yang digunakan untuk mendeskripsikan kejahatan. Wacana akan kejahatan yang diproduksi oleh polisi, masyarakat, dan akademisi makin memperkuat ciptaan ide akan kejahatan tersebut. Individu, kultur, komunitas, dan struktutr sosial mempunyai deskripsinya sendiri akan definisi tentang apa yang teratur dan tidak teratur, dan definisi akan apa yang jahat versus yang baik.

Jadi, cara terbaik untuk mengurangi kejahatan adalah dengan mengurangi ide akan produksi kejahatan dan mencegah wacana-wacana yang tidak sehat dengan cara menggantinya dengan kedamaian dan wacana inklusi. Yang dibutuhkan adalah agen-agen untuk memproduksi wacana-wacana alternatif demi membentuk lingkungan sosial kita di luar wacana-wacana yang tidak sehat tersebut. Dan kita, sebagai manusia, sebenarnya adalah agen pembentuk aktif lingkungan kita sendiri.
Saya lantas teringat pada proyek Anitha Silvia dan Hoo Fan Chon pada Makassar Biennale 2019 yang lalu. Pada presentasi di Simposium Makassar Biennale 2019, Hoo Fan Chon memaparkan tentang identitas kecinaan dan keindonesiaan; bagaimana sebuah nama itu menentukan identitas kita. Pada masa Orde Baru, orang-orang keturunan Cina di Indonesia harus mengganti nama mereka dengan “nama pribumi”. Negara mengerahkan kekuatannya untuk berusaha menghapus ingatan dan identitas tubuh dengan cara mengganti nama.
Definisi terhadap tubuh juga dilakukan negara dalam rangka membingkai tubuh perempuan. Ada satu karya kuratorial oleh seorang kurator filem muda Indonesia, bernama Dini Adanurani. Ia melakukan penelitian tentang filem berita yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara pada 1951-1976, bernama Gelora Indonesia. Gelora Indonesia ini diputar di bioskop seminggu sekali sebelum filem utama dimulai. Jadi, alih-alih memutar iklan, bioskop harus memutar filem yang menceritakan apa saja yang telah dilakukan negara kepada rakyat banyak. Dini Adanurani melakukan penelitian tentang bagaimana perempuan diletakkan di filem berita tersebut.
Filem berita Gelora Indonesia mempunyai segmen khusus, yaitu Dunia Wanita. Dini Adanurani dalam tulisannya memaparkan tentang bagaimana kamera menangkap citra perempuan yang shot-nya selalu diambil dari bawah, lalu ke atas. Itu berlaku untuk citra perempuan yang berada dalam konteks kecantikan maupun perempuan yang sedang baris-berbaris dalam situasi militeristik. Narasi-narasi seperti ini dipaparkan Dini sebagai narasi yang eksploitatif. Di beberapa segmen, terdapat segmen yang penuh dengan tangkapan gambar yang fokus pada lekukan-lekukan tubuh berbaju renang minim, dan gambar yang menyorot keseluruhan tubuh perempuan dari bawah ke atas.
Bagaimana tubuh perempuan dilihat, mana yang ideal dan yang tidak ideal, didefinisikan oleh negara. Tidak hanya itu. Pihak di luar negara, seperti pelaku industri, pun melakukannya sehingga kita terkonstruksi: tubuh seperti apa yang ideal. Kita bisa melihat di iklan-iklan korset di lejel home shopping, misalnya.
Untuk itu, dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif, kita sendiri haruslah sadar, dan harus mulai melakukan upaya penyadaran bahwa kita mempunyai peluang, dan menjadi peluang itu sendiri, untuk memberikan wacana atau narasi alternatif mengenai hukum yang dituliskan pada tubuh kita. Menjadi sangat mungkin bagi kita untuk menuliskannya ulang dengan narasi yang kita konstruksi sendiri.
Tindak upaya untuk mendekonstruksi gender dalam tubuh manusia adalah semangat mengembalikan agensi untuk menarasikan wacana alternatif tentang norma, bahasa, dan agensi itu sendiri secara dinamis, yang terus-menerus berubah, menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini, seni dapat menjadi metode untuk menuliskan ulang tato seperti apa yang ingin kita tuliskan ke tubuh kita sendiri.
Seni performans (performance art) merupakan salah satu tawaran. Saya dapat katakan bahwa, apa yang dilakukan oleh Hoo Fan Chon dan Anitha Silvia beserta kawan-kawan yang lain di Bulukumba adalah usaha yang performatif. Mereka membuat seseorang berusaha untuk mengingat nama asli mereka dalam Bahasa Tionghoa, atau nama ayah mereka dalam Bahasa Tionghoa, untuk melacak ulang identitasnya. Untuk melacak ulang ingatannya akan identitas mereka yang terdahulu. Ingat, ingatan adalah sesuatu yang memberi konteks terhadap kehidupan.
Spasialitas dan kebersituasian merupakan salah satu unsur performance art. Karena pada dasarnya ia bukanlah seni reproduksi yang bisa diulang. Ia tidak mungkin pernah sama di waktu dan ruang yang berbeda, dengan individu, ruang, dan masyarakat yang berbeda.
Mengutip apa yang Akbar Yumni paparkan dalam Forum Festival ARKIPEL Bromocorah, “…membayangkan performativitas, sebagaimana praktik seni performans bekerja, ia bersifat present, ia tidak akan sama pada waktu dan ruang yang berbeda karena tidak bertujuan untuk mereproduksi dirinya sendiri. Ia adalah sebuah peristiwa (event) ketimbang metode yang bisa di ulang-ulang secara reproduktif, karena objeknya adalah waktu dan spasialitas yang melingkupi seninya. Sifat spasialitas pada seni performatif tersebutlah yang kemudian menjadikan seni pertunjukan adalah seni peristiwa.”
Lalu, dapat kita simpulkan, karena ia adalah sebuah peristiwa yang mempunyai kaitan erat dengan individu, ruang, dan masyarakatnya, ia akan memberikan peluan-peluang berupa ruang kontemplasi kepada penonton. Ruang kontemplasi itu lah yang dapat memberikan interpretasi dan ide yang beraneka ragam yang dapat melahirkan suatu narasi alternatif.
Tubuh di dalam karya-karya seni performans, yang diperlihatkan kepada penonton, bukanlah tubuh-tubuh yang hitam putih. Tubuh dalam seni performans adalah tubuh yang memberikan ruang diskusi. Demi hal itu, bahasa estetika yang dipakai dalam seni performans adalah bahasa yang progresif dan alternative. Ia bersifat transformatif, menciptakan perubahan yang disebabkan oleh tubuh, terhadap tubuh, dan terutama dalam memandang dan mendefinisikan ulang gender.
[Tulisan ini akan bersambung ke Bagian 2...]
Bibliografi
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2011). Teori Sosiologi. Bantul: LKPM.
Butler, J. (2015) Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press.