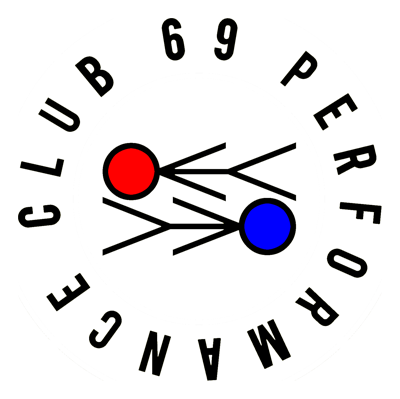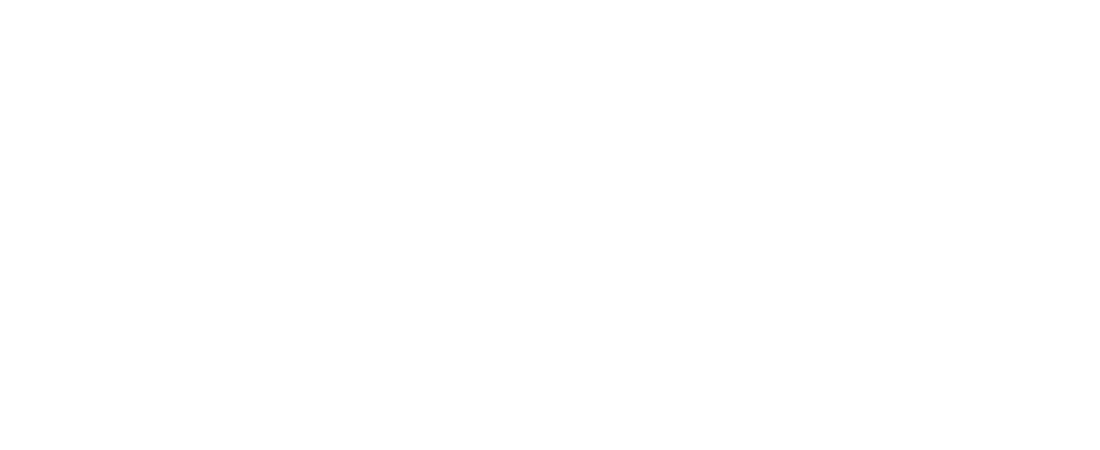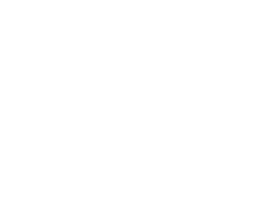DALAM SEJARAH SENI rupa, subjek tema pada karya-karya masyhur paling banyak memuat rekaman-rekaman peristiwa sehari-hari yang dialami oleh si seniman. Tradisi perekaman ini sudah jamak muncul sejak aliran seni rupa impresionisme berkembang di Eropa pada abad ke-19, dengan aksi merekam secara langsung objek peristiwa di masyarakat, atau hal-hal yang sangat pribadi bagi sang seniman. Aliran impresionis melekat dengan kejadian yang sesungguhnya, di mana tatapan mata pada satu peristiwa atau objek dipindahkan ke atas kanvas dari impresi-impresi indrawi. Salah satu subjek yang sering direkam adalah peristiwa pesta-pesta yang memabukkan dengan minuman-minuman beralkohol. Pada satu masa pada abad ke-17, ada banyak pelukis di Perancis dan Belanda yang melukiskan kondisi para buruh tani yang menghabiskan waktu hari-harinya dengan mabuk minum anggur dengan penuh drama seperti “The Drinking Peasants” (1620-1630) karya Adriaen Brouwer dan “Peasants Drinking In A Tavern Interior” (1676-1704) karya Egbert van Heemskerk. Pada periode romantik itu, segala peristiwa digambarkan dengan hal-hal yang penuh drama, begitu juga dengan peristiwa mabuk. Saya mengingat salah satu lukisan favorit waktu kuliah di sekolah seni rupa, “The Card Players” (1890) karya Paul Cezanne, yang menggambarkan dua orang buruh tani dari kawasan Jas de Bouffan, Aix en Provence, Perancis, yang tenggelam dalam permainan kartu remi dan sebotol anggur. Berbeda dengan lukisan pada abad ke-17, “The Card Players” tidak menggambarkan kegilaan peristiwa mabuk, namun Cezanne secara puitik mengganti hal yang memabukan itu dengan ketenggelaman dua tokoh dalam kanvas itu pada kartu-kartunya, sementara sebotol anggur menemani mereka. Karya ini adalah satu karya terbaik Cezanne pada periode terakhirnya.

Lukisan “The Card Players” (1890) oleh Paul Cezanne
Tidak hanya di Eropa, tradisi minum minuman beralkohol juga sudah menjadi bagian dari masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, dari kalangan petani hingga pekerja di kota. Berbagai jenis minuman beralkohol lokal sangat dikenal masyarakat kita, seperti cap tikus, tuak, arak bali, sopi, dan ciu yang berasal dari fermentasi beras, nira enau, kelapa, aren, dan berbagai jenis buah tropis sudah menjadi konsumsi utama dari ratusan tahun lalu. Minuman beralkohol juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ritual-ritual keagamaan masyarakat lokal dalam memasuki dunia transenden nenek moyang, selain untuk pesta-pesta pergaulan. Meskipun sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, tidak banyak yang merekam peristiwa-peristiwa mabuk dalam karya seni. Hal ini mungkin terkait dengan aturan-aturan moral agama yang menempatkan minuman berakohol sebagai dosa dan wajib dihindari. Minuman beralkohol khas daerah-daerah di Indonesia dianggap ilegal secara hukum formal. Sebagai subjek seni, tentu saja bukan kegilaan dari minuman ini yang perlu dibingkai, tapi bagaimana ia sering dipakai sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat di beberapa daerah di Indonesia.

Ketika kita membicarakan bagaimana membingkai persoalan budaya mabuk ke dalam seni, karya seni performans “Oh Parmitu” (The Supper) dari Otty Widasari, adalah salah satu karya penting untuk dilihat. Judul karya ini berangkat dari sebuah lagu Batak ciptaan Nahum Sitomorang yang sangat terkenal berjudul “Lisoi”, dalam bahasa Indonesia berarti “Oh Kawan Seperminuman”. Lagu ini selalu menjadi lagu utama yang dinyanyikan dalam pergaulan pesta di lapo-lapo (warung minuman khas Batak), serta pesta masyarakat Batak. Lirik pada lagu “Lisoi” adalah gambaran betapa guyubnya orang-orang Batak. Pada lirik yang sederhana itu tergambar betapa ikatan persaudaraan mereka sangat kental satu sama lain. Saling menghibur dalam duka dan saling tertawa dalam gembira.
Karya performans “Oh Parmitu” ditampilkan pada 14 Desember 2018 di Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan, pada perhelatan festival seni performans bertajuk “Perform” yang diselenggarakan oleh salah satu museum terbesar di Seoul setiap tahun. Performans berdurasi 50 menit ini menghadirkan sang performer di atas panggung dengan latar layar yang memproyeksikan secara langsung peristwa performans dari tangkapan kamera dan terhubung dengan kanal media sosial YouTube. Selain para penonton di ruang museum, para pemirsa dari berbagai penjuru dunia dapat melihat secara langsung peristiwa performans ini dari kanal video sosial media ini.

Saya melihat secara daring di Indonesia saat karya ini ditampilkan di Seoul. Otty memulai dengan naik ke atas panggung dalam ruang pertunjukkan museum, membawa sebotol anggur merah dan gelas. Di atas meja, sudah tersedia sebuah metronom. Kemudian ia mengeluarkan dua sumpit kayu yang tersimpan di jaketnya. Sesaat kemudian Otty memulai menggerakkan metronom dengan tempo lambat. Lalu, ia membuka botol anggur dan menuangkannya ke dalam gelas. Ia meminum tuangan pertama itu sampai habis. Kemudian ia mulai memukul meja dengan sumpit kayu, mengikuti irama tempo metronom. Satu dua mengisi ruang jeda antara ketukan yang keluar dari metronom. Ketukan konstan ini berlangsung selama beberapa menit. Kemudian ia mengubah kecepatan metronom, yang secara konsisten mengulangi aktivitas yang sama; menuang anggur, meminumnya, lalu memulai memukul meja dan gelas kosong dengan sumpit kayu, mengikuti tempo metronom. Hal ini terus dilakukan dalam tiga bagian pertama. Kemudian ia menggeser posisi meja dan tempat duduk ke arah penonton — lebih dekat ke arah kamera. Seperti sebelumnya, ia memulai aktivitas yang sama, menuangkan anggur ke gelas, meminumnya, lalu memukul meja dan gelas mengikuti tempo metronom, yang sudah dipercepat dari tempo sebelumnya. Aktivitas yang sama terus dilakukan dalam babak-babak selanjutnya dengan mengikuti tempo ketukan metronom yang semakin cepat dan semakin cepat. Di setiap perubahan kecepatan, sang seniman berusaha mengikuti konstruksi tempo yang terukur itu, dalam situasi kesadaran yang mulai berubah karena pengaruh anggur. Pada menit-menit terakhir, tempo semakin cepat, Otty seperti sudah melampaui kesadaran untuk dapat mengikuti tempo metronom yang dia atur. Adegan ini diakhiri dengan pecahnya gelas anggur yang dipukul olehnya.

Selain adegan Otty dengan metronom dan minum anggur, layar di belakangnya menampilkan secara langsung tangkapan kamera di depan panggung. Otty, dengan sengaja, menghadirkan proyeksi video feedback yang dihasilkan dari posisi kamera yang menangkap secara langsung aktivitas performans dan tangkapan kamera di layar. Posisi kamera menghasilkan noise video, di mana tangkapan kamera tereplikasi secara elektronis berlapis-lapis sampai pada jumlah yang tak terhingga (infinity). Setiap lapis menimbulkan jeda (delay) secara proyeksi, sehingga menghasilkan efek pengulangan dengan jeda beberapa detik dari tangkapan secara langsung. Pada awal-awal munculnya seni video di Amerika Serikat dan Eropa, teknik video feedback menjadi salah satu ‘bahasa visual’ yang jamak untuk membangun ilusi visual dunia yang tak terbatas. Sehingga pada tahun 1970an, efek noise video feedback ini dianggap sebagai bentuk-bentuk visual yang psychedelic, acap kali dikaitkan dengan ‘dunia memabukkan’ yang sering dipakai oleh para pemadat dan pemusik-pemusik psychedelic di zamannya. Pada tahun 1990an, teknik video feedback ini sempat menjadi trend dalam ruang-ruang diskotik di berbagai belahan dunia. Ilusi video feedback inilah yang secara sadar digunakan oleh Otty dalam karya “Oh Parmitu” untuk membuka lapisan-lapisan simulasi yang terjadi pada seorang seniman performans saat pertunjukan. Selain efek feedback video, secara bersamaan suara yang dihasilkan pada pertunjukkan itu menghasilkan feedback suara yang membentuk lapisan-lapisan bunyi yang baru, yang memberikan dampak ilusi suara di luar bunyi yang dihasilkan pukulan sumpit pada meja dan gelas, serta suara konsisten dari metronom. Secara langsung, penonton menangkap pertunjukkan “Oh Parmitu” bukan hanya sebagai sebuah pertunjukan seni performans, namun juga pertunjukan seni bunyi atau musik eksperimental, jika merujuk pada pola struktur yang sangat ketat dengan pembabakan dan tempo yang sangat terukur yang dilakukan Otty pada benda-benda dan teknologi yang menghasilkan bunyi.

“Oh Parmitu” terdiri dari 4 babak. Pada setiap babak terjadi pengulangan-pengulangan adegan yang sama. Perbedaan tiap babak dihadirkan dengan tingkat intensi berbeda di mana ketukan metronom diposisikan sebagai pengatur tempo gerakan dan bunyi jadi bingkai utamanya. Tiap-tiap tempo akan mengurai lapisan-lapisan bunyi dan bentuk, dengan menghanyutkan sang performer dalam formasi yang dirancang oleh Otty secara sadar. Lapisan-lapisan itu disimulasikan lagi dengan proyeksi hasil tangkapan kamera, yang yang terurai dalam video feedback berulang-ulang. Dengan sengaja Otty memberikan ruang jeda melalui keterbatasan teknologi internet, di mana visual atas siaran langsung tersebut menghasilkan jeda yang tak terduga. Sehingga, terkadang proyeksi siaran langsung tersendat, karena jaringan internet yang tidak stabil. Di sini kita bisa melihat bagaimana tiap lapisan terurai dengan kemungkinan-kemungkinan berbeda, di mana pertunjukan secara langsung yang diproyeksikan juga secara ‘langsung’ melalui jaringan internet akhirnya menghadirkan ‘ketidak-langsungan’ peristiwa. Penonton mendapat kesempatan dalam jeda-jeda yang terjadi di antaranya untuk menikmati lapisan-lapisan visual dan suara yang saling berhimpun selama pertunjukan berlangsung. Tiap perubahan-perubahan tempo yang digagas oleh Otty, kita diajak untuk menduga-duga kemungkinan bunyi dan gerakkan apa yang akan muncul sesudahnya. Selain itu, latar proyeksi, memunculkan efek enigmatis secara visual pada peristiwa pertunjukannya.

Pertunjukan yang berlangsung selama 50 menit ini menghabiskan satu liter anggur merah hingga akhir pertunjukkan. Selama pertunjukkan, Otty mendorong sejauh mana batas kemampuan tubuhnya, dalam hal kesadaran, saat distimulasi dengan minuman beralkohol. Secara biologis, tubuh akan bereaksi secara langsung saat sejumlah stimulasi kimiawi masuk ke dalam tubuh. Dalam kadar tertentu, alkohol akan mengubah kemampuan bertahan pada kesadaran neurotik karena stimulasi secara terus-menerus pada jantung dan otak. Dalam “Oh Parmitu”, Otty dengan sadar melakukan pengujian pada tingkat kesadaran dan ketidaksadaran neurotik itu melalui stimulasi yang sangat kompleks. Selain menggunakan alkohol, ia juga menggunakan hitungan matematika dalam ketukan metronom yang secara terus-menerus memaksa dirinya untuk tetap sadar. Secara kimiawi, ia menstimulasi tubuh dengan alkohol. Lalu dengan bunyi yang terukur, ia menstimulasi bunyi atau indra pendengarannya. Kemudian, secara kognitif, Otty menghadirkan benda-benda dengan kemungkinan-kemungkinan aktivitas atau peristiwa pada benda tersebut, seperti botol anggur, gelas, metronom, sumpit, meja, bangku, bahkan ruang pertunjukkannya. Melalui dramaturgi ruang, ia menempatkan benda dan kemungkinan visual dengan terukur; posisi kamera, layar proyeksi, dan di mana ia hadir di hadapan penonton yang selama pertunjukan bergeser ke titik yang telah ia perhitungkan di akhir performans.

Pada “Oh Parmitu”, dapat dilihat kesadaran pada pembagian ruang yang diperhitungkan secara matang, selayaknya konstruksi pada alur filem, di mana tiap babak punya intensitas dan dramatiknya sendiri. Performans dengan sengaja meletakkan posisi sorot lampu pada satu titik; di tengah panggung di mana ruang di luar sorotan cahaya menjadi temaram. Pada babak pertama, Otty berada di luar sorotan lampu dan secara perlahan memulai aksinya di cahaya temaram. Babak berikutnya, ia bergeser tepat di pusat sorotan cahaya lampu, di mana permainan tempo bunyi metronom dilakukan. Pada babak ini, ia mulai bermain dengan permainan bunyi yang mengganggu ‘keteraturan’ suara yang keluar dari metronom. Feedback video yang menghadirkan berlapis-lapis bingkai tak terbatas, diikuti suara yang bercampur aduk dengan lengkingan feedback yang dihasilkan dari lapisan pengulangan-pengulangan, serta bunyi pukulan yang dimainkan. Di bagian akhir, ia kembali berada di zona temaram persis dihadapan penonton. Jika diamati dari awal babak, kita dapat melihat pembagian ‘frame’ yang merujuk pada kehadiran kamera yang membingkai posisi performer di atas panggung. “Oh Parmitu” membingkai peristiwa dalam bingkai kamera dengan long-shot, medium-shot, medium-close-up, dan close-up, yang menghasilkan efek sinematik yang sangat berbeda dari sekadar sebuah peristiwa seni performans.
Jika diamati lebih jauh, karya performans “Oh Parmitu” membongkar lapisan-lapisan kerja teknologi media yang sejatinya terkontrol dalam sebuah sistem dan berubah menjadi otonom. Ia meruntuhkan kontrol atas konten yang diproduksi, lalu lepas dalam ruang-ruang yang tanpa batas. Mesin atau teknologi media bekerja sendiri, seperti yang terlihat bagaimana performans yang ditayangkan langsung melalui YouTube direplikasi dalam jumlah yang tak terhingga atau infinity, menuju tindakan tanpa kendali atau automatis. Dari sini kita dapat melihat bagaimaa kerja ‘mesin’ yang otonom itu, pada akhirnya melawan kreatornya, seakan seperti Frankenstein syndrome dalam sebuah novel, atau yang lebih dikenal dengan konsepsi humanoid dan robota yang terkenal dari Ceko. Dari pandangan ini, dapat dilihat bagaimana Otty mempertanyakan modernitas dan konsepsi-konsepi yang mengikutinya dalam peradaban kita sekarang. Modernitas hakikatnya adalah sesuatu yang terukur dan terkontrol dalam mekanisme pengetahuan saintifik, namun dalam praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, kontrol dan mekanisme yang tersistem tersebut bisa saja menjadi tidak dapat dikendalikan.
Dalam sejarah seni performans di Indonesia, tidak banyak karya yang mempertanyakan aspek-aspek teknologi media, serta hubungannya dengan modernintas kita. Apalagi menjadikan ‘minum’ sebagai bingkai estetik untuk masuk ke ruang sistematis itu, hampir tidak pernah saya temukan. Karya-karya performans kita, masih banyak berhenti pada tubuh sebagai statement politis dan ekspresi subjektif. Kesadaran pada praktik media (media massa, media sosial, dan teknologinya) sering luput dari praktik berkesenian, terutama seni performans. “Oh Parmitu” memberikan ruang yang berbeda dalam seni performans kita. Ia menjadikan praktik-praktik yang berlaku dalam masyarakat (tradisi) menjadi pintu masuk untuk mengkritisi dirinya sendiri dan ruang-ruang modernitas kontemporer kita. Karena dalam satu sisi modernitas itu telah menjadi ‘hantu’ dalam ruang-ruang tanpa kontrol yang bernama teknologi media.

Mengingat kembali pada lukisan “The Card Players” (1890) karya Paul Cezanne, saya jadi tersenyum bagaimana “Oh Parmitu” karya Otty seperti melengkapi dimensi politis dari apa yang saya kagumi dari lukisan itu. Pada performans ini, tentu saja tidak ada kawan minum atau lawan main kartu. Kawan minum digantikan oleh kehadiran penonton di ruang pertunjukkan museum atau penonton dari berbagai belahan dunia secara daring pada kanal YouTube. Melalui performans ini Otty mengajak kawan-kawan minumnya untuk menertawakan ‘hantu’ modernitas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. “Sirupma, sirupma, dorgukma, dorgukma ingkon rumar doi, Lisoi! Oh Parmitu” (Hiruplah, hiruplah, telanlah, telanlah harus dihabiskan, Lisoi! Oh kawan seperminuman). *