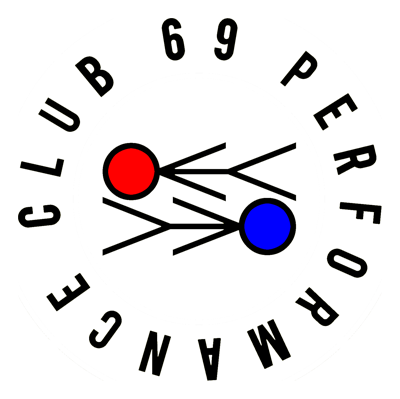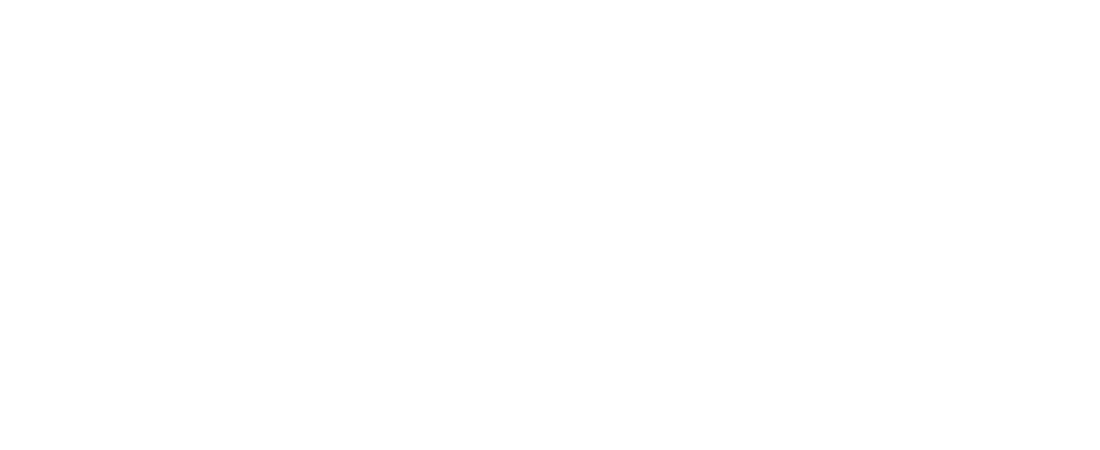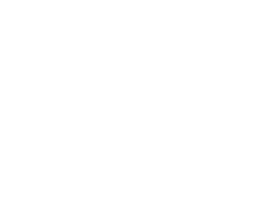Dokumentasi karya seni performans berjudul Boxing (2016) karya Muhammad Fauzan Chaniago. (Foto: Forum Lenteng).
SENI PERFORMANS ADALAH karya seni atau penampilan (bisa juga disebut pameran, pertunjukan, atau peragaan)[1] karya seni yang dibuat melalui aksi-aksi yang dilakukan oleh seniman atau partisipan lainnya, baik berdasarkan sketsa (tertulis) yang dikembangkan secara matang maupun yang direalisasikan secara spontan; karya atau penampilan ini bisa disaksikan secara langsung ataupun lewat dokumentasi, dan secara tradisional disajikan kepada publik di dalam konteks fine art dengan suatu modus interdisipliner.[2]
Kita juga bisa mengajukan definisi yang lebih sederhana. Seni performans adalah “karya seni berupa aksi dan peristiwa yang dihasilkan dari aksi tersebut.” Pengertian ini memenggal “pemanggungan” dari keharusan, dan sekaligus memperluas kemungkinan penyajian karya seni performans, bahkan ke situasi di mana audiens tidak menyadari dirinya tengah menjadi audiens.
Terma “tampil” yang melekat dalam genre ini kemudian bisa dimaknai pula dengan lebih tepat sebagai konsep yang berarti “mewujud” atau “menjadi ada” (come into being) daripada sekadar “hadir di panggung” (come on stage). Sementara itu, untuk mengartikan seni performans dalam hubungannya dengan subjek pelaku (si penampil—performer), kita bisa mengutip kata-kata Helga Finter dan Matthew Griffin (1997): performans adalah sebuah bentuk yang merupakan “…the manifestation of subject’s presence by his doing.”[3] Dengan kata lain, signifikansi kehadiran tubuh seorang seniman performans dipertimbangkan berdasarkan tindakan yang ia lakukan.
Pengertian-pengertian di atas bisa menjadi basis kita untuk menangkap aspek polemis ketika ingin memperbincangkan karya seni performans ketiga Muhammad Fauzan Chaniago a.k.a. Padang, yang berjudul Boxing (2016). Karya ini tampak sangat sederhana dari segi aksi, tetapi terbilang cukup pelik dari segi konsepsi.

Dokumentasi karya seni performans berjudul Boxing (2016) karya Muhammad Fauzan Chaniago. (Foto: Forum Lenteng).
Boxing dipresentasikan pada acara 69 Performance Club yang dikurasi oleh Hafiz dalam tajuk Transmitted Delusion pada tanggal 6 Maret 2016 di Forum Lenteng, Jakarta. Ide kuratorial Hafiz adalah tubuh sebagai media transmisi bagi rekaman-rekaman kenyataan yang maknanya telah dilepaskan dari konteks sosial, kultural, dan kepatutan. Melalui tubuh pula, rekaman-rekaman itu dikolase untuk membangun “kenyataan yang melampaui kenyataan”—kenyataan baru. Namun, dengan terbentuknya kenyataan baru itu melalui seni performans yang disajikan, audiens diharapkan dapat menarik konteks-konteks tertentu yang memperjelas ikatan tak terputus antara “hasil transmisi” dan “habitus-sosial”, baik habitus yang berhubungan dengan si penampil maupun habitus yang berhubungan dengan audiens sendiri. Dengan picuan ide itu, bagaimana kiranya bentuk transmisi dan kolase yang dilakukan oleh para seniman?
Padang memilih untuk bermain-main dengan kotak kardus; agaknya ia hendak mengejutkan penonton. Akan tetapi, bagi saya, aksinya terbilang jauh lebih filosofis daripada sekadar gurauan artistik yang mengundang tawa dan kebingungan penonton. Terkait hal ini, mari kita tinjau terlebih dahulu aksi Padang melalui Boxing sebelum mengurai aspek filosofis yang saya maksud:
Saat tiba giliran Padang untuk “tampil”, sang kurator mengumumkannya dengan berujar, “Karyanya Fauzan—Padang, yang berjudul Boxing!” Di dalam video dokumentasi karya ini, kita dapat melihat bahwa audiens seketika membentuk suatu “jarak” terhadap tumpukan kotak kardus yang terletak di salah satu sudut ruang tamu Forum Lenteng kala itu (area yang menjadi tempat penyajian karya-karya seni performans hari itu). Audiens secara naluriah memberikan semacam “ruang/zona tampilan” bagi Boxing. Agaknya, kata “boxing” yang diujarkan kurator sebagai judul karya inilah yang menyadarkan audiens bahwa akan ada sebuah penampilan yang berhubungan dengan kotak-kotak kardus yang sedari tadi nangkring di situ, menemani mereka sejak acara bermula. Artinya, gelagat audiens ini secara tidak langsung menciptakan suatu “pemanggungan” bagi karya seni performans tersebut.

Setelah menunggu beberapa saat, kita melihat kotak-kotak kardus itu tumbang; ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Salah satu kotak kardus yang berukuran lebih kecil terlepas dari susunan awal. Setelah hening beberapa detik, konstruksi kotak kardus yang ukurannya besar-besar bergerak lagi—kembali berdiri—menuju posisi dan posenya yang semula. Ternyata, kotak-kotak kardus yang ukurannya lebih besar itu dibuat saling terekat satu sama lain. Nah, di momen ketika konstruksi kotak kardus itu kembali bergerak berdirilah kita mendapati sebuah celah yang terbuka, yang melaluinya audiens bisa melihat dengan jelas bahwa ada orang di dalam konstruksi kardus yang bersitumpuk tersebut—ternyata si seniman “bertingkah” di baliknya.

Dapat kita pahami kemudian bahwa kotak-kotak kardus itu kosong; mereka disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bilik yang di dalamnya Padang bersembunyi selama acara 69 Performance Club berlangsung. Sesaat setelah gilirannya beraksi diumumkan, ia menjatuhkan dirinya dari dalam untuk menumbangkan kotak-kotak kardus itu, lalu memberikan suatu jeda bagi penonton untuk mengamati kejadian tersebut, hingga akhirnya ia berdiri lagi, mengembalikan posisi tumpukan kotak kardus, menyisakan waktu bagi penonton untuk mencermati apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, kali ini raut visual dari tumpukan kotak kardus telah berubah. Salah satu bagiannya telah terpisah—kotak kardus yang kecil menggeletak di lantai—sementara permukaan mereka telah renyuk sebagian.

Terlihat bahwa, pada presentasi karya seni performans Abi Rama, The Trust Among Us, tumpukan kotak kardus sudah nangkring di sudut ruangan. (Foto: Forum Lenteng).
Perlu diingat bahwa dalam acara 69 Performance Club hari itu, ada juga karya-karya seni performans dari seniman lain yang ditampilkan bergiliran; para seniman tampil secara bergantian. Penyajian karya Padang nyatanya diumumkan bukan pada giliran pertama. Sang kurator baru mengumumkannya justru sebagai sajian terakhir, setelah empat karya lainnya selesai dipertunjukkan. Akan tetapi, Padang sebenarnya sudah melakukan aksi performatifnya bahkan sebelum acara 69 Performance Club tersebut benar-benar dimulai. Ia bersembunyi di dalam tumpukan kotak kardus, bergeming di sana mulai dari sejak ruangan acara belum dipenuhi oleh audiens, sampai dengan gilirannya tampil diumumkan. Inisiatif semacam ini pada dasarnya telah mengganggu “teatrikalitas” suatu acara secara keseluruhan; inilah suatu keunikan dari intensi artistik yang menonjolkan “kualitas-performans”,[4] di mana batas-batas ruang-waktu sajian dibuyarkan oleh tindakan dalam sajian, sedangkan sifat representasi dan presentasi dilebur menjadi sebuah proses dalam tindakan itu sendiri. Menariknya, setelah ia melakukan aksi “menjatuhkan diri bersama kotak kardus untuk kemudian berdiri lagi”, Padang tetap bergeming di sana, di dalam “pose baru” tumpukan kotak kardus itu. Padang tetap diam hingga acara 69 Performance Club hari itu benar-benar ditutup oleh kurator. “Lebih dari tiga jam gue di dalem kardus!” kata Padang, suatu hari kepada saya.
Kita bisa meninjau lagi konteks ruang-waktu dari Boxing ini, yang sebenarnya lebih luas daripada lingkup saat dia beraksi menjatuhkan diri. Kotak-kotak kardus itu, sejak awal, tentunya tampak sebagai properti yang dipersiapkan dan sengaja di taruh di sana. Mungkin, di mata sebagian audiens, kotak-kotak kardus itu akan digunakan oleh salah satu seniman dalam salah satu karya yang akan dilihat. Pikiran audiens ini tidak benar sepenuhnya. Sebab, nyatanya, pada saat sebagian audiens mengira bahwa kotak-kotak kardus itu akan digunakan, sesungguhnya kotak-kotak kardus itu sudah dan sedang digunakan oleh si seniman. Sementara beberapa karya dari seniman lain tengah ditampilkan ke hadapan audiens secara bergiliran di waktu-waktu sebelum penyajian Boxing diumumkan, penampilan Boxing itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung, disadari atau tidak oleh audiens. Dengan kata lain, Boxing telah “mengada” atau “menjadi ada” sebagai peristiwa artistik-performatif sejak “panggung belum diberikan” kepadanya, dan juga sejak “audiens belum menyadari” keberadaan si seniman, tindakannya, dan peristiwa yang diciptakannya.
Sehubungan dengan gagasan mengenai “kehadiran tubuh dalam seni performans”, dalam deskripsi karya Boxing—sebagaimana yang termuat dalam situs web performanceart.id—dinyatakan bahwa Padang “…mempersoalkan kehadiran itu sebagai ‘kehadiran’ yang imajinatif.” Saya pikir, deskripsi ini kurang lengkap. Alih-alih hanya “kehadiran yang imajinatif”, Boxing juga berbicara soal “ketidakhadiran yang imajinatif”. Karya ini menjadi semacam argumentasi yang membolak-balikkan kemungkinan ontologis dari praxis kehadiran yang termanifestasi melalui aksi. Dalam konteks seni performans, kita memahami bahwa kegemingan tubuh Padang saat bersembunyi (berupaya “tidak hadir”), pada satu sisi, secara teoretis menegaskan kehadirannya sebagai tubuh performatif di dalam peristiwa performatif, terlepas apakah audiens menyadarinya atau tidak. Akan tetapi, pada sisi yang lain, upaya memfaktualkan kehadiran tubuh dalam Boxing, secara paradoks, juga menciptakan manifestasi baru tentang ketidakhadiran tubuh. Justru, tatkala ia benar-benar hadir ke hadapan audiens melalui aksi memporak-porandakan konstruksi kotak kardus, audiens diajak untuk berimajinasi mengenai “ketidakhadiran”-nya. Padang hadir saat ia “belum hadir”, dan ia “tidak hadir” saat ia hadir secara faktual di mata penonton.

Dokumentasi karya seni performans berjudul Boxing (2016) karya Muhammad Fauzan Chaniago. (Foto: Forum Lenteng).
Di lingkup pengulang-alikan konseptual antara “hadir” dan “tidak hadir”, serta antara “yang imajinatif” dan “yang faktual”, dalam konteks sajian Boxing ini, transmisi menuju “kenyataan” yang berangkat dari aksi tubuh yang memainkan benda tersebut, ujung-ujungnya, mengantarkan kita kepada refleksi mengenai virtualitas material performans.
Dalam virtualitas material performans, apa yang kita sebut “teatrikalitas”—jika meminjam kata-kata Helga Finter (1994: 155)—adalah suatu batas yang menjadi prasyarat keberadaan “Teks” (dengan T kapital), namun sekaligus merupakan sesuatu yang perlu dilanggar, didobrak, dihancurkan, atau dilampaui oleh peformans itu sendiri; dan dengan begitu, “Teks” bukan lagi sebuah objek, melainkan sebuah proses, sedangkan subjek yang mengungkapkan (utter) “Teks” tersebut—menurut istilah filosofis Kristeva (sebagaimana dikutip oleh Finter)—adalah “subjek dalam proses”.[5] Si penampil bukanlah pihak yang menentukan “Teks”, dan oleh karena itu, “Teks” berada di luar prediksinya. Pandangan ini, menurut Finter, memposisikan performans sebagai sesuatu yang “…mempertanyakan representasi sebagai sebuah hasil dari pementasan imajiner.”[6] Keberadaan representasi dianggap tidak lagi ada, sebab performans (aksi si penampil), pada saat itu juga, tengah “…menciptakan realitasnya sendiri di dalam sebuah proses”, yaitu proses yang mengandaikan sistem-sistem tanda (seperti gerak dan gesture) untuk “berada” dan “mengada” secara bersama-sama menjadi layaknya unsur-unsur dalam eksperimen saintifik, yang memungkinkan observasi atas interaksi virtual mereka satu sama lain.[7] Audiens, menurut Finter, diajak “…untuk membangun hubungan-hubungan virtual tersebut di antara tingkatan persepsi yang berbeda-beda, untuk membuat teks mereka sendiri dari material yang diperpandangkan”—penekanannya dengan kata lain terletak pada kualitas material dari apa yang dipertunjukkan/diaksikan.[8]
Jika kita mengacu kepada refleksi di atas, aksi Padang yang menjatuhkan diri di dalam kotak kardus bukanlah aksi yang sedang mencoba merepresentasikan makna apa yang mungkin dikandung baik di dalam keberadaan kardus, di dalam peristiwa jatuhnya kardus, maupun di dalam kondisi pasca-pergerakan kardus. Yang merupakan sasarannya adalah “presentasi perubahan”, baik secara spasial (hubungan antara komposisi kardus dan ruangnya), temporal (hubungan antara keberadaan mereka dan rentang waktu acara), maupun perseptual (hubungan antara keberlangsungan peristiwa dan kesadaran audiens akan peristiwa itu), serta bagaimana kehadiran dari perubahan ini memicu penilaian relasional terhadap kenyataan-kenyataan kita sehari-hari yang terkonstruksi secara sosial.
Kita layak memahami bahwa peristiwa artistik yang diciptakan dari aksi performatif Padang ini menyisakan suatu efek pada benda dan tubuh, sekaligus juga memproyeksikan “efek penanda” kepada audiens, yaitu “keberubahan” raut permukaan kardus, dan “keberubahan” posisi komposisional tumpukan kardus itu terhadap ruang-waktu tampilan—suatu efek yang melaluinya mekanisme dari modalitas bahasa dapat diperdebatkan lebih jauh. Namun, virtualitas material bukan hanya terletak pada dua macam “keberubahan” itu, tetapi juga pada “keberubahan” sikap subjek dan atmosfer peristiwa: dari geming ke gerak, dari “Tidak Ada” (yang mendalihkan Ada) ke Ada (yang memaksudkan “Ketidakberadaan”). Oleh karena itu, yang dapat kita simpulkan sebagai “kenyataan” (dengan tanda petik) yang melampaui kenyataan (tanpa tanda petik), dalam konteks Boxing ini, adalah “imajinasi yang dikonkretkan”, sebagai aksi, lantas peristiwa, yang di dalamnya tubuh bukan lagi perihal “tubuh manusia”, tetapi “tubuh material”.
Akhir kata, kita pun bisa menutup artikel ini dengan mengajukan refleksi yang lebih umum: melalui performans, realitas material yang terkonstruksi secara sosial dapat didekonstruksi dengan menguak propertinya. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita mesti menghancurkan sebuah benda dalam rangka meneliti atau memahami bakat-bakat material yang dikandungnya…?
Jadi, seperti yang saya bilang: dengan karya ini, Padang bukan sedang bergurau…, meskipun aksinya, ya… ngebongkar kotak kardus. *
Endnotes:
[1] Saya menyertakan semua kata tersebut—‘penampilan’, ‘pertunjukan’, ‘peragaan’, dan ‘pameran’—sebagai arti dari “exhibition”, mengingat masing-masing dari mereka kerap digunakan sebagai istilah-istilah yang berkaitan dengan genre ini, performance art. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa ada sejumlah literatur (dan beberapa pelaku seni, seperti kurator dan kritikus) yang memberikan batasan definisi untuk membedakan konteks penggunaan dan filosofis dari masing-masing kata itu. Istilah tertentu lebih cenderung dikaitkan dengan disiplin yang lain, misalnya ‘pertunjukan’ lebih identik ke performing art, atau ‘pameran’ yang lebih identik ke seni rupa. Di tulisan ini, batasan masing-masing istilah bukan menjadi perhatian kita.
[2] Pengertian ini saya kutip dan terjemahkan dari Wikipedia Bahasa Inggris, “Performance Art”, sedangkan Wikipedia mengutip dari situs web Tate Modern, “Performance Art”. Saya menyetujuinya secara pribadi karena pengertian ini meletakkan “seni performans” dalam posisi yang jelas (secara historis), yaitu latar fine art, sehingga menyiratkan perluasan epistemiknya yang paling mungkin dalam keterhubungan genre ini dengan genre seni lain, misalnya dengan “seni pertunjukan” (performing arts: musik, tari, dan teater).
[3] Helga Finter dan Matthew Griffin, “Antonin Artaud and the Impossible Theatre: The Legacy of the Theatre of Cruelty”, TDR (1988-), Vol. 41, No. 4 (1997), hlm. 17.
[4] Perlu digarisbawahi bahwa, ketika saya menyebut “kualitas-performans” (atau performance-quality), itu tidak serta-merta merujuk hanya kepada karya seni performans saja. Nyatanya, karya-karya pada genre lain, misalnya Teater, juga mempunyai “kualitas-performans” yang dapat ditelaah. Dalam kajian-kajian mengenai estetika Teater Modern, “kualitas-performans” menjadi perhatian para pengamat dalam hubungannya dengan upaya mempertanyakan kembali sistem representasi.
[5] Helga Finter, “Disclosure(s) of Re-Presentation: Performance hic et nunc”, dalam REAL: Year-book of Research in English and American Literature 10, Herbert Grabes, ed. (Tiibingen: Aesthetics and Contemporary Discourse, 1994), hlm. 155.
[6] Ibid.
[7] Helga Finter, ibid., hlm. 157.
[8] Ibid.