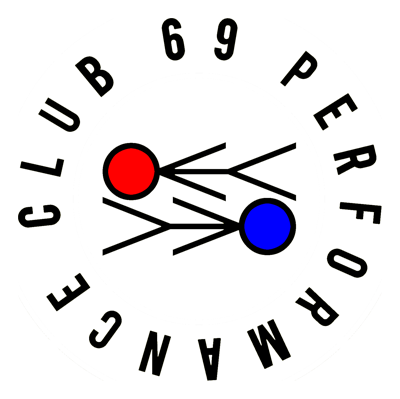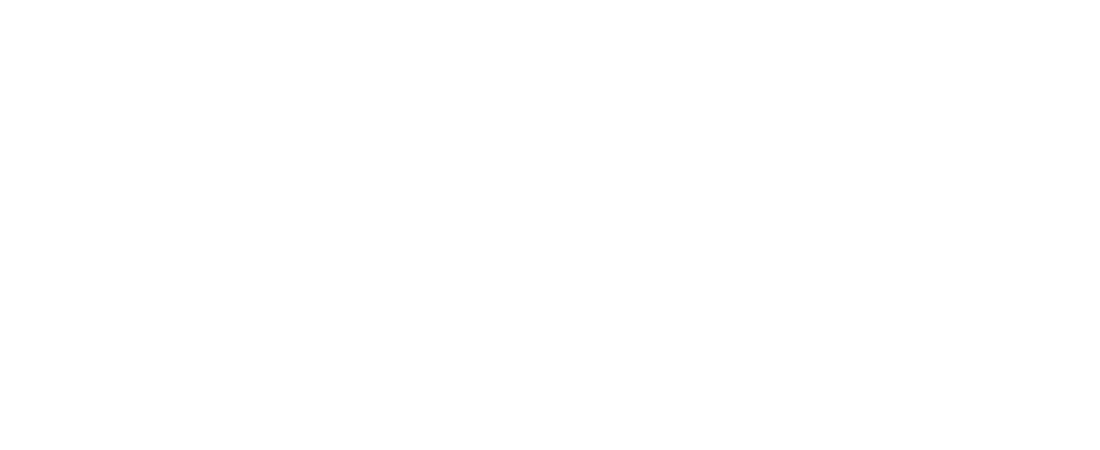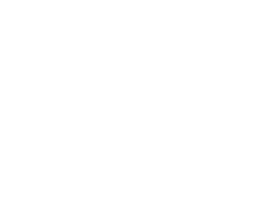KOMUNIKASI JARAK JAUH yang diperantarai teknologi kian menjadi lumrah dari hari ke hari. Relasi manusia dan mesin tak lagi terlihat sebagai sesuatu yang dingin dan objektif, justru menjadi sangat personal, dan ini juga mengubah relasi subjek dengan publik menjadi hubungan yang lebih langsung. Perubahan relasi-relasi ini berusaha diurai oleh Dhanurendra Pandji dalam karyanya, The Other Me. Karya ini dipresentasikan di RewindArt Festival, Universitas Negeri Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2019. Dalam trajektori kekaryaan Pandji, The Other Me adalah titik awal upayanya menggali persoalan replikasi dan representasi, sebelum ia mengulasnya lebih jauh dalam karya-karya fotografi (I Wonder How the Scanner Sees My Body dan Absence) dan gambar bergerak (Scan, Empty Chair, Punishment, dan Moving Image).
Performans ini diadakan di sebuah lorong di gedung Fakultas Seni Rupa UNJ, dengan perangkat yang cukup sederhana. Pandji berjongkok dan meletakkan sebuah pengeras suara nirkabel di tengah lorong. Ia menggunakan ponselnya untuk merekam dirinya yang berbicara dan memainkannya ulang di pengeras suara tersebut. Ia mengambil langkah mundur dan mengulangi kegiatan tersebut, berulang kali, semakin menjauhi pengeras suara. Timbal-balik antara suara Pandji dan suara yang muncul di pengeras suara, ditambah lagi dengan posisi Pandji yang menghadap dan menatap si pengeras suara itu, membuat adegan ini tampak seperti sebuah percakapan antara Pandji dan pengeras suara. Percakapan berlangsung secara dua arah, dengan suara yang sama:
“I can see you.”
“Can you see me?”
“I can hear you.”
“Can you hear me?”
“I’m watching you.”
Penonton memiliki kebebasan perseptif untuk mengikuti performans dari titik mana saja di lorong tersebut. Jika penonton berdiri diam di depan pengeras suara, ia akan melihat Pandji berjalan menjauh, sampai akhirnya ia menghilang di ujung tangga. Sedangkan, jika penonton memutuskan untuk mengikuti gerak Pandji, mereka akan semakin jauh dari pengeras suara, dan gaung ucapan Pandji akan terdengar semakin pelan.
Di sini, terjadi pemisahan antara tubuh dan suara. Suara yang direkam dan ditransmisikan melalui mesin memperoleh nyawanya sendiri, menjadi sebuah gaung. Pada titik terjauhnya, tubuh Pandji menghilang, yang kelihatan di ujung tangga hanya sepasang kaki. Secara fisik, penonton sudah tidak lagi mampu mendengar suara Pandji, namun jangkauan bluetooth masih menyambar, sehingga suara hanya bergaung lewat pengeras suara: “I can see you.” “You cannot see me.” “You are watching me.”



Dhanurendra Pandji, 2019, The Other Me (Dokumentasi: Milisifilem Collective)
Nyatanya, proses-proses penggunaan teknologi dalam performans ini biasa kita lakukan sehari-hari. Subjek menginput data ke dalam mesin, mesin tersebut memprosesnya melalui suatu mekanisme, dan mesin memberikan output yang mampu merespon data yang kita masukkan. Alur demikian paling lazim kita gunakan saat sedang menggunakan media sosial. Unsur “sosial” yang ditekankan di dalamnya mendorong keterbukaan pengguna dalam berinteraksi dan menyingkap informasi pribadi. Setiap interaksi yang kita lakukan di internet merupakan input jaringan pola dan data yang lantas digunakan oleh mesin platform untuk membentuk pengalaman bermedia kita selanjutnya: entah itu dalam rekomendasi topik atau orang untuk diikuti, atau barang untuk dibeli. Sekilas, hasilnya terlihat seperti timbal-balik yang menyenangkan: sebuah komunikasi lancar yang terjadi di dalam “mesin” yang memahami diri kita, mungkin lebih dibandingkan diri kita sendiri. Namun, kenyataannya mesin tersebut melakukan itu semua melalui pengawasan dan perekaman terus-menerus terhadap seluruh gerak-gerik kita.
Hubungan ambigu ini tergambar melalui frasa yang diucapkan dalam performans Pandji, yang berkaitan dengan kegiatan melihat, menonton, dan mendengar. Di satu sisi, memang ketiga mode perseptif itu yang kita gunakan untuk menyimak hal-hal yang sedang terjadi di media sosial. Respon yang dilontarkan balik oleh pengeras suara menandakan adanya inteligensi mesin yang memungkinkan hubungan dua arah antara si mesin dan pengguna. Namun, respon tersebut juga menunjukkan bahwa mode persepsi yang kita gunakan berlangsung secara dua arah pula: saat kita sedang menonton mesin, mesin pun balik menonton kita.
Di luar mesin dan subjek pengguna, ada pihak ketiga, yakni pemirsa. Performans ini memiliki audiens yang menonton, sama seperti layaknya hakikat kanal media sosial yang dapat ditonton siapa pun di seluruh dunia. Komunikasi antara subjek dan mesin pada saat yang sama “tampil” sebagai hubungan yang mengulurkan tangannya kepada publik: karena sifatnya yang terbuka, interaksi tersebut ditujukan untuk dipersepsi, bahkan boleh juga direspon oleh publik. Maka, hal yang menarik terjadi menjelang akhir performans, saat tubuh Pandji semakin menjauh dan hanya menampakkan kakinya saja di ujung tangga, penonton sudah tidak lagi dapat menangkap adanya percakapan dua arah, sementara perhatian sepenuhnya tertuju pada si pengeras suara merapal ucapannya seperti mantra, “You are watching me.” Suara di pengeras suara merujuk kepada penonton yang sedang memerhatikannya, berusaha melibatkan mereka melalui kepandaian komunikasi yang kini ia peroleh dari input data yang dimasukkan oleh subjek pengguna pertama.
Namun, jika performans ini hendak menggambarkan siklus komunikasi yang termediasi oleh mesin atau algoritma, publik masih diposisikan sebagai penonton semata, belum menjadi partisipan yang leluasa sebagaimana komunikasi di media sosial yang cepat sekali menjadi diskursus yang dimiliki oleh publik. Bisa jadi, ini disebabkan oleh kegagalan seniman mengubah paradigma yang ia tetapkan sedari awal. Paradigma “panggung” yang dipaksakan hadir dalam ruang publik menyiratkan suatu hambatan dalam proses negosiasi antara seniman dan ruangnya. Posisi penonton dibiarkan cair mengikuti performans, sehingga apa yang dipersepsi oleh penonton akan berbeda-beda, tergantung pada jarak penonton dengan sumber suara. Perubahan paradigma “panggung” menuju paradigma publik di akhir performans tidak berjalan dengan lancar. Lantas, saat perubahan seharusnya terjadi, penonton tidak mengalami secara total pengalaman performatif yang dituju oleh seniman. Saat kenyataan sensorik yang terjadi (menonton, ditonton, mendengar, didengar) diungkapkan kembali secara verbal, kegagalan mengubah paradigma bentuk tersebut mereduksi performans menjadi didaktif. Pada akhirnya, imajinasi yang terbentuk berjalan satu arah. Penonton diarahkan untuk memahami satu konsep yang diungkapkan dua kali tanpa adanya keterlibatan lebih lanjut dalam mengalami dan memahami konsep tersebut.