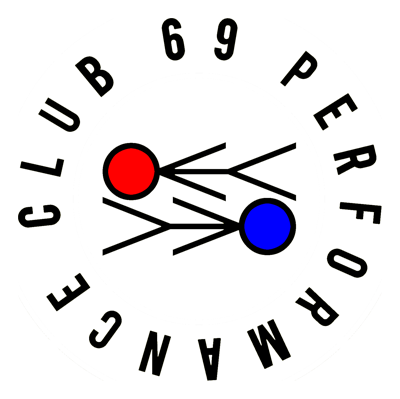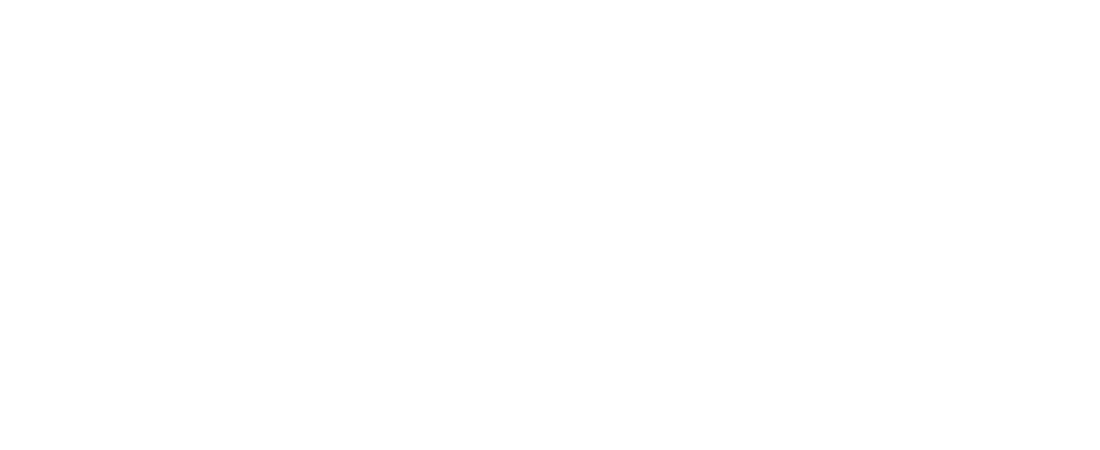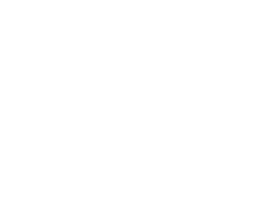Tulisan ini adalah esai yang dibacakan Otty Widasari pada panel diskusi bertajuk “Media Performance” di acara PERFORM, program tahunan Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan, yang memamerkan seni performans bersamaan dengan penyelenggaraan forum diskusi tentang seni performans.
SAYA ADALAH SENIMAN yang melewati masa remaja di era 90-an, dengan latar belakang pendidikan jurnalistik. Pada masa itu, saya tidak banyak bersentuhan denga dunia seni, melainkan hanya menjadi mahasiswa biasa dan mencoba mempelajari dunia jurnalisme, walaupun keinginan saya untuk menjadi seniman sangat kuat. Namun, pemahaman saya terhadap seni sangat minim. Seperti kebanyakan orag tua di Indonesia, orang tua saya tidak mengijinkan saya untuk menempuh pendidikan senirupa, disebabkan lemahnya infrastruktur seni di Indonesia pada masa itu. Bagi orang awam, menjadi seniman seolah terlihat seperti menjalanani sebuah pekerjaan yang jauh dari profesionalisme.
Saya baru mulai mempelajari semua dari awal saat saya sudah berusia 26 tahun, saat saya sudah bekerja di linkungan industri perfileman. Karena merasa tidak cocok dengan sistem industrial tersebut, saya mulai banyak mendatangi event–event senirupa dan mulai rutin mengikuti berbagai diskusi di ranah tersebut.
Pada tahun 2003, saya bersama beberapa teman mendirikan kolektif berbentuk kelompok belajar, bernama Forum Lenteng, untuk mempelajari filem, video, seni, dan media. Misi utama dari membentuk Forum Lenteng berada pada ranah respon dan kritisisme tentang situasi lack of knowledge sebagai imbas dari keterpusatan informasi dan referensi di era dictatorship yang berakhir pada 1998. Maka, kami bergerak seterusnya hingga sekarang dalam jalur pendidikan alternatif untuk mengisi ruang kosong yang tidak dipenuhi oleh institusi pendidikan seni di Indonesia. Layaknya kelompok belajar, kami berusaha menelusuri sejarah, persebaran, dan perkembangan dunia seni dan kaitannya dengan budaya serta media, satu per satu dengan intensif, dengan menampung apirasi dan minat dari tiap-tiap anggota.
Dalam perjalanannya selama 15 tahun, Forum Lenteng berkembang dengan beberapa platform yang terbentuk secara organik sesuai dengan perkembangan kajian yang dilakukan di dalamnya, juga sesuai dengan minat dari para anggotanya yang terus bergenarasi hingga sekarang. Range usia anggota di Forum Lenteng adalah dari 47 tahun hingga yang termuda adalah 18 tahun. Maka, dalam keseharian kami, ruang kerja Forum Lenteng selalu diisi dengan generasi muda dari tahun ke tahun.
Dari sini, saya mempelajari bahwa dalam setiap era di lokasi mana pun, peran generasi muda adalah tonggak awal sebuah kebudayaan, karena generasi muda adalah agen yang paling memahami situasi hari ini.
Saya menyoroti persoalan anak muda di sini, adalah terkait dengan pembahasan saya tentang bagaimana Forum Lenteng memulai sebuah platform bernama 69 Perfomance Club pada 2016, yang memfokuskan diri pada kajian dan praktik performance art di Indonesia.
69 Performance Club berdiri atas inisiatif beberapa anggota Forum Lenteng yang memiliki ketertarikan pada bentuk seni yang memiliki karakter unik, jika ditinjau dari perjalanan kronologisnya sejak dekade 70-an di Indonesia.
Sayangnya, dalam proses belajar yang kami lakukan, kami menemukan sedikit kesulitan dalam mencari pencatatan yang mendalam berbentuk tulisan-tulisan kritis mengenai performance art di Indonesia. Mungkin, itu disebabkan oleh kuatnya tradisi tutur di Indonesia. Hal itu yang paling memicu 69 Performance Club untuk mengukuhkan platform ini sebagai ruang belajar intensif yang memiliki kelengkapan dengan melakukan pembelajaran, pencatatan, pendokumentasian, dan pengarsipan tentang “hari ini” sambil melihat kepada sejarah.
Saat saya mencoba menoleh ke belakang, saya selalu menemukan bagaimana peran anak muda sangat signifikan dalam membuat perubahan, khususnya di bidang seni.

Otty Widasari dan Prashasti W. Putri memberikan presentasi pada Panel Diskusi “Media Performance” di acara PERFORM, Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan.
Chronicle
DALAM KRONOLOGI SEJARAHNYA, performance art Indonesia hadir di dalam skena seni sekaligus di tengah masyarakat dengan usaha menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai di era 70-an, sistem pengajaran di perguruan tinggi seni rupa di Indonesia sangat ketat dengan kurikulum pendidikan yang berbasis Pendidikan Klasik.
Pada masa pemerintahan dictatorship militer di bawah kepimpinan Soeharto, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru (1967-1998), prinsip ‘seni untuk seni’ merupakan ruang tersendiri untuk melakukan praktik depolitisasi, di mana seniman tidak boleh bicara politik, untuk menjaga ketat stabilitas kemanan tanpa kritik terhadap jalannya pemerintahan militeristik. Mengingat seni adalah sebuah medium yang paling leluasa untuk mengusung pesan protes.
Performance art hadir di era tersebut atas prakarsa para mahasiswa dari perguruan tinggi senirupa di Jakarta, Bandung, dan Yogayakarta, sebagai perlawanan terhadap kekakuan sistem pengajaran yang membatasi eksperimentasi seni, karena medium seni yang sangat terbatas hanya pada lukis, patung, dan seni grafis. Selain itu, perlawanan kalangan mahasiswa senirupa di masa itu juga kepada agenda depolitisasi dalam kurikulum pengajaran senirupa di kampus-kampus. Maka, bermunculanlah pemikiran ekspresi senirupa yang mulai mengarah pada bentuk “aksi seni” yang dipertontonkan pada publik, dengan muatan protes yang kental. Ragam bentuk dalam karya senirupa makin mengarah pada bentuk demonstrasi eksekusi maupun realisasi dari seni yang lebih mengarah pada penekanan gagasan dari pada bentuk akhir, dalam sebaran karya-karya yang bersifat instalatif, happening, dan konseptual. Tubuh pun kerap dijadikan medium dalam karya-karya seni. Ini semua sepenuhnya mengadopsi pengetahuan Modern Barat yang berakar pada kemunculan Dadaisme, hingga Fluxus.
Namun, sayangnya, pencatatan atau kajian terhadap pergeseran bentuk ini tak mudah ditelusuri karena tradisi pencatatan, pengarsipan, dan pendokumentasian yang diterima secara acak di Indonesia melalui kolonialisme yang membawa diktat pengajaran modern. Maka performance art sebagai pengetahuan dalam ranah senirupa menjadi minim kajian. Saat ini, hanya bisa saya membacanya sebagai bagian dari gejala senirupa kontemporer.
Aksi bentuk seni yang performatif tersebut mencapai puncaknya pada demonstrasi massa besar-besaran untuk meruntuhkan rezim dictatorship Orde Baru. Performace art yang identik dengan kepedulian sosial-politik dan selalu mengusung ide protes terhadap kebobrokan sistem kekuasaan negara (di samping isu-isu lainnya seperti kerusakan lingkungan, gender, konsumerisme, kapitalisme, dan persoalan-persoalan lainnya), dan memiliki kekuatan yang mampu mendekati publik sekaligus melibatkan mereka, mendapat paggung yang sesungguhnya pada Reformasi Indonesia 1998. Seniman turun ke jalan, menggelar karya-karya performans-nya, bergandengan dengan aksi protes masyarakat di berbagai kota-kota besar, khususnya Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Performance art bercampur baur dengan propaganda pernyataan-pernyataan politik dan properti demonstrasi.
Pada titik ini performance art Indonesia mengalami kerancuan statusnya yang merupakan pernyataan individual seniman, sebagai anak kandung senirupa modern, dengan bentuk demonstrasi yang merupakan ekspresi sosial atau kolektif.
Lagi-lagi, saya kesulitan menemukan pencatatan kompreshensif yang mengkaji tentang aspek estetika dari pergeseran makna seni modern yang diterapkan di ranah lokal Indonesia. Yang jelas lebih mencolok ialah aspek respon dan dampaknya terhadap publik sebagai bagian dari pemicu perubahan sosial, dibanding aspek estetikanya.
Namun, sampai di sini, bisa dilihat bahwa performance art di Indonesai telah menempuh satu tugas avant-gardisme untuk mengembalikan hakikat seni kepada kehidupan.
Mamasuki dekade akhir 90-an, karya-karya performance art di Indonesia tampaknya mengalami pergeseran, walau masih kental mengusung tema-tema politis, ke arah yang lebih eksklusif. Para seniman performance art banyak terlibat dalam event–event berskala regional dan internasional. Pada satu sisi, ini merupakan dampak positif dalam perkembangan skena seni performance art Indonesia, di mana karya-karya para seniman yang berjuang sejak tahun 70-an ini telah mengukuhkan keberadaannya dan mendapatkan pengakuan di area yang lebih luas. Namun, di sisi lain menjadi ironis, karena fitrahnya performance art—yang menolak komersialisasi oleh galeri yang awalnya menjadi objek perlawanan mereka—menjadi bagian dari dominasi sistem yang diberlakukan oleh infrastuktur seni yang dewasa ini mengakomodir semua bentuk kesenian sebagai komoditi dan tontonan. Performance art menjadi sama eksklusifnya dengan karya-karya lukis dan patung yang dahulu dianggap sebagai keterbatasan medium dalam berkespresi.

Otty Widasari dan Prashasti W. Putri memberikan presentasi pada Panel Diskusi “Media Performance” di acara PERFORM, Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan.
Generasi MTV
SEMENTARA, KEMBALI KE persoalan anak muda, pada akhir 90-an, generasi muda era itu memaknai aksi performatif sebagai hal yang dekat dengan gaya hidup sehari-hari. Seiring dengan euforia kebebasan di era reformasi dan budaya televisi yang sangat lekat dengan masyarakat, MTV menjadi model yang dirasa paling mewakili bahasa anak muda. Selain itu, fenomena software bajakan juga memicu kegatelan mengutak-atik teknologi yang erat kaitannya dengan budaya visual. Maka, ekspresi anak muda banyak diterapkan dalam performativitas yang memadukan budaya populer dengan teknologi multimedia lainnya seperti synthesizer, komputer, juga video dan internet. Ekspresi ini dipanggungkan dalam skena clubbing. Bingkaian event seni tidak lagi sakral dan bisa dikatakan menghindar dari pengusungan tema-tema politk. Party di setiap kesempatan, berbaur dengan bingkaian event seni.
Situasi ini justru makin mengaburkan batasan antara seni performans dan gaya hidup populer di kalangan anak muda yang mulai menapaki jejaknya sebagai seniman.
Pada dekade awal 2000-an, banyak bermunculan kolektif-kolektif yang mengedepankan inisiatif seniman (collective as artist’s initiative), sebagai bentuk perlawanan terhadap keterceburan seniman kembali dalam dominasi pasar dan infrastruktur seni mapan. Situasi di masa ini, saya pikir, bukannya menolak galeri secara head to head, melainkan memberi alternatif ruang bagi ekspresi seni yang bersifat kesezamanan.
Namun, dalam tiap eranya, selalu aktivisme yang sama dilakukan para seniman muda aktif di Indonesia, yaitu menolak semua bentuk definisi seni yang terbatas dan cenderung menuju ke arah eksklusivitas.
Melalui perjalanan kurang lebih setengah abad, performance art di Indonesia, karena kedekatannya dengan aktivitas kehidupan dalam arti yang luas, performance artist selalu memiliki peluang untuk mempertanyakan, menghindari, dan menolak konvensi sempit yang membuat pengertian seni semakin mengikat dan berjarak.
Di pertengahan 2000-an, situasi performativitas berkesenian makin melebur dengan sekat-sekat kesenian lain dan bahkan dengan disiplin lain, jadi memengaruhi keragaman gagasan maupun bentuk presentasi performance art.
Semua itu bermuara pada situasi “semua bebas”. Siapa pun bisa jadi seniman. Selesai dalam kecairan, dan usaha yang didorong tetap tidak menghasilkan kajian komprehensif bagi pembelajaran itu sendiri. Situasi yang cukup mengarah pada krisis kedangkalan pengetahuan. Namun, pergeseran performativitas yang dilakukan oleh aksi gaya hidup generasi muda ini bisa saya maknai sebagai sebuah penempuhan tugas kesezamanannya.

Usaha Generasi Performatif
SEBAGARI ORGANISASI YANG secara naturalnya adalah kelompok belajar, bagi Forum Lenteng kecairan ini adalah sebuah situasi yag harus direspon dalam aksi kritisisme, salah satunya dengan membuat platform performance art.
69 Performance Club adalah inisiatif anak-anak muda anggota Forum Lenteng yang lahir sebagai generasi yang tidak lagi peduli dengan market. Generasi ini, para milenialis, membuka matanya saat pertama lahir ke dunia dengan situasi yang berwarna, di mana semua warna tersebut berada dalam satu genggaman tangan bernama remote control. Maka si tombol kontrol ini yang selanjutnya mengembangkan dirinya sendiri sebagai ruang tradisi, yang merupakan wadah budaya yang dihidupi oleh sirkulasi para milenialis kemudian.
Sementara tradisi authorship dari era modern lalu masih menjejakkan kakinya dengan cukup mantap hingga kini, generasi milenium yang serba terhubung dan melegitimasi dirinya melalui jumlah follower dan like, sadar ataupun tidak, masih terpesona oleh tradisi authorship tersebut. Terbukti dengan besarnya minat menjadi performance artist di kalangan generasi muda sekarang ini. Sementara, referensi tentang performance art yang mereka dapat melalui berbagai event yang terlegitimasi di Indonesia masih sangat mengusung semangat avant-garde, walau secair apa pun bentuknya dengan segala perangkat digital dan internet.
Di sisi lain, ada sebuah friksi, yang bisa memberikan gambaran tentang karakter apolitis generasi “Y”. Generasi yang terbiasa menerima afeksi melalui emoticon/emoji, #hashtag, pray for “sesuatu”, ataupun tersanjung oleh “tanda jempol”. Karakter milenialis kebanyakan adalah: bertradisi performatif dengan budaya tampil yang kuat; biasa berekspresi sosial secara termediasi; menjadi bintang karena banyaknya jumlah follower memberi peluang menyumbangkan “like” mereka terhadap tampilannya. Artinya, semua harus terhubung melalui media.
Sementara, performance art di Indonesia masih membutuhkan pembelajaran panjang tentang hubungan tampilan happening dengan publiknya yang berinterasksi secara meruang dan langsung. Sementara, ranah di luar simulatif media tersebut memiliki jenjang pengetahuan yang cukup berbeda, yang telah terlebih dahulu tersusun secara mapan sejak lahirnya modernitas. Maka terjebaklah generasi ini di bawah kutukan mitos kontemporer yang bergulir dalam pesona zaman dan romantisme semangat “kekinian”, yang mengharuskan generasi menjadi sepenuhnya pengguna (users), dan hidup bergulir sesuai dengan pengembangan diri teknologi itu sendiri. Padahal, kita semua tentu ingat bahwa teknologi adalah anak emas kapitalisme. Eksistensi yang terbangun atas dasar bagaimana penilaian subjek lain di ranah jejaring, alias para likers, jempolers, dan komentators, dibenturkan dengan situasi nyata yang jelas mencirikan lokalitasnya. Ciri di dunia tidak terhubung itu, saat dibingkai, dia bersifat satu arah. Sebuah karya performance art terlahir untuk ditampilkan dengan mentalitas satu arah. Dia hanya akan hadir di dunia maya untuk menjelma menjadi sebuah produk simulasi. Dia harus menanggalkan sifat-sifat lamanya yang sakral, karena bahkan dia bisa ditonton dalam layar telepon pintar.
Oh Parmitu (atauThe Supper, 2018) karya Otty Widasari, dipresentasi di Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan, dalam rangka acara PERFORM.
Kode Baik (atau Good Code, 2018) karya Prashasti W. Putri, dipresentasikan di Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan, dalam rangka acara PERFORM.
The Three Percuss (2018) karya Pingkan Polla, dipresentasi di Ilmin Museum of Art, Seoul, Korea Selatan, dalam rangka acara PERFORM.
Jadi, bagaimana sebuah karya performance art bisa menjadi demikian relevan untuk diminati kalangan muda, jika bisa dibilang para milenialis tidak percaya lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah; mereka lebih percaya kepada user generated content (UGC) atau konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan, dan berdialog secara peer-to-peer?
Pembacaan terhadap hal ini menuntut pemahaman bahwa audiens performance art adalah merupakan bagian dunia yang termediasi pula. Semua orang terhubung dan semua orang di era internet adalah audiens yang mengonsumsi konten sekaligus memproduksi konten.
Lalu di mana posisi performance art di era milenium ini?
Mungkin dia berada di situasi pencarian makna yang sia-sia oleh manusia, dalam menghadapi dunia yang tidak dapat dipahami.
Menggunakan analaogi dari mitologi Yunani, saat Sisifus harus menjalankan kutukannya menggulingkan batu karang ke atas bukit kemudian menggulingkannya kembali ke bawah, Albert Camus melihatnya bukan sebagai kesia-siaan, melainkan sebuah perjuangan, karena menurutnya perjuangan sudahlah cukup untuk mengisi hati manusia. Maka kita harus membayangkan Sisifus bergembira, bukan terkutuk. Mungkin kita harus bergembira merayakan teknologi dan aplikasi hari ini, daripada menjadi pengguna berat yang dimanfaatkan oleh ranah kapital. Mari bayangkan absurditas mendorong-dorong batu ke atas gunung untuk digulingkan kembali ke bawah itu seperti sebuah perjalanan bolak-balik kerja media yang absurd juga, yang menyetir manusia milenium untuk terus bergulir sebagai user tanpa peduli apa yang sedang dilakukannya. Yang dibutuhkan adalah pemberontakan, karena ada bentangan sejumlah pendekatan terhadap kehidupan yang absurd. Jangan-jangan pendekatan tersebut, terhadap hidup yang absurd mana pun, yang kemudian menjadi tradisi, adalah dengan pendekatan yang bisa mengganggu atau memprovokasi kebiasaan tersebut.
Mungkin, kita harus melihat dengan perspektif bahwa, sesuai sifat dasarnya, manusia terus mencari makna dalam kehidupan, dan perjuangan itu dibingkai dalam karya-karya yang mencoba melihat hubungan dunia absurd dengan pendekatan absurd lainnya. Karena absurditas adalah alasan jernih untuk mengingatkan kita akan batas-batas. Karena manusia hidup bertatapan dengan berbagai hal yang tak masuk akal, tentunya dia merasakan kerinduan pada kebahagiaan yang disebabkan oleh akal. Aksi-aksi kreatif, yang jika terus diaktivasi menjadi kebudayaan, akan menebas belantara ketidaktahuan. Inilah mengapa sebuah ciptaan atau karya yang berpengetahuan adalah sebuah hadiah indah bagi masa depan. Mungkin para performance artist hari ini bisa mewacanakan hal ini melalui karya-karyanya.
Maka, platform 69 Performance Club dihadirkan untuk membaca hal tersebut, sekaligus melakukan praktik pembelajaran dan melakukan penyeimbangan dengan memproduksi karya-karya oleh para seniman yang terlibat di dalamya. Misi utama dalam proses ini adalah memberi alternatif dari sistem skena seni yang sekarang berlaku (khususnya di Indonesia), kembali mempertanyakan komodifikasi seni, dan bersikap kritis terhadap budaya internet dan social media sekarang. Selain itu, social media berperan sebagai metode untuk membesarkan platform ini sendiri. Respon publik merupakan salah satu metode survive yang dilakukan dalam hal ini, selain ke-saling integral-an antar platform lain yang ada di Forum Lenteng, untuk menjangkau publik yang lebih luas. *