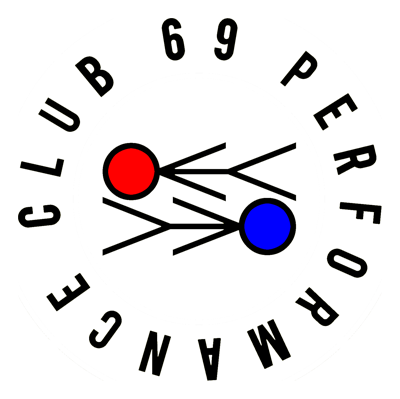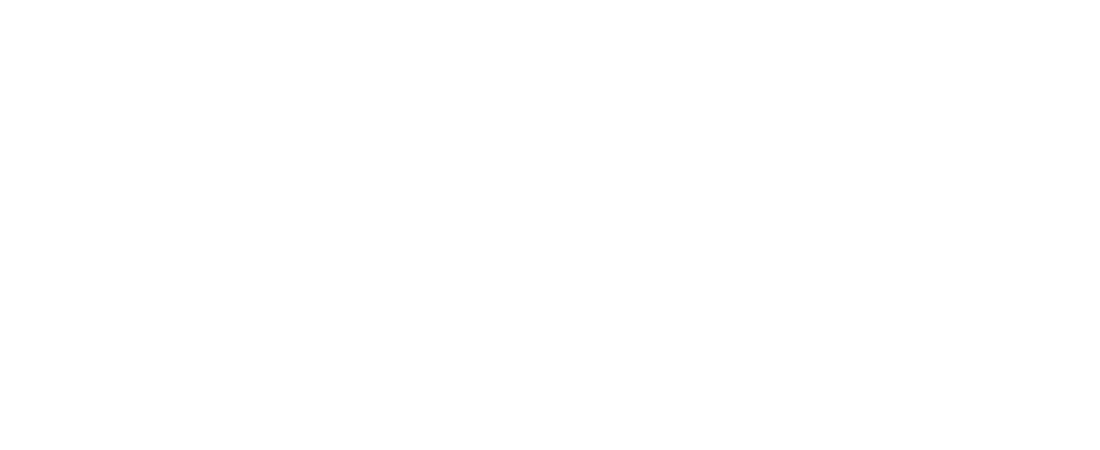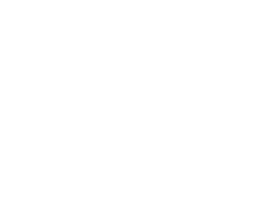Suasana pembukaan acara perdana 69 Performance Club di Forum Lenteng, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2016 (Foto: Forum Lenteng).
HANIF ALGHIFARY, DI hari-harinya tahun 2016, adalah seorang pegiat DIY dan sempat terlibat mengurus Visual Jalanan, sebuah platform jurnal online yang merekam dan mengarsipkan budaya visual yang ada di jalanan. Salah satu kegiatannya kala itu adalah mengelola Toko Store, sebuah unit usaha kecil milik platform tersebut; menjual baju kaus produksi Visual Jalanan. Urusan lipat-melipat dan mengepak baju adalah rutinitas Hanif. Agaknya, inilah yang melatarbelakangi ide karya seni performansnya yang pertama di 69 Performance Club, yang dipresentasikan pada tahun itu di Forum Lenteng, Jakarta.
Dalam kaitannya dengan isu yang jauh lebih besar, Hanif sebenarnya ingin berbicara tentang masalah domestik—membingkai kegiatan rumah tangga. Karena itu, kegiatan lipat-melipat baju yang ia angkat menjadi karya seni performans berjudul Untitled #1 (2016) itu, dipadukan dengan kegiatan lain yang paling umum dikenal sebagai salah satu bagian dari keseharian rumah tangga, yaitu menyetrika baju.
Dalam Untitled #1, Hanif menggunakan 35 baju kaus dan sebuah setrika. Mengambil salah satu sudut di teras belakang kantor Forum Lenteng, ia menumpuk semua baju itu di atas sebuah meja panjang, sedangkan setrika di dekatnya sudah tersambung ke sumber listrik. Pengaturan ruang pun sudah dilengkapi dengan sebuah kamera yang akan merekam aksi performans Hanif. Ini dimaksudkan agar orang-orang juga bisa menyaksikan aksi Hanif di layar tayang di ruangan lain, tidak mesti menyaksikannya langsung di depan si seniman.
Ia memulai performansnya dengan mengenakan satu per satu baju-baju itu ke tubuhnya, berlapis-lapis. Setelah semua baju terpasang dan tubuhnya tampak gemuk, selanjutnya Hanif menggunakan setrika: ia menyetrika baju yang masih berada di badannya. Juga dengan satu per satu, Hanif melepas setiap baju yang sudah disetrika di atas badannya itu, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di meja lain yang berukuran lebih kecil. Di ujung penampilannya, baju yang sebelumnya ditumpuk terbuka, kini ditumpuk dengan tatakan dan lipatan yang rapi.

Jika kita bertanya, apa yang unik dari sebuah karya seni performans (dan secara lebih spesifik, apa yang membedakannya dari seni-seni pertunjukan lainnya, misalnya teater), untuk memaparkannya dengan sederhana, kita boleh meminjam jawaban Marina Abramović yang cukup populer: seorang seniman performans harus membenci teater. Karena, baginya, apa yang ada di teater adalah palsu, tidak nyata. “The knife is not real, the blood is not real, and the emotions are not real. Performance is just the opposite: the knife is real, the blood is real, and the emotions are real.” (Abramović, 2010). Ini diajukan dalam rangka berurusan dengan apa yang dapat disebut Abramović sebagai “realitas sejati”, dan untuk hal itu, seni performans kerap “mengorbankan” hal fisik dan psikologis untuk tujuan artistiknya. Itu semua dilakukan demi, sekali lagi meminjam jawaban Abramović, menguji batas diri sendiri untuk kemudian mentransformasinya (ibid.). Sehubungan dengan “perubahan” yang ingin dicapai tersebut, Abramović beranggapan bahwa seorang seniman performans juga bisa mengambil energi dari audiensnya, terutama ketika sebuah karya (efeknya) mengarah kembali ke penonton dengan cara yang berbeda, juga untuk tujuan mentransformasi keadaan yang ada pada audiens. Selain itu, demi mencapai transformasi yang diharapkan, Abramović meyakini bahwa sebuah karya seni performans mestilah bersifat “besar”, dalam artian bukan harus berwujud gigantik, tetapi lebih kepada soal kemampuannya memunculkan efek besar yang bisa “mengganggu” [zona nyaman] penonton. Salah satu pendekatan yang dapat diupayakan untuk “transformasi nyata” itu, menurutnya, adalah dengan menciptakan/melakukan karya seni performans berdurasi panjang.



Kita bisa membayangkan gagasan Abramović di atas dengan menelaah dan merefleksikan karya pertama Hanif ini. Jika kita menilainya dari perspektif isu, yakni isu domestik, Untitled #1 tampaknya tidak bersuara lantang, baik itu dalam hal mengkritisi isu tersebut maupun untuk menyuarakan pernyataan politis tertentu mengenainya. Namun memang, bagi saya, yang menarik dari karya ini bukan kedalaman isunya, melainkan upaya transfigurasi aktivitas keseharian ke ranah peristiwa performatif yang “membosankan”.
Pengulangan dari gerakan memasang, menyetrika, dan melepas baju yang dilakukan tubuh Hanif, dalam waktu yang cukup panjang, menguatkan nilai kebosanan yang saya maksud itu. Dari sudut pandang tertentu, perlu diakui bahwa hal itulah yang dikejar dan ingin dicapai karya ini. Dengan kata lain, aspek durasional dan repetitif adalah dua hal pokok yang tengah dibicarakan oleh Hanif. Dapat dimaklumi kemudian, mengapa si seniman menyiapkan sebuah kamera yang merekam secara langsung aksinya: penonton yang tidak ingin berlama-lama menunggu performansnya hingga selesai, dapat meninjau perkembangan aksinya melalui layar tontonan yang ditempatkan di ruangan lain. Dalam pelaksanaannya di Forum Lenteng pun, karya Hanif digilir di awal acara, dan ketika aksinya telah berjalan beberapa menit, penyelenggara acara lanjut mengumumkan giliran penampilan seniman berikutnya. Aksi Hanif itu tetap berlangsung terus sementara penampilan-penampilan dari seniman lainnya berjalan. Penonton dapat memilih, apakah ingin menyaksikan langsung penampilan Hanif secara utuh atau meninggalkannya sebentar untuk melihat penampilan lain, dan meninjaunya kembali beberapa menit kemudian atau sekadar menyimak kelanjutannya di layar tontonan saja.
Dalam hemat saya, persoalan durasi dalam konteks Untitled #1-nya Hanif ini mencerminkan fleksibilitas karya seni performans. Aspek ini merupakan ciri umum yang kerap dipakai untuk membedakan seni performans dari seni pertunjukan (performing arts) dan teater, yaitu penonton tidak diikat oleh kewajiban untuk menonton durasi yang utuh.[1] Sebagai sebuah konsep, “ketidakwajiban” ini adalah hal yang esensial, karena seni performans berpangku pada peristiwa, bukan naratif. Kesengajaan dalam membuka kemungkinan “untuk terlewat disimak” oleh penonton merupakan antitesis dari kerangka konvensional yang dahulunya melekat pada peristiwa-peristiwa atau tontonan-tontonan artistik. Sebab, “peristiwa yang terlewat” (gagal ditonton audiens) itu sendiri merupakan sebuah peristiwa pula.
Terkait dengan hal di atas, karya seni performans “membosankan” ini juga bisa dibilang turut mempersoalkan aspek daya tahan (endurance)—faktor utama dan paling umum dibicarakan dalam karya-karya seni performans—dari dua sisi, yaitu daya tahan pada tubuh si penampil dan daya tahan pada diri audiens performans. Durasi yang panjang, sebagaimana yang sudah dibahas di atas, agaknya merupakan salah satu elemennya, tetapi hal ini tentu saja baru bisa ditegaskan dengan mengesampingkan fakta artistik Untitled #1 yang membolehkan penonton memilih antara menonton penampilan secara utuh atau tidak. Namun, jika pun aspek durasional ini terpaksa gugur karena adanya fakta tentang aturan yang membebaskan audiens untuk memilih cara dan durasi menonton, perihal daya tahan yang saya maksud tetap tampak dan terbingkai dari intensi Hanif yang mencoba memancing ketegangan tertentu di kepala penonton melalui penggunaan setrikanya: setrika sungguhan dengan sambungan listrik yang juga bukan pura-pura.
Dari tampilan tubuh yang gemuk karena baju yang dikenakannya berlapis-lapis, perlahan-lahan setrika tersebut mulai mendekati kulit Hanif karena satu demi satu baju dilepaskan. Penonton diganggu dengan kemungkinan rasa sakit yang akan dialami Hanif dipenghujung performans. Puncaknya bukan terletak pada apakah peristiwa mengalami rasa sakit itu benar-benar terjadi atau tidak di ujung penampilannya, tetapi justru pada proses ketika para penonton menunggu-nunggu dan bertanya-tanya tentang kemungkinan kejadian itu. Kegamangan penonton, atau mungkin rasa kesal yang barangkali muncul selama proses menunggu itu, adalah peristiwa performatif lainnya yang menjadi bagian dari penampilan karya. Dalam situasi ini, kondisi audiens dipaksa untuk bertransformasi ke “ketidaknyamanan”.
Kegelisahan yang dialami penonton, seiring dengan kekhusyukan Hanif mengulang kegiatan memasang, menyetrika, dan melipat baju ke, di, dan dari tubuhnya itu bersifat langsung dan riil, terjadi dalam situasi yang steril dari pengadeganan berbasis skenario/karangan yang umum dilakukan dalam tradisi teater. Bisa dikatakan, karya ini merupakan contoh dari penerapan faktor transformatif yang dimaksud oleh Abramović. Durasi panjang, efek bosan, aksi mengulang, dan alur yang menegang, adalah bentuk-bentuk penting yang bisa membangun dramatika dan gramatika sebuah karya seni performans. *
Catatan Kaki
[1] Namun, perlu dicatat bahwa perkembangan disiplin teater dan seni pertunjukan pada hari ini juga telah memungkinkan pendekatan yang sama, bahwa penonton diposisikan dalam situasi yang bebas dalam konteksnya menyimak karya. Perkembangan tersebut, tentu saja, juga dipengaruhi oleh perkembangan seni performans dan seni kontemporer.
Bibliografi
Abramović, M. (3 Oktober 2010). Interview: Marina Abramović. (S. O’Hagan, Interviewer) The Guardian. Diakses dari situs web The Guardian pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 16:00 WIB.