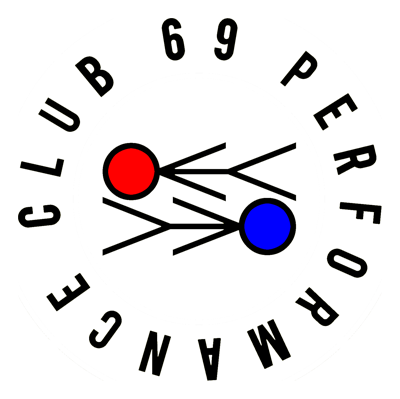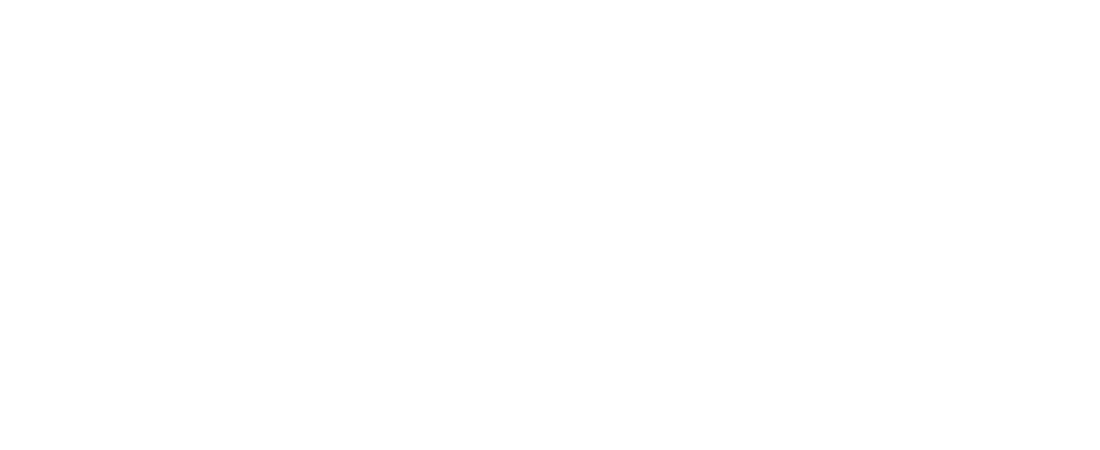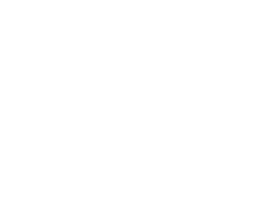DI TAHUN 1934, Walter Benjamin merombak pengertian dari kepengarangan, kesenimanan, dan proses penciptaan karya seni. Dia menantang status quo para pengarang dengan menyatakan bahwa, betapa pun revolusionernya kecenderungan politik para pengarang, karya mereka bisa berfungsi kontrarevolusioner selama masih mengalami solidaritas bersama kaum proletar secara ideologis saja, bukan sebagai seorang produser. Pernyataan ini dicetuskan dalam rangka mendudukkan kembali posisi seniman di dalam alur dan rantai produksi; ia menyerukan bahwa para pengkarya semestinya menularkan/menyebarkan alat produksi sekaligus mengubahnya semaksimal mungkin ke arah usaha-usaha untuk kepentingan sosialisme.
Terkait hal itu, ia mengambil contoh disiplin fotografi. Menurutnya, gerakan Objektivitas Baru (Neue Sachlichkeit) di Jerman memang menekankan “…fungsi ekonomi fotografi untuk menghadirkan kepada massa elemen yang sebelumnya tidak dapat mereka nikmati … dengan mengolahnya kembali sesuai mode saat ini” (Benjamin, 1999, hlm. 775). Penekanan itu juga bisa dipahami sebagai pendayagunaan “…fungsi politik dari fotografi untuk memperbaharui dunia sebagaimana adanya dari dalam” (ibid.). Namun, praktik gerakan ini, bagi Benjamin, masih semata menyebarkan alat produksi tanpa mentransformasinya. “Apa yang harus kita tuntut dari fotografi adalah kemampuan memberikan caption pada cetakan yang akan merobeknya dari klise modis dan memberinya nilai guna revolusioner” (ibid.).[1] Apa yang dimaksud oleh Benjamin ialah upaya untuk menerabas batas antara “tulisan” dan “gambar”.
Kita barangkali akan lebih paham ketika menyimak bagaimana Benjamin memposisikan Teater Epik (Epic Theatre)-nya Bertolt Brecht sebagai model (atau pendekatan) dari keperpaduan antara tujuan politis (political tendency) dan tujuan literer (literary tendency) yang maksimal, yang dapat memenuhi fungsi organisasional dari sebuah karya seni; karya yang melaluinya si seniman bisa menawarkan suatu tindakan indikatif (bergejala) dan patut dicontoh; karya yang bisa membuat orang-orang keluar dari keberadaannya sebagai sekadar penonton/pembaca/penyimak. Brecht, melalui Teater Epik, menurut Benjamin, “mentransformasi hubungan fungsional antara panggung dan publik, teks dan produksi/performans, sutradara dan aktor,” dan pendekatan ini lebih menekankan usaha untuk “menghadirkan sebuah situasi” daripada sekadar “membangun sebuah aksi” (Benjamin, 1999, hlm. 778). Untuk mencapai itu, baik Benjamin maupun Brecht setuju bahwa aksi[2] (bisa juga kita sebut “adegan” atau “naratif”) mesti diledakkan, dipecah, atau diganggu. Bagi mereka, gangguan ini dilakukan demi menentang terus-menerus ilusi teatrikal yang kerap diterima/dialami publik (audiens).

Whitening, 2016, Rambo Rachmadi. (Foto: Forum Lenteng)
Mari kita beralih sebentar dari latar belakang pemikiran di atas. Di esai ini, saya tidak akan berbicara tentang teater, apalagi sosialisme. Karya yang ingin saya ulas pun, perlu saya garisbawahi (berdasarkan pendapat saya pribadi), masih terbilang jauh dari angan-angan semacam itu, cita-cita untuk mendudukkan “pengarang sebagai produser”. Senimannya juga bukan aktivis buruh. Yang ingin saya paparkan ialah sebuah karya seni performans yang agaknya lebih relevan bagi situasi masyarakat konsumeris alih-alih proletar. Namun, Whitening (2016) karya Rachmadi a.k.a. Rambo, yang dipresentasikan dalam kuratorial bertajuk Menelisik Tubuh di Forum Lenteng, Jakarta, pada tanggal 9 Februari 2016, yang menjadi objek bahasan saya di sini, setidaknya bisa merenyahkan elaborasi kita terkait gagasan mengenai “teks” yang dimainkan dalam suatu “tindakan performatif”. Upaya karya ini, dalam derajat tertentu, menggemakan kecenderungan politis dan literer sekaligus, serta mendemonstrasikan salah satu eksperimen tentang “teknik interupsi” di dalam konteks karya seni performans.
Sebelum membahas karya tersebut lebih jauh, kita masih perlu menyertakan kerangka gagasan lain sehubungan dengan gagasan Benjamin di awal. Yaitu, konsep operatif yang dikemukakan oleh Sergei Tretyakov (yang juga disinggung oleh Benjamin di dalam esainya yang saya kutip). Gaya tutur atau gaya ungkap operatif yang dibayangkan Tertyakov, menurut sejumlah literatur, berkaitan dengan kemampuannya mentransformasi sikap (bahkan juga memobilisasi aksi) massa. Tapi, hal ini baru akan dicapai jika si penutur/pengungkap bahasa artistik benar-benar memahami logika dan keseharian massa (karena itu, Tretyakov menyerukan agar para seniman hidup bersama publik—dalam konteks masyarakat sosialis nan progresif, yaitu hidup bersama buruh, dan bahkan turut menjadi buruh yang sesungguhnya).
Konsep yang diajukan Tretyakov tersebut sebenarnya berhubungan dengan potensi dari produk-produk massal, semacam pers dan film, yang kehadirannya (atau penciptaan produk-produknya) tidak semata hanya “milik seniman individual”, tetapi merupakan output dari suatu rantai produksi dan jaringan kerja (labour) di dalam masyarakat yang didominasi oleh sistem kapitalis. Tretyakov mencita-citakan buruh yang bisa memproduksi sendiri pers dan filmnya secara progresif untuk kepentingan revolusioner. Mengamini hal itu, Benjamin melihat bahwa pers mempunyai potensi untuk memungkinkan publik (pembaca) bertindak sebagai “pengarang” (author) juga, karena teknologi dan sistem publikasi pers mempunyai fitur yang menampung aspirasi warga (semisal, surat pembaca dan kolom opini). Pers dan film, atau berita, membuat publik terlibat secara lebih intens di kehidupan keseharian mereka dibandingkan dengan karya-karya lain.
Sehubungan dengan latar profesinya sebagai budayawan dan sastrawan, Tretyakov menganggap pers (dan praktik jurnalistik) sebagai medium yang ampuh untuk mengembangkan “seni masyarakat”. Tapi kita perlu mengingat bahwa, apa yang disebut operatif, menurut Tretyakov, berada pada titik pertemuan antara sastra dan jurnalisme. Yury Tynyanov dalam Literary Fact (1924), esai yang kepadanya konseptualisasi “faktografi” (pengembangan dari konsep operatif itu) berhutang (Devin Fore, 2006, hlm. 4), menyatakan bahwa betapa pentingnya kita untuk melihat dan mengakui teks-teks di dalam jurnal (koran) dan almanak (primbon) sebagai suatu “fakta sastra” juga (lihat Tynyanov, 2000, hlm. 29-49). Pernyataan Tynyanov ini memberikan peluang bagi sumber-sumber atau produk-produk tulisan apa pun untuk dapat diakui sebagai/oleh “sastra” (“seni”), sehingga kita tidak lagi memahami sastra sebagai bidang yang hanya terbatas pada cakupan “karya tulis seorang pengarang”.
Kembali kita kepada karya Rambo. Apa yang dapat disebut “produk massal” dalam rangka menghadirkan konteks massa/publik di dalam Whitening adalah sabun pembersih wajah.

Whitening, 2016, Rambo Rachmadi. (Foto: Forum Lenteng)
Di dalam karya seni performansnya itu, Rambo menggunakan beberapa merek sabun pembersih wajah. Rambo sungguh-sungguh beraksi menggunakan sabun-sabun itu ke wajahnya, satu per satu. Ia mencuci wajahnya dengan air, mengoles sabun pertama, lalu membaca dengan suara lantang teks yang terdapat di sampul botol sabun tersebut, yaitu teks yang menerakan nama-nama zat yang terkandung di dalam cairan kimiawinya. Rambo melafalkan istilah-istilah berbahasa asing itu dengan terbata-bata, atau lebih tepatnya dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang amburadul. Setelah selesai dengan sabun pertama, ia mencuci wajahnya lagi dengan air, dan mengoleskan sabun kedua, lantas membaca teks-teks yang tertempel di botol kedua. Begitu terus hingga beberapa kali, hingga semua sabun yang sudah ia siapkan tuntas digunakan.
Menilai dari perspektif karya ini, perlu kita akui bahwa posisi Rambo bukanlah buruh, melainkan individu di antara semua masyarakat pengguna sabun (warga konsumen). Dia menghadirkan dirinya sebagai konsumen alih-alih produsen ataupun pekerja. Faktanya, Rambo tidak mendorong dirinya dan orang-orang/massa untuk membuat sabun pembersih wajah, apalagi dalam rangka “aksi seni progresif demi sosialisme”, tapi justru menegaskan dirinya sebagai perwakilan masyarakat konsumeristik. Ia sedang membingkai rutinitas warga kontemporer sebagai sebuah peristiwa artistik melalui tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, meskipun aksi ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai seniman—yang juga tidak berada di ranah gagasan untuk mereposisi statusnya dari seorang author menjadi producer (sebagaimana yang dicita-citakan oleh Benjamin)—Rambo tetap membentangkan suatu kontekstualisasi pengalaman massa ke dalam karyanya, dan bukan mengalih-lenakan audiens ke “apa yang cantik dari keseharian”. Apa yang ia lakukan adalah apa yang dialami publik, dan tindakan ini merupakan suatu idiom yang begitu dekat dengan audiens. Tindakan Rambo, boleh dikatakan, menjadi cermin bagi penonton. Namun, sebagai “tindakan demi peristiwa performatif”, Whitening perlu dilihat—sebagaimana Brecht menyikapi teater—sebagai sebuah “produksi”—sebuah “performans”.[3] Lewat konteks itu, kita boleh saja menginterpretasi tindakan performatif Rambo—yang menghadirkan kegiatan sehari-hari itu senyata dan sefaktual mungkin—layaknya artikel berita yang mewakili keseharian publik. Tindakan Rambo, dan peristiwa yang muncul dari tindakan itu, bukan membangun naratif sebagaimana pengertian usangnya, juga bukan untuk “mereproduksi” kenyataan. Kegiatan menggunakan sabun pembersih wajah adalah upaya untuk menghadirkan situasi, menunjukkan fakta, lantas mengungkap (kebenaran)-nya. Yaitu, fakta tentang keseharian, fakta tentang zat-zat kimiawi yang digunakan warga konsumen, fakta tentang kemungkinan sebab-akibat dari penggunaan zat-zat itu pada tubuh.
Dapat dilihat, untuk mengungkap hakikat dari situasi keseharian tersebut (yaitu, situasi dari “menggunakan sabun pembersih wajah”), Rambo seakan mengadopsi teknik gestus-nya Brecht sehingga menciptakan peristiwa “montasional” (modus naratif yang berlandas pada jukstaposisi dua elemen, entah itu gambar, teks, kejadian, dll., di dalam suatu runutan). Ini merupakan aspek yang menunjukkan signifikansi dari penggunaan teks yang dilafalkan oleh Rambo.
Kita bisa menguraikan bahwa struktur Whitening terdiri dari dua elemen. Pertama, ialah tindakan tubuh si penampil yang menggunakan sabun. Kedua, ialah teks yang diujarkan si penampil. Dalam sudut pandang gestus, kita bisa menyebut bahwa elemen yang kedua menginterupsi jalannya elemen yang pertama; kegiatan menggunakan sabun diinterupsi dengan tindakan mengujarkan kata-kata dari teks yang ada di botol. Ujaran-ujaran dari mulut Rambo itu bagaikan caption yang memberi nilai baru tindakannya. Teks bergabung dengan visual/peristiwa. Oleh Rambo, teks tersebut diperistiwakan, dideklamasikan (layaknya puisi), dengan kesadaran dan untuk tujuan literer. Interupsi menggunakan teks inilah yang menginisiasi “ledakan”, atau berperan sebagai jeda untuk membiarkan penonton mencerna “pernyataan artistik” si seniman.
Dengan menghadirkan situasi melalui konstruksi seperti itu, jika kita meminjam sudut pandang Brecht dalam Teater Epik, Rambo sesungguhnya tengah melibatkan publik. Akan tetapi, bentuk pelibatan ini bukan dalam arti mengikutsertakan audiens ke dalam aksi/peristiwanya, melainkan dengan memberikan jarak—untuk berpikir dan mencerna situasi yang mereka lihat. Rambo membingkai kegiatan sehari-hari yang begitu dekat dengan audiens itu justru dalam rangka “menjauhkannya” sejenak dari mereka. Rambo seakan melakukan zooming out sehingga hal yang dekat dapat ditinjau secara utuh dan objektif. Seperti tujuan Teater Epik, karya seni performans ini “…memperlakukan elemen realitas sebagai sebuah rangkaian eksperimen” (Benjamin, 1999, hlm. 778). Dengan kata lain, tindakan performatif Rambo di dalam Whitening adalah sebuah proses (dengan demikian: “produksi”); proses yang memungkinkan penonton “…melihatnya sebagai situasi nyata, bukan dengan kepuasan diri, melainkan dengan keheranan” (ibid.). Seperti penilaian Benjamin terhadap Teater Epik, efek dari eksperimen semacam ini barangkali tidak akan ditemukan pada saat “proses produksi peristiwa” itu dilakukan, tetapi niscaya tercipta di akhir peristiwa/penampilan, yaitu sebagai suatu dampak yang melekat di kepala audiens: mungkin pertanyaan, kegelisahan, keanehan, atau ketidaknyamanan. Mengadopsi kalimat Fore (2006, hlm. 5), konsep operatif—yang berkembang menjadi konsep faktografi—menganggap situasi atau fakta sebagai sebuah outcome dari proses produksi. Dalam hal ini, “situasi performatif” Rambo, dapat dikatakan, adalah sebuah gaya ungkap yang operatif karena Whitening berpijak pada pengalaman nyata audiens, yang mana pengalaman itu tidak dibangun sebagai ilusi teatrikal, tidak dikarang, tapi sebagai fakta, dan si penampil cukup berlaku sebagaimana konsumen biasanya, tapi juga sebagai konsumen yang tengah menyadari akan apa yang ia konsumsi. Situasi dan fakta itu, sebagai konsekuensinya, menjadi hal yang patut ditinjau kembali oleh audiens.
Kesadaran si seniman untuk mendayagunakan teks (bukan teks-teks sastra melainkan teks-teks dari produk massal) itu mencerminkan tujuan literer. Pada contoh kasus Whitening ini, kita bisa melihat bagaimana kesadaran untuk membingkai “fakta sastra” (atau “kualitas literer”) dari teks-teks di luar disiplin sastra, menjadi dasar untuk menciptakan kesadaran politis. Karya seni performans Rambo ini, dengan kata lain, berbicara tentang politik budaya massa di ranah kehidupan masyarakat konsumen. Akan tetapi, fakta ini adalah hasil dari proses produksi, yang terkonstruksi. Tanpa pengujaran teks, barangkali peristiwa menggunakan sabun pembersih wajah itu hanya akan menjadi fakta gamblang tanpa suatu pernyataan yang ditegaskan. Teks tersebut hadir dalam rangka politis, yang diujarkan untuk menguak “politik fakta” yang disituasikan ke dalam seni performans.
Rambo nyatanya memang bukan aktivis yang menggerakkan masyarakat, apalagi anarkis yang merebut alat-alat produksi, juga bukan produser yang mengubah alat produksi untuk kepentingan sosial. Akan tetapi, dia adalah si penampil yang melakukan interupsi, yang mengingatkan audiens melalui tubuhnya, mengenai kebenaran dan fakta sehari-hari yang diketahui tapi kerap diabaikan. Aksi menginterupsi inilah, yang dilakukan dengan basis “fakta sastra” (dari teks yang ia baca), yang membuat tindakan performatifnya itu juga menjadi “aksi politik”.
Whitening adalah sebuah karya seni performans yang mempunyai kemungkinan untuk bisa membentuk sikap audiens; karya yang mentransformasi kesadaran publik meskipun tidak dimaksudkan sebagai karya progresif yang revolusioner. Bagaimanapun, karya ini mencontohkan salah satu pendekatan terkait pendayagunaan teks di dalam seni performans, yang salah satu efeknya adalah “interupsi performatif”—mengikat retorika lebih pada tujuan afektif ketimbang persuasif. Meskipun mungkin belum memenuhi apa yang dituntut oleh Benjamin dan Tretyakov, Whitening di mata saya tetap menunjukkan kecenderungan politis dan literer yang mereka dambakan itu. *
Endnotes:
[1] Cetak miring berasal dari saya sendiri untuk memberikan penekanan.
[2] Istilah ‘aksi’ yang digunakan Benjamin dalam memaparkan pemikiran Brecht itu tentunya mempunyai kaitan dengan konteks teater. Diterjemahkan dari kata ‘Handlungen’ yang bisa berarti action, act, plot, atau story di dalam bahasa Inggris.
[3] Dalam dua versi terjemahan yang berbeda, kata Aufführung di dalam esai Walter Benjamin yang berjudul “Author as Producer”, diartikan sebagai “production” (menurut terjemahan John Heckman, lihat https://www.marxists.org/reference/archive/benjamin/1970/author-producer.htm), juga sebagai “performance” (menurut terjemahan Rodney Livingstone, dalam Selected Writings, vol. 2, bag. 2, hlm. 778).
Bibliografi
Benjamin, W. (1999). The Author as Producer (Address at the Institute for the Study of Fascism, Paris, April 27, 1934). Dalam W. Benjamin, & H. E. Michael W. Jennings (Eds.), Selected Writings (R. Livingstone, Terj., Vol. 2, hal. 768-782). Cambridge & London: Belknap Press.
Fore, D. (2006). Introduction. October, vol. 118, Soviet Factography, hlm. 3-10.
Tynyanov, Y. (2014). The Literary Fact. Dalam D. Duff (Ed.), Modern Genre Theory (hlm. 29-49). London & New York: Routledge.