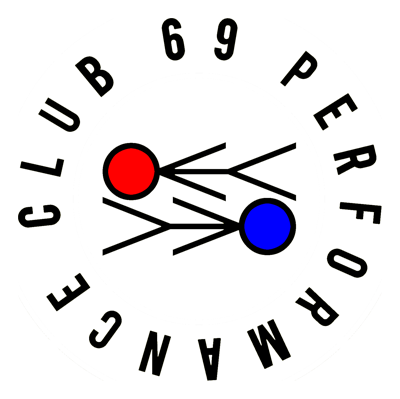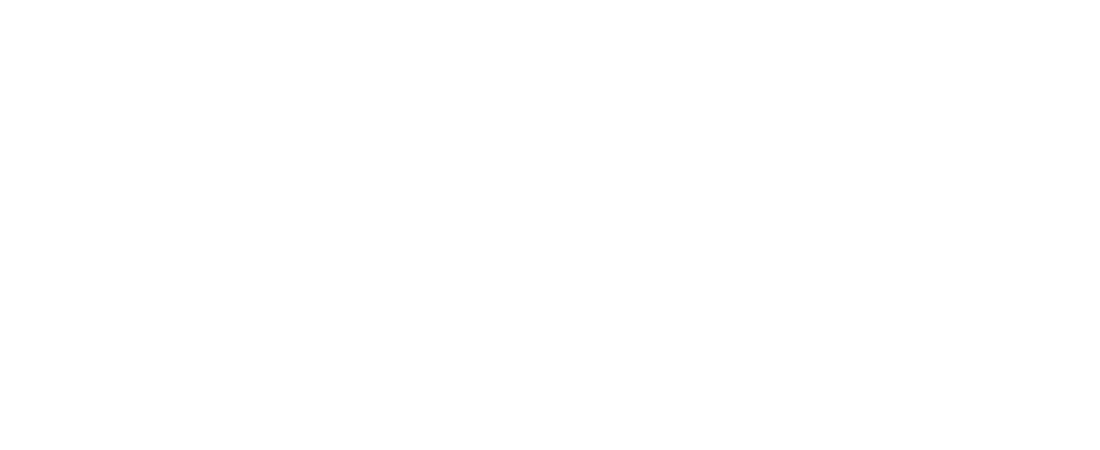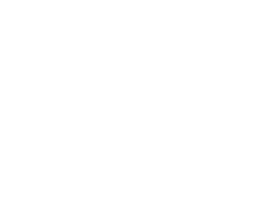Suasana pembukaan acara perdana 69 Performance Club di Forum Lenteng, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2016 (Foto: Forum Lenteng).
DARI JUDULNYA SAJA, Eye Contacting Myself (2016), karya seni performans pertama Abi Rama pada acara perdana 69 Performance Club di Forum Lenteng, Jakarta, tahun 2016, sudah menunjukkan sebuah keambiguan—kalau bukan kompleksitas. Menurut struktur bahasa, judul ini bisa diartikan dua macam. Pertama, ‘mata yang menatap diriku’; mata menjadi subjek utama (bagian tubuh) yang dieksplorasi sebagai medium. Tapi, di dalam arti yang kedua, ‘diriku yang mengontakmata’, yang menjadi subjek adalah justru tubuh (si seniman) secara keseluruhan. Dan lantas kita bisa bertanya lebih rinci, tubuh apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh Abi, karena gerakan yang ia lakukan di karya seni performansnya ini terbilang minim? Bolehlah saya menjawabnya dengan menarik istilah “tubuh termediasi”. Sebab, Abi memposisikan tubuh konkretnya sebagai panduan untuk memahami kerja teknologi komunikasi digital-internet.
Keambiguan dalam karya ini tidak berhenti di judul itu saja. Selain antara “tubuh konkret” dan “tubuh termediasi”, kita juga bisa menyadari keambiguan antara “citra tubuh sebagai konten teknologi” dan “tubuh dari teknologi itu sendiri”. Dan masih ada lagi: antara visual dan bunyi. Abi meramu semua kemungkinan itu menjadi peristiwa artistik yang, nyatanya, jauh dari kecenderungan umum karya-karya seni berbasis teknologi kala itu. Apa yang patut disebut imersif dalam karya ini, bukannya berhasil melenakan kita ke suatu perjalanan di dalam ruang yang penuh dengan efek-efek visual canggih dan bunyi-bunyi robotik, tetapi malah mengingatkan kita (setidaknya, saya sendiri) pada struktur interior toko cukur rambut yang bising.
Saya kira, kita perlu mencatat hikmah yang dihadirkan karya ini: seni berbasis teknologi tidak melulu harus menyajikan “kecanggihan”, tetapi bisa juga memaparkan “kekurangan teknologi” dalam susunan yang, seperti yang dapat kita lihat, biasa-biasa saja.

Suasana ketika Hafiz, mentor 69 Performance Club, memberikan pengarahan kepada para partisipan sebelum acara dimulai.
Abi menggunakan dua laptop, dua handphone, dua proyektor, dan dua layar. Masing-masing laptop, mengoperasikan perangkat lunak berupa aplikasi telekomunikasi obrolan video via internet, yang tersambung langsung ke masing-masing proyektor yang menembakkan visual dari tampilan desktop laptop tersebut ke masing-masing layar. Semuanya disusun berhadap-hadapan sehingga ruang yang terekam tampil berlapis-lapis di layar. Abi duduk di tengah-tengahnya.
Sembari perlahan kita mendengar suara melengking (audio feedback) yang diakibatkan adanya looped signal gara-gara posisi mikrofon dan speaker dari masing-masing device yang saling berhadapan itu, kita juga menyaksikan Abi mulai menatap-natap monitor laptop, beberapa saat, lalu menoleh cepat ke layar di dinding, lalu menoleh lagi ke monitor laptop. Gerakan kecil ini ia lakukan berulang-ulang. Awalnya, dia berkutat dengan laptop dan layar yang ada di meja sebelah kanannya, lalu di kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi, seakan-akan sedang mencari sesuatu.
Bunyi dengking terdengar konstan, tapi perlahan semakin kencang. Suatu ketika menjelang akhir penampilannya, Abi mengambil dua handphone yang ternyata sudah diletakkan di samping laptop yang ada di meja sebelah kirinya. Dia menyalakan kedua handphone itu—dapat diduga bahwa perangkat mobile tersebut juga mengoperasikan aplikasi obrolan video yang sama—dan menggenggamnya masing-masing di tangan kanan dan kiri. Abi memainkan jarak antara kedua handphone sembari tetap melanjutkan gerak menatap monitor laptop, layar di dinding, dan (kali ini ditambah dengan) menatap layar handphone di tangannya. Suara dengking semakin kuat dan terdengar begitu bising, tetapi terasa lumayan berirama. Mungkin karena Abi memainkan jarak antara perangkat mobile itu, yang mana permainan jarak ini sebenarnya berkaitan dengan upayanya menatap layar-layar perangkat, sehingga audio feedback yang terjadi terdengar seolah mempunyai intonasi tertentu.
Yang lebih membuat ‘gereget’, kita justru tidak melihat suatu kejutan, entah itu berupa semacam “ledakan” atau apa pun yang menjurus ke arah sana, karena, Abi malah mengakhiri penampilannya hanya dengan mematikan aplikasi di masing-masing handphone itu sehingga bunyi bising seketika berhenti. Setelah meletakkan kedua handphone di salah satu meja, ia pun menundukkan badan, tanda bahwa penampilannya sudah selesai.



Eye Contacting Myself bisa dibilang merupakan aksi filosofis untuk mengenali kinerja citra yang diproduksi oleh perangkat digital-internet. Aspek ‘internet’ penting dalam hal ini karena Abi bukan sedang menonton citra tubuhnya semata, tetapi juga mengejar citra-citra yang ditransmisikan melalui jaringan. Ia berusaha menatap mata tubuhnya di dalam layar dengan kemungkinan yang sangat kecil.
Mari kita perhatikan kembali momen ketika Abi melirik-lirik layar di sebelah kanan: saat dia menatap monitor laptop, citra tubuh di layar di dinding (yang menayangkan tampilan visual laptop) menatap ke depan, sedangkan ketika dia mencoba menatap layar di dinding, citra tubuhnya di layar dinding itu menoleh ke kanan. Abi berusaha secepat mungkin menatap mata dari citra tubuhnya yang ada di layar dinding tersebut. Nyatanya, hal itu sulit dilakukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa menyaksikan, Abi rupanya berhasil menatap mata dari citra tubuhnya di layar dinding itu selama beberapa detik, beberapa kali. Peristiwa ini dapat terjadi karena, faktanya, teknologi internet yang mentransmisikan citra, mempunyai kelemahan, yaitu ketertundaan transmisi (delay). Demonstrasi itu ia lakukan di semua perangkat, agaknya untuk menguji atau meninjau perbedaan delay di setiap perangkat yang, tentu saja, berhubungan dengan ketangkasan masing-masing perangkat dalam menangkap sinyal berdasarkan posisi peletakkan mereka di dalam ruangan.
Dengan kata lain, Abi sejatinya sedang merepresentasikan rutinitas masyarakat kita sehari-hari ketika menggunakan teknologi internet.
Dalam konteks Eye Contacting Myself, Abi mendudukkan perangkat-perangkat teknologis yang ia gunakan sebagai “tubuh objektif” untuk dieksplorasi demi kebutuhan artistik peristiwa seni performans. Perayaan terhadap teknologi dilakukan dengan menghadirkan realitas yang sesungguhnya dari teknologi itu, sebagaimana yang sering kali terjadi (tapi kerap diabaikan) di keseharian para pengguna. Realitas sungguhan dari teknologi itu dibingkai menjadi suatu statement mengenai kondisi, sikap, dan ciri media kontemporer. Dalam penggunaan sehari-hari, ketertundaan informasi biasanya dianggap sebagai eror dan sering kali dikeluhkan. Namun, kekeliruan sistem tidak jarang menjadi sumber inspirasi bagi pengartikulasian suatu karya. Kekeliruan itu, kalau bukan dibingkai menjadi kritik balik terhadap sistem, diramu menjadi sebuah kemungkinan estetis. Akan tetapi, untuk membicarakan hal ini, Abi tidak merepotkan dirinya dengan konstruksi rumit dari teknologi yang dibongkar-pasang, atau diimprovisasi, atau dioprek-oprek. Tidak. Dia memasang dan mengoperasikan perangkat-perangkat teknologis itu sebagaimana orang-orang biasa menggunakannya, dan memanfaatkan kejadian-kejadian eror sebagai pokok bahasa keseniannya.




Pendekatan yang dilakukan oleh Abi ini, bagi saya, memperkuat beberapa hal. Pertama, pemahaman terhadap gelagat teknologi yang saling menarik-ulur dengan gelagat tubuh para pengguna (user). Kedua, fakta sosial dari teknologi tersebut, karena Abi tidak mencerabut kodrat penggunaannya hanya untuk ditempatkan atau dialihbentukkan menjadi “robot asing” yang tak dikenal audiens. Ketiga, peluang dari “kelemahan teknologis” sebagai material karya seni. Di sini, kita bisa menyinggung signifikansi bunyi bising (audio feedback) yang sengaja diadakan oleh si seniman.
Menurut saya, dalam memperlakukan kebisingan atau noise sebagai elemen atau bahasa artistik, kita setidaknya perlu mengacu pada logika bagaimana kebisingan itu dapat terwujud. Dan setelah berhasil terwujud, bagaimana kebisingan itu dimainkan lewat patokan tertentu berdasarkan keberadaan objek penghasil bunyinya. Dalam beberapa kasus di karya-karya berbasis bunyi (sound art), permainan bunyi bisa saja terjadi atau dilakukan tanpa aturan, tetapi tetap mengacu pada logika objek yang menjadi sumbernya (objek di sini bahkan bisa yang berbentuk atau bersifat spasial). Kebisingan elektronis, misalnya, atau kebisingan dari teknologi digital, meskipun dipertunjukkan seolah “tanpa konstruksi”, logika konstruktif mereka dapat ditelisik dari logika perangkat ataupun kode-kode komputer yang bekerja di belakangnya sebagai pewujud bebunyian.
Di dalam kerangka seni performans Eye Contacting Myself, prinsip itu terterakan dengan sangat wajar—sewajar kodrat teknologinya sendiri tanpa ditambah ina-inu atau dikurangi di sana-sini. Bising terjadi karena sinyal yang berulang, kontinu, dan melingkar. Irama bunyi terjadi karena goyangan perangkat yang mengikuti gerakan tubuh si penampil. Di mata saya, kewajaran ini justru merupakan keunggulan dari “performans bunyi” yang dihasilkan Eye Contacting Myself. Terlebih lagi, sebagai sebuah fragmen yang terpisah dari peristiwa visual yang dilakukan oleh si senimannya, bebunyian ini pun masuk akal dari segi montase: audio feedback dari semua perangkat berkorespondensi dengan gerak minimal kepala dan mata Abi yang mengejar transmisi citra tubuhnya di layar. Sebagai suatu paduan audiovisual, kebisingan dan ketertundaan transmisi citra ini terasa musikal.
Sampai di sini, karya Abi ini masih menyisakan keambiguan: keberadaannya sebagai pertunjukan “seni bebunyian” (sound art) dan sebagai “seni performans” (performance art). Tapi, bukankah dalam menikmati sebuah karya seni zaman sekarang, batas-batas semacam itu tidak lagi penting? Lewat karya Abi, setidaknya kita paham bagaimana perangkat yang berada di hadapan Anda sekarang ini bekerja sehari-harinya. *