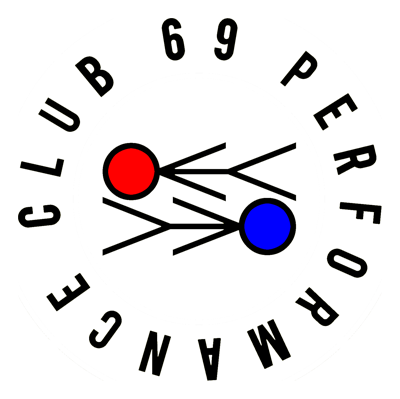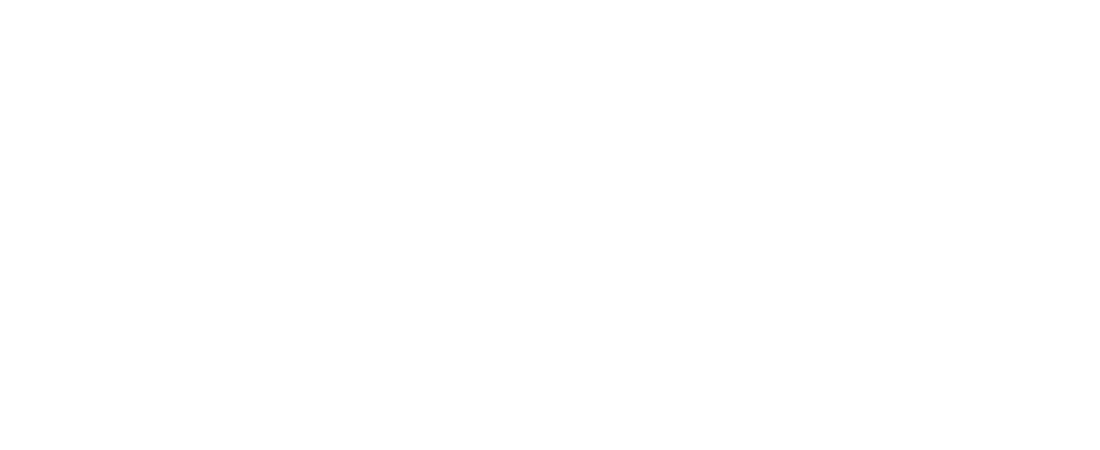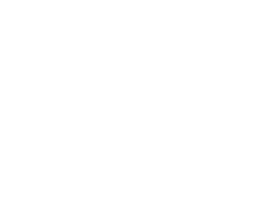KITA BOLEH SAJA meyakini bahwa, di dalam sebuah peristiwa, hakikat setiap benda dan manusia yang menjadi elemen-elemennya akan selalu identik—ada dengan properti yang utuh-lengkap—dari waktu ke waktu, sebagaimana para Endurantis memahami dunia. Namun, akal sehat kita secara awam memahami hal yang sebaliknya bila kita berbicara tentang keutuhan peristiwa (secara spesifik untuk konteks yang tengah dibahas dalam esai ini ialah “peristiwa artistik”, yaitu peristiwa yang diciptakan melalui modus seni performans). Properti visual dan auditori dari suatu tampilan peristiwa [artistik] tampak tidak tetap; ia dapat berubah-ubah seiring dengan berkembangnya aksi subjek penampil (performer) selama menjalankan peristiwa tersebut. Bagaimanapun, setiap benda dan subjek di dalam peristiwa seakan memperlihatkan “bagian-bagian” yang berbeda dari waktu ke waktu. Keberubahan bentuk dan situasi dari sebuah peristiwa artistik, besertaan dengan “tampilan yang beda” dari setiap elemennnya, dengan demikian, juga menggoda model interpretasi Perdurantis.
Apa yang sedang saya sasar dalam ulasan kali ini, hal yang akan kita garis bawahi sebagai sesuatu yang bertahan (tetap) dan berubah, adalah komposisi.





Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Di dalam karya seni, komposisi dapat menjadi subject matter. Dalam arti, ia bukan semata konsekuensi yang tertangkap (atau penampakan belaka dari akibat-akibat perlakuan seniman atas material dan medium) ataupun semata-mata tampilan formal-teknis yang menopang—apalagi yang sekadar mewakili—ekspresi si seniman. Komposisi bukan disikapi sebagai “hanya gaya ungkap” yang di baliknya suatu pesan yang sesungguhnya tengah bersembunyi, menunggu untuk dipecahkan. Pada konteks itu, komposisi bukan sesuatu yang bertujuan pada makna. Sebab, sebagai subject matter, komposisi adalah ekspresi itu sendiri; gaya ungkap merupakan pesan sejatinya; keberadaan dan kemenjadiannya adalah tujuan yang sebenarnya. Mendudukkan komposisi sebagai ekspresi bisa pula berarti memfokuskan penginterpretasian terhadap masalah tentang dualitas properti yang diembannya, yaitu yang bersifat intrinsik dan yang bersifat ekstrinsik.
Sementara itu, kita juga perlu memahami bahwa seni performans selalu dan akan selalu tentang spasio-temporal. Karena mewujud sebagai “peristiwa”, karya seni performans hadir ke dalam suatu “ruang”[1] dengan durasi tertentu, sesingkat-sekejap apa pun itu. Bisa dibilang, cara pandang dan pengalaman durasional adalah salah satu prinsip yang mendasari genre seni ini. Berdasarkan prinsip tersebut, kita bisa sama-sama sepakat bahwa, ketika seorang seniman performans mendudukkan komposisi sebagai hal paling pokok (subject matter) di dalam karyanya, itu artinya kita sedang diajak untuk mencerna sekaligus mengalami komposisi secara durasional—memahami komposisi sebagai sebuah peristiwa. Dengan kata lain, komposisi diakui sekaligus ditelaah sebagai sebuah persoalan hanya dan hanya jika kita (baik seniman maupun audiens) secara sadar mempertimbangkan spasialitas dan temporalitas setiap objek dan subjek yang ada di dalam peristiwa yang ditampilkan; kita digiring untuk memperhitungkan daya persistensi[2] setiap elemen di dalam komposisi tersebut. Selain itu, “komposisi” yang kita maksud juga bertalian dengan empat macam pengistilahan yang satu sama lain bisa mempunyai arti yang berbeda: “komposisi dari peristiwa”, “peristiwa dari komposisi”, “komposisi sebagai peristiwa”, dan “peristiwa sebagai komposisi”.
Dengan begitu, interpretasi kita lantas perlu berorientasi pada dua segi. Pada satu segi, ialah persistensi material-material di dalam sebuah peristiwa artistik. Pada segi yang lain, adalah persistensi dari bentuk peristiwa artistiknya sendiri. Karenanya, kita mau tak mau mesti melihat persistensi mereka—elemen-elemen dari “komposisi dari peristiwa”, “komposisi sebagai peristwa”, dan “peristiwa dari komposisi”, serta “peristiwa sebagai komposisi” itu—terhadap ruang dan waktu. Melalui pengamatan atas persistensi dari elemen-elemen itulah kita agaknya bisa merenungkan relasi-relasi metafisikal dari komposisi suatu karya seni performans, serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan dari muatan gagasan “endurantis” dan “perdurantis” yang bisa jadi tengah dipantiknya, untuk memahaminya sebagai perihal yang ontologis, dalam rangka menelisik aspek “keberadaan”-nya, “kemenjadian”-nya, dan “realitas”-nya.
***



Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Komposisi hanyalah salah satu persoalan yang mencuat dari kuratorial Hafiz yang berjudul “Framing Objects”. Kuratorial ini disajikan dalam acara presentasi karya seniman-seniman 69 Performance Club pada tanggal 9 April 2016 di ruangrupa, Jakarta Selatan.[3] Gagasan yang agaknya lebih utama dibicarakan kuratorial tersebut adalah, sebagaimana arti harfiah judulnya, “pembingkaian objek-objek”.
Para seniman ditantang untuk mengkontekstualisasi secara baru sepuluh benda (yang sudah ditetapkan dan disediakan oleh kurator). Masing-masing benda mengemban nilai sejarahnya sendiri, antara lain: sosial, mekanikal, spasial/ruang, urban/kota, keintiman, domestik, kekanak-kanakan, dan gender.[4] Untuk tampil, setiap seniman tidak diwajibkan menggunakan semua benda; mereka diperkenankan untuk memilih sebagian saja dan fokus pada benda-benda yang mereka pilih itu. Para seniman merealisasikan upaya kontekstualisasi baru benda-benda yang mereka pilih dengan cara membingkainya menjadi sebuah peristiwa artistik,[5] yang di dalamnya mereka beraksi dengan atau terhadap benda-benda itu, untuk menciptakan serangkaian kejadian dengan modus seni performans, dan dengan sadar pula menampilkan peristiwa itu sebagai sebuah tontonan. Pembingkaian, yang dimaksudkan dalam visi kuratorial Hafiz ini, juga berarti semacam menginskripsi nilai “sejarah baru” pada benda-benda tersebut: dengan aksinya, seniman menyuntikkan konten pada benda-benda, sekaligus juga menarik konteks kekinian yang melatari keberadaan mereka.
Mengapa komposisi menjadi hal penting untuk diperbincangkan kemudian? Kita bisa memaklumi alasannya jika mempertimbangkan intensi dari latar sajian yang diatur oleh kurator: area yang menjadi zona tampilan (atau panggung) bagi setiap penampilan karya diatur sedemikian rupa menjadi area yang steril. Dengan keseluruhan latar berwarna putih, tata ruang pada acara kala itu nyaris menyerupai white cube; tata latar ruangnya mengandaikan fungsi dari suatu “bidang” yang dapat menghadirkan bingkai imajiner dan meminimalisir distraksi. Sementara itu, sepuluh benda yang sudah disiapkan oleh kurator diletakkan di area luar “white cube” tersebut. Setiap seniman, ketika tampil, bisa keluar-masuk area “white cube” untuk memilih benda-benda yang akan mereka “bingkai”. Dengan latar yang steril macam itu, penonton diarahkan untuk fokus menyimak benda-benda yang “dimainkan” oleh seniman, “aktivitas” seniman dengan benda-benda, atau “kejadian” yang tercipta dari interaksi subjek-objek, dan sebisa mungkin tidak terganggu oleh penampakan-penampakan lain.
***


Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri, saya kira, merupakan salah satu penampilan seni performans dalam acara itu yang paling memudahkan kita untuk mendalami diskusi mengenai komposisi berdasarkan cara pandang dan pengalaman durasional ini. Perihal durasi sebagai suatu penekanan filosofis, dalam derajat signifikansi yang berbeda, juga mencuat dalam karya Rachmadi, berjudul Measuremental (2016).
Saya pribadi berpendapat bahwa aspek komposisi karya Asti lebih mencolok, dalam hal kualitas dari kepenuhannya pada ruang/latar tampilan, jika dibandingkan dengan bentuk karya Rachmadi yang lebih “minimalis”. Akan tetapi, perlu diingat, bukan berarti bahwa sesuatu yang minimal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan komposisi. Measuremental juga mempunyai persoalan komposisional, tentu saja, sebagaimana halnya semua karya seni performans yang pernah disajikan oleh 69 Performance Club, atau bahkan semua karya seni dari genre apa pun. Di esai ini, saya memang hanya fokus pada karya Asti, dengan alasan sederhana: kehendak untuk mengurai setiap karya para partisipan 69 Performance Club, satu per satu. Dengan kata lain, model refleksi kita atas Crossing bisa saja kita terapkan untuk menelaah karya Measuremental atau mengulas karya-karya yang lain, jika hal itu memang ingin dilakukan. Tapi, saya sendiri berencana untuk merefleksikan aspek yang berbeda—meskipun masih terkait dengan konsep durasi—pada ulasan tentang karya keempat Rachmadi itu, di tulisan lain, nantinya.
***




Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Mengamat-amati Crossing, kita dapat menyadari betapa Asti pada awalnya tidak sedang membebankan tubuhnya pada gerak koreografis ataupun gerak teatrikal. Aksinya terbilang wajar dan lugas: memasuki “white cube” dengan mengenakan dress hitam dan sepatu hak tinggi, ia mula-mula mengangkut tangga bambu dan menyandarkannya dalam posisi miring ke dinding (dinding di sebelah kiri, jika dilihat dari sudut pandang penonton). Kemudian, ia bergerak lagi ke tepi “white cube”, mengambil benda berupa kumpulan bola kecil warna-warni yang terbuat dari plastik (bola-bola itu terbungkus tas jala). Sambil menjinjingnya santai, Asti menaiki tangga, lalu mencantolkan jala berisi bola-bola kecil itu ke paku yang ternyata sudah disiapkan di langit-langit “white cube”. Posisi bola jadi berada di atas tangga; lebih tepatnya, di sisi kiri atas bidang “white cube”.
Asti turun lagi dari tangga, kemudian sedikit demi sedikit mengambil batu bata merah, menyusunnya menjadi empat pondasi, lebih-kurang setinggi lutut: dua pondasi pertama (satu sama lain berjarak kira-kira selebar bahu, atau selebar tangga bambu) berposisi di tengah-tengah “white cube”, sedangkan dua pondasi sisanya diletakkan pada posisi yang berjarak sekitar sembilan langkah ke sisi kanan. Asti menyusunnya sedemikian rupa untuk menjadi sama tinggi. Kegiatan menyusun batu bata merah ini memang terbilang memakan waktu, dan dapat dimaklumi jika kejadian itu memunculkan kesan bosan pada penonton.
Usai membentuk keempat pondasi itu, Asti bergerak memindahkan tangga bambu. Posisi tangga bambu hendak diubahnya, dari bersandar pada dinding di sebelah kiri menjadi merebah di atas pondasi batu bata. Saat ia mengangkat tangga bambu itu, disengaja atau tidak, bola kecil warna-warni yang menggantung di langit-langit tadi tersenggol sedikit sehingga objek itu bergoyang selama beberapa saat. Sejenak kemudian, kita mulai mengerti bahwa Asti ingin membuat konstruksi “jembatan tangga bambu”. Tapi ternyata, jarak antara pondasi di kiri dan di kanan melebihi panjang tangga bambu. Mau tak mau, Asti harus mengatur ulang posisi dua pondasi bata yang ada di sisi kanan itu dengan menggesernya sedikit ke kiri, sehingga tangga bambu bisa diletakkan di atas keempat pondasi, membentuk semacam jembatan—di momen ia menggeser pondasi bata di sisi kanan itu, tangga bambu direbah-miringkan ke sisi dua pondasi bata yang ada di sebelah kiri, sementara objek bola di langit-langit masih terus bergoyang, perlahan menuju geming.
Setelah konstruksi “jembatan tangga bambu” berhasil terbentuk, Asti tampak bergerak ke tengah ruangan, ke titik dua pondasi yang ada di kiri, lalu menekankan berat badannya di pangkal “jembatan tangga bambu” itu. Kelihatannya, ia ingin memastikan bahwa konstruksi itu kokoh untuk menahan beban badannya. Di momen ini, objek bola warna-warni sudah diam, berhenti bergoyang. Sementara, kegiatan mengatur konstruksi dan memastikan kekokohan “jembatan tangga bambu di atas pondasi batu bata” itu pun, lagi-lagi, terasa benar-benar memakan waktu, benar-benar membosankan.[6]
Dan begitulah: setelah tampak yakin bahwa konstruksi itu kokoh, Asti melepas sepatu hak tinggi dari kakinya dan malah memindahkan objek itu ke tangannya. Selanjutnya, ia merangkak perlahan di atas tangga bambu yang melintang tersebut. Dari posisi di ujung kiri tangga (yang berarti dari posisi di tengah-tengah “white cube”), bergerak ke sisi kanan tangga (ke tepi “white cube”), kemudian berbalik lagi ke sisi awal. Kegiatan merangkak bolak-balik ini dilakukan dengan gerak yang pelan, berkali-kali. Dari bangku penonton, rangkakan bolak-balik Asti terlihat berlangsung pada area tengah-ke-kanan bidang “white cube”. Situasi “gerak horizontal” (diwakili oleh aktivitas Asti dengan konstruksi “jembatan tangga bambu) di sisi kanan bidang ini bersanding dengan situasi “geming vertikal” di sisi kiri bidang, yang diwakili oleh “area kosong” berpuncak bola warna-warni yang menggantung di langit-langit. Jika kita mengamati video dokumentasi yang tersedia, gerakan bolak-balik itu dilakukan sebanyak tiga kali.[7]
Setelah menuntaskan kegiatan merangkak bolak-balik berulang-ulang tersebut, Asti kembali mengenakan sepatu hak tinggi di kakinya. Kemudian dia mengangkat tangga bambu dari atas pondasi bata, memposisikannya kembali bersandar pada dinding di kiri. Lalu Asti menaiki tangga itu, menggapai bola kecil warna-warni tadi yang telah bergeming cukup lama. Ia menyobek tas jalanya, membiarkan bola-bola itu jatuh bertebaran ke lantai, menciptakan suara gemuruh yang singkat. Akhirnya, bola-bola itu mengisi sebagian area di lantai, beberapa di antaranya mengitari pondasi bata yang tersisa, sedangkan Asti berdiri diam di atas tangga bambu. Penampilannya usai.
***



Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Deskripsi rinci sebagaimana yang saya jabarkan di atas, adalah paparan tentang komposisi dari peristiwa artistik Crossing. Dari sudut pengertian ini, kita tengah meletakkan fokus pada bagaimana peristiwa itu berlangsung. Setiap kejadian, sekecil apa pun, sebocor apa pun, adalah elemen yang tidak bisa diabaikan. Sebagai suatu modus seni performans, yang di dalamnya aksi adalah daya ungkap yang utama, setiap sub-kejadian dalam lingkup sebuah peristiwa mengandung pernyataan yang dapat memantik—kalau bukan makna—sensasi. Setiap sub-kejadian adalah “nada” tertentu yang, disengaja atau tidak oleh si penampil, dapat menciptakan kesan; suatu elemen gerak yang, kalaupun tidak berarti apa-apa (atau bahkan terasa mengganggu), keberadaannya dapat menggugah rasa pada diri penonton terhadap peristiwa yang mereka saksikan.
Di saat yang bersamaan, “komposisi dari peristiwa” di atas adalah juga “peristiwa dari komposisi”. Dalam sudut pengertian yang ini, kita meletakkan fokus pada pertanyaan apakah peristiwa yang sedang berlangsung ini. Penempatan sebuah objek pada satu titik di dalam bidang (ruang latar “white cube”), serta pemindahannya ke titik yang lain pada bidang yang sama, merupakan suatu proses yang tidak bertujuan pada formasi final (absolut). Ini bukanlah keadaan yang tetap, ataupun sesuatu yang menuju keadaan tetap. Sebab, dalam konteks karya ini, “proses” penempatan-perpindahan-penempatan itu sendirilah yang merupakan tujuan. Crossing mewujud utuh sebagai satu kesatuan komposisi justru karena keberubahan bentuknya, atau karena keberubahan dari keberadaan elemen-elemen di dalamnya: objek (tangga bambu, batu bata, bola warna-warni) dan subjek (si penampil—Asti).
Pada lapis pengertian yang ketiga, Crossing juga bisa dipahami menjadi “komposisi sebagai peristiwa”. Dalam sudut pandang ini, kita meletakkan fokus pada bagaimana pencerapan yang diekspektasikan terhadap komposisi tersebut. Dapat diamati bahwa, setiap elemen di dalam komposisi ini bergerak untuk mencari dan berhenti pada satu keadaan/situasi tertentu, tetapi seketika bergerak dan berubah lagi untuk mencari keadaan/situasi yang lain, persis di saat satu keadaan/situasi itu nyaris terbentuk. Ini adalah komposisi yang selalu menangguhkan dirinya, atau menangguhkan representasi yang diharapkan penonton atas dirinya. Ia ada sebagai sebuah komposisi karena “terus menjadi komposisi”; komposisinya disebut persisiten karena ke-“menjadi”-annya. Dengan sifat yang seperti ini, ia akan tercerap utuh sebagai sebuah komposisi justru tatkala dialami, atau dilalui, sebagai suatu peristiwa—sesuatu yang berlandaskan prinsip durasional. Ketika keseluruhan peristiwa berhenti (atau tuntas), segala aspek durasi telah terlampaui, dan komposisi sudah tidak ada lagi.
Dan dengan adanya sifat ketiga di atas, karya ini secara bersamaan juga mengandung sifat keempat: “peristiwa sebagai komposisi”, yaitu sifat apakah yang ada atau dimiliki peristiwa Crossing. Dalam konteks keempat ini, seni performans menempatkan rima dan irama sebagai pondasi utama kejadian, yang keberlangsungannya menentukan bentuk peristiwa secara utuh. Wujud setiap benda dan subjek tersaji dalam ikatan spasial tertentu dengan bidang sajian (yaitu, yang kita sebut di dalam esai ini “white cube”) dan juga terikat dengan keberadaan benda-benda lainnya. Akan tetapi, keterikatan itu valid hanya dan hanya jika kondisi gerak-dan-geming masing-masing elemen tersusun dalam rangkaian temporal yang signifikan. Hukum persandingan, jukstaposisi, superimposisi, proksimitas, dan kesinambungan berlaku dalam relasinya atas waktu, atau dengan mengekstensifkan propertinya ke dalam logika waktu, alih-alih hanya logika ruang. Durasi persistensi setiap elemen adalah sifat utamanya, alih-alih semata konsekuensi dari interaksi antara subjek dan objek. Durasi persistensi masing-masing elemen juga saling tumpang-tindih, menjadi suatu kompleksitas—nada [yang] kompleks. Setiap elemen pada setiap momen tidak tampil utuh, tetapi hanya menghadirkan sebagian aspek temporalnya—sebagaimana Perdurantis memahami dunia.
Dengan kata lain, berapa lama suatu benda dan subjek diam, berapa lama dia bergerak-berpindah, atau gerak lain apa atau diam lain apa yang tengah berlangsung saat suatu elemen sedang bergerak atau berdiam; kesemuanya adalah perihal yang niscaya tengah diekspresikan sebagai sebuah bingkaian yang bertujuan pada sensasi ketimbang representasi. Apa yang kemudian dapat kita tangkap sebagai “gereget” dari peristiwa ini, adalah apa yang terkandung dalam setiap kejadian, bukan saja pada kejadian-kejadian yang sudah direncanakan oleh si penampil melalui aksi sadarnya (misalnya, berpindahnya posisi tangga, atau dijatuhkannya bola-bola kecil warna-warni dari langit-langit), tetapi juga kejadian-kejadian yang tak direncanakan (misalnya, posisi pondasi bata yang tidak tepat, goyangan bola-bola kecil warna-warni yang tak disengaja, dan bahkan gerak arbitrer setiap bola ketika menumbuk, memantul, dan mencari titik hentinya di lantai). Konstelasi kejadian ini saling bersanding, saling terkait, saling mengganggu, saling membentuk sekaligus saling “menghancurkan”, saling menghindari kemapanan bentuk, tetapi secara aneh juga mengandaikan bentuk yang semestinya pasti; setiap kejadian mengemban tonalitas yang berbeda, berkumpul dalam gejolak tempo tertentu, menghasilkan rima dan irama yang pada akhirnya menjadi properti intrinsik peristiwa. Ia adalah peristiwa komposisional, dalam arti: bukan hanya karena posisi dari setiap benda-benda dan subjek, tetapi karena kejadian (atau hal yang terjadi) pada benda-benda dan subjek tersebutlah dia dapat disebut memiliki komposisi. Kejadian itu, bisa berupa “berubah bentuk/posisi” ataupun “tetap pada bentuk/posisi” (bergeming). Dan secara ekstrinsik, “peristiwa sebagai komposisi” ini menyasar kepekaan haptikal ketimbang optikal dari daya amatan penonton.
***



Crossing (2016) karya Prashasti W. Putri di ruangrupa, Jakarta. (Foto: Forum Lenteng).
Dapat disadari bahwa analisis formal yang saya lakukan terhadap Crossing, sedikit-banyak, menyinggung-nyinggung dua pandangan filosofis—yang saling ber-“konflik”—mengenai “perubahan” dan “kesinambungan” dari keberaadaan (existence) objek, yaitu cara pandang Endurantis dan cara pandang Perdurantis.
Cara pandang yang pertama meyakini bahwa objek hanya mempunyai bagian-bagian spasial, yang dengannya objek tersebut dapat mengalami dua atau lebih kondisi berbeda pada satu waktu secara fisikal (misalnya, tangga bambu mengalami dua kondisi yang bertentangan pada satu momen, yaitu menyentuh dinding serentak dengan menyentuh lantai). Sedangkan cara pandang Perdurantis melihat bahwa setiap objek, selain properti spasial, juga mempunyai properti unik lainnya, yaitu “properti temporal”, yang menyebar di sepanjang waktu, dan penampakan wujudnya pada setiap momen hanya penampakan sebagian dari keseluruhan properti temporal yang dimilikinya. Endurantis meyakini bahwa objek-subjek hanya riil ada pada “waktu sekarang” (karena masa lalu telah mati dan masa depan belum ada), dan subjek-objek yang riil di waktu sekarang itu selalu identik dengan kelengkapan properti spasialnya. Sedangkan, Perdurantis meyakini bahwa setiap objek itu riil di segala masa.
Dalam logika Endurantis, bola kecil warna-warni yang ada di langit-langit “white cube”, misalnya, adalah bola kecil warna-warni yang sungguh-sungguh identik dengan yang bertebaran di lantai—itu adalah objek yang sama. Tetapi, ketika ia ada bertebaran di lantai, itulah yang rill, karena ia yang digantung sudah tidak lagi ada. Sementara itu, dalam logika Perdurantis, keduanya adalah suatu keberadaan yang masing-masingnya merupakan “objek berbeda” (dalam tanda petik), atau sesuatu yang menampilkan properti temporal yang berbeda: bola dengan properti “bola-yang-digantung” dan bola dengan properti “bola-yang-bertebaran”. Perdurantis justru tidak mengenal masa lalu dan masa sekarang karena, setiap momen, dan setiap wujud yang tampak dari keberadaan objek, hanyalah penggalan dari sebuah totalitas keberadaan (dari/di dimensi lain); tidak ada yang tidak riil.
***
Alih-alih mengurai konteks yang barangkali sedang dibicarakan Asti melalui performa tubuh dan kostumnya di dalam Crossing, misalnya ide soal “tubuh perempuan sebagai pernyataan simbolik tentang pertarungan, perjuangan, dan kesenangan,”[8] saya sengaja menggiring arah diskusi kita ke perihal metafisikal semacam ini dalam rangka memantik refleksi universal dan manusiawi yang, pada akhirnya nanti, juga bisa diaplikasikan secara lebih filosofis terhadap isu perempuan. Tentu saja, singgungan kita terhadap dua cara pandang tersebut, antara Enduratisme dan Perdurantisme, bukan juga dalam niatan untuk mendemonstrasikan (lewat Crossing) cara pandang mana yang lebih benar/tepat jika dibandingkan satu sama lain. Justru, saya sedang berargumentasi soal kekhasan seni performans, yaitu kecenderungannya untuk merangkul ambivalensi sebagai gaya bahasanya, atau sebagai lorong yang melaluinya kita bisa menjelajahi lebih dalam esensi karya tersebut.
Crossing, bagi saya, memantik (atau menggemakan) ide teoretikal baik enduratis maupun perdurantis karena penekanan artistiknya, disadari atau tidak, pada durasi dan komposisi sekaligus. Melihatnya dengan sudut pandang Endurantis, karya ini mengafirmasi sifat kesekarangan seni performans. Karena setiap objek (dan kejadian) itu hanya berada/mengada secara nyata pada satu momen, Endurantis menegaskan keberhargaan setiap aksi, setiap kejadian. Esensi detik ini, membabat esensi dari detik yang telah lalu, dan tidak memusingkan esensi pada detik yang akan datang. Dengan kata lain, untuk mengalami segala yang riil dari runutan peristiwa, kita wajib menyimak setiap kejadian elemen di setiap momen.
Akan tetapi, keberhargaan setiap aksi dapat dicermati dengan cara yang lain pula, yaitu cara Perdurantis: justru karena tidak ada yang namanya masa lalu, sekarang, dan masa depan (bahwa waktu itu hanya satu) itulah, maka, apa yang secara umum kita ketahui atau kita label sebagai “telah berlalu” tidak bisa serta-merta dipenggal dari apa yang terjadi sekarang dan dihilangkan hubungannya dengan kemungkinan dari apa yang secara umum kita sebut “masa depan”. Dengan kata lain, pemutusan yang sekarang dari “masa lalu” dan “masa depan” sama halnya dengan mengenyahkan bagian penting dari suatu keberadaan yang total/utuh—itu, secara konseptual, mengamputasi kehidupan. Sebuah peristiwa—yang dalam konteks pembahasan kita di sini adalah peristiwa artistik Crossing—merupakan suatu keutuhan yang penting dari pangkal ke ujung.
Kombinasi cara pandang paradoksikal endurantis-cum-perdurantis ini memberikan kita sebuah pemahaman lainnya tentang apa yang selama ini kita sebut—terutama di artikel-artikel ulasan tentang karya-karya 69 Performance Club yang saya tulis sebelum esai ini—sebagai “endurance”, atau “daya tahan”. Kita pun bisa mafhum, sebagaimana dipantik oleh Crossing, daya tahan bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal ketahanan tubuh penampil, tetapi juga soal ketahanan objek-subjek untuk “ada di dalam waktu”. Seni performans bukan semata soal “keringat”, tetapi juga soal irama, tempo, dan yang lebih radikal: soal apa yang tak bisa dicerap.
Seni performans merangsang kepekaan durasional, menciptakan empati terhadap momen. Dengan kepekaan atas durasi, suatu komposisi mewujud sebagai sebuah sensasi, menjelma menjadi suatu kontemplasi yang tidak hampa. Dan tentu saja, ini pun berlaku pada komposisi-komposisi yang diam (komposisi yang tidak mengandung gerak secara nyata, seperti yang ada pada fotografi dan lukisan). Kepekaan atas durasi, dengan mengambil contoh praktisnya pada Crossing, adalah inti dari komposisi yang menduduki posisi subject matter. Bisa dikatakan, para seniman, terutama seniman performans, membicarakan ini untuk menawarkan cara mengalami karyanya.
Durasi singkat bisa memicu ledakan estetik, durasi panjang/lama mengandaikan pemurnian ekspresif. Kombinasi keduanya, di dalam peristiwa yang terkonstruksi, adalah fluktuasi yang dengannya kita bisa merasakan gairah terhadap tontonan, gairah untuk mengalami karya—atau bahkan gairah untuk menikmati pahit-getir kehidupan. *
Endnotes:
[1] Konsep “ruang” dalam hal ini tidak melulu merujuk pada suatu bangunan dengan bidang-bidang pembatas (area berdinding/berpartisi), tetapi bisa meluas ke suatu pengertian yang merujuk pada rentang area di mana keberadaan fisikal dan konseptual suatu objek/subjek dapat diperbincangkan, diwacanakan, bahkan dirasakan.
[2] Dalam filsafat (khususnya bidang metafisika), “persistensi” (bisa juga diartikan sebagai “daya tahan”, “ketahanan”, atau lebih rincinya, “kesinambungan untuk tetap ada/berada”) digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk kepada suatu rentang bagi sebuah objek untuk mulai berada pada satu titik ruang-waktu hingga lenyap dari titik itu. Pendek kata, “persistensi” adalah fenomena dari “benda-benda yang mewujud atau ada (exist) selama waktu tertentu”.
[3] Markas ruangrupa lama di Jl. Tebet Timur Dalam Raya, Kecamatan Tebet, sebelum pindah ke Gudskul di Jl. Durian, Kecamatan Jagakarsa.
[4] Sementara diketahui ada 10 benda yang disediakan, teks kuratorial ini hanya menyebut delapan “nilai sejarah”. Dengan kata lain, terdapat satu-dua benda yang mengandung atau merujuk nilai sejarah yang sama.
[5] Kalau menggunakan kata-kata Hafiz, ialah “peristiwa estetik”.
[6] Tentu saja saya mempunyai alasan mengapa saya menekankan aspek “membosankan” ini lebih dari sekali. Saya berpendapat bahwa salah satu cara menikmati karya seni performans adalah menerima dengan tulus rasa bosan yang tertangkap dari sebuah tampilan, sekaligus membangun empati terhadap proses yang berlangsung dalam peristiwa tampilan tersebut. Sebab, kalau meminjam kata-kata seorang seniman, Otty Widasari (yang pernah ia ujarkan kepada saya): “bosan”, “kebosanan”, dan “hal yang membosankan” juga bisa dilihat sebagai bahasa seni. Khususnya dalam konteks seni performans, “bahasa seni” yang “bosan” itu merupakan salah satu jenis dari “sensasi seni” (konteksnya di sini, ialah, sensasi sebagai bahasa). Tinjau refleksi mengenai “bosan”, “kebosanan”, dan “membosankan” ini dalam artikel berjudul “Setrika Baju yang ‘Membosankan’”, performanceart.id, 11 Maret 2021.
[7] Tapi, saya pikir jumlahnya lebih dari itu. Saya pribadi menyaksikan penampilan Asti dalam karya ini secara langsung pada hari itu, dan kalau saya tidak salah ingat, Asti merangkak bolak-balik lebih dari tiga kali. Proses tersebut, buat saya waktu itu, terasa begitu lama dan benar-benar membosankan. Asti sendiri mengaku kepada saya bahwa ia melakukannya sebanyak sepuluh kali bolak-balik, sampai tangga bambu itu bengkok.
[8] Sebagaimana yang tertera pada deskripsi karya ini di laman terkait: Crossing di situs web performanceart.id.