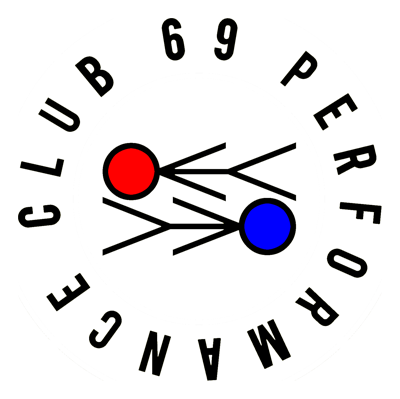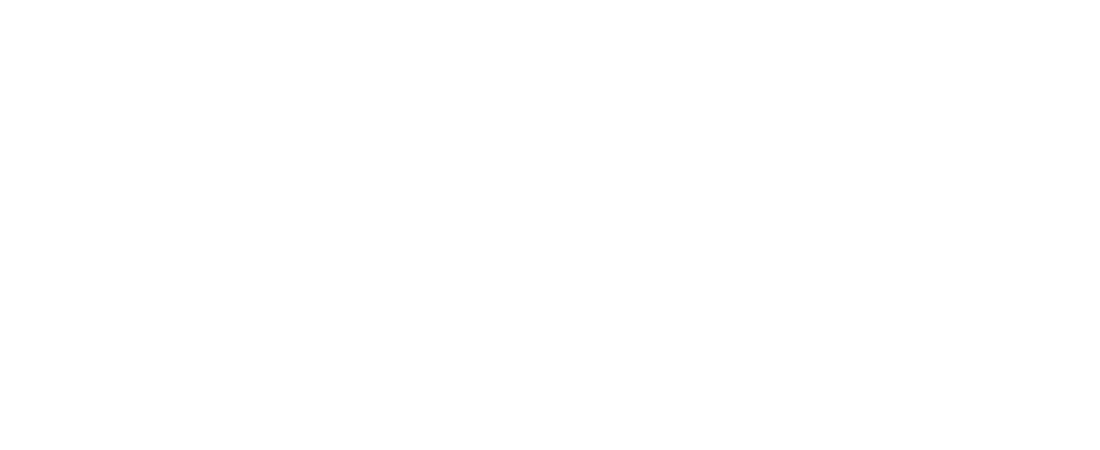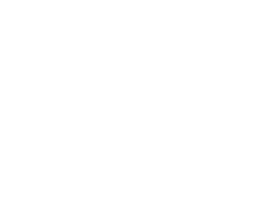CUKUP ADA BUKTINYA jika ingin mengatakan bahwa Ragil Dwi Putra sering menggunakan cermin sebagai material di dalam karya-karya seni performansnya, terkhusus yang ia buat pada masa ia aktif di 69 Performance Club. Penggunaannya pun berada di tingkat yang telah menyikapi cermin sebagai medium[1] yang menubuh dengan tubuhnya sendiri (pada karya-karyanya, tubuh Ragil bagaimanapun tetap menjadi medium utama). Atau bahkan, sebagai subject matter, seperti yang terlihat pada karya berjudul By the Mirror (2016) yang di dalamnya tema tentang sistem refleksi (mirroring) dianalisis dengan sudut pandang seni performans meskipun tanpa menghadirkan benda cermin saat karya itu ditampilkan.

Suasana ketika acara 69 Performance Club bertajuk Transmitted Delusion dibuka. (Foto: Forum Lenteng).
Menurut saya, dalam karya-karya seni performans-nya Ragil, cermin merupakan hal pokok untuk menganalisa tubuh. Kesadaran memilih cermin sebagai “sarana analitis” itu sudah bisa kita lihat sejak karya seni performans pertamanya yang berjudul Self Portrait (2016). Karya ini dipertunjukkan pada acara 69 Performance Club dengan tajuk kuratorial Transmitted Delusion (dikurasi oleh Hafiz) pada tanggal 6 Maret 2016 di Forum Lenteng, Jakarta.
Pada Self Portrait, tema yang bergaung ialah kemungkinan-kemungkinan untuk mengurai logika rupa, perspektif, dan juga—dalam kedudukannya sebagai karya seni performans (karya berbasis peristiwa langsung)—pengorganisasian gerak audiens. Terkait poin terakhir ini, “pengorganisasian”, meskipun Ragil tidak berangkat dari gagasan seni abstrak, penampilan Self Portrait bagaimanapun menunjukkan sebuah gejala artistik yang bisa mengingatkan kita pada upaya Konstruktivisme[2] dalam mentransformasi unsur-unsur taktilitas[3] dan gerak perseptual yang ada dalam karya seni ke suatu skala berbasis ruang. Upaya transformasi tersebut, menurut Buchloh (1984), bisa melibatkan penonton karya ke dalam suatu pengalaman fenomenologis—sebuah gagasan tandingan terhadap “perilaku kontemplatif” tradisional yang biasanya terjadi ketika penonton menyimak karya seni di ruang pameran.[4]
Saat menampilkan Self Portrait, Ragil tampil telanjang. Dari semua kemungkinan ruang yang ada di markas Forum Lenteng saat itu, ia memilih bilik kecil berupa kamar mandi sebagai zona penampilan karyanya. Ia berjalan ke dalam kamar mandi kecil itu, yang di dalamnya sudah disiapkan banyak cermin dengan berbagai ukuran (kecil dan besar) dan bentuk (persegi dan lingkaran); cermin-cermin itu diletakkan menyebar di berbagai posisi (di atas rak, dan di posisi yang lebih bawah, di atas kloset). Masing-masing cermin, karena posisinya yang berbeda-beda, memantulkan penggalan-penggalan bagian tubuh Ragil yang juga berbeda-beda, ada yang hanya memantulkan bagian wajah saja, bagian bahu saja, dada saja, atau bagian perut saja. Sembari bagian-bagian tubuhnya itu dipantulkan cermin, Ragil melukis garis beragam warna pada bagian-bagian tubuhnya, seperti di wajah, leher, bahu, lengan, dan dada, serta barangkali juga perut (bagian ini tidak tampak dalam dokumentasi video dari karya itu, tetapi layak diduga bahwa Ragil juga melukis garis di bagian perutnya). Penampilannya kemudian berakhir tatkala Ragil menutup pintu kamar mandi.


Ragil ketika menampilkan karya seni performansnya, Self Portrait (2016). (Foto: Forum Lenteng).
Jujur saja, ketika karya ini ditampilkan, saya tidak hadir pada acara tersebut. Ulasan saya di sini hanya mengacu kepada video dokumentasi karya yang sudah menjadi arsip 69 Performance Club. Saya sempat menanyakan kepada Ragil, apakah di dalam konsep karyanya itu, penonton diperkenankan atau tidak untuk masuk ke dalam kamar mandi selagi dia melukis garis di tubuhnya? Ragil menjawab bahwa ketentuan itu tidak ada di dalam konsep karyanya, tetapi kurator dengan cukup jelas mengumumkan bahwa Ragil akan melakukan aksi performans di dalam kamar mandi itu. Barangkali, penegasan ini secara psikologis menciptakan situasi yang menyebabkan audiens segan untuk masuk ke dalam kamar mandi; mereka hanya menonton dari luar—melongok hanya melalui celah pintu yang lebarnya tak seberapa, sebagaimana kamera video yang mendokumentasikan karya ini juga hanya merekam dari luar kamar mandi saja, menggunakan berbagai teknik bidikan (ada yang di-zoom untuk mengejar detail kejadian, ada yang dengan bidikan lebar, wide shot, untuk menunjukkan suasana baik di dalam kamar mandi maupun di luar kamar mandi sekaligus).
Namun, terlepas dari kemungkinan tentang boleh atau tidaknya penonton mendekat, bahkan masuk, ke dalam kamar mandi, saya pribadi ingin menaruh perhatian pada pilihan Ragil atas ruang tampilan karyanya, yaitu kamar mandi tersebut. Disadari atau tidak, pemilihan kamar mandi ini berimplikasi pada gaya ungkap artistik Self Portrait, yang dari sanalah saya menarik pembacaan tentang “pengorganisasian audiens” yang menyimak karya.
Lukisan garis pada tubuh Ragil mungkin saja memiliki maksud penandaan tertentu, entah itu merepresentasikan hal yang berkaitan dengan ekspresi subjektif si seniman atau perihal yang lain sama sekali. Akan tetapi, melandaskan penilaian pada sudut pandang formal, saya menilainya lebih sebagai upaya restrukturisasi dalam proses pembingkaian tubuh, semacam lapisan yang mengandaikan simplifikasi anatomis terhadap tubuh yang hendak direfleksikan pada cermin. Garis-garis ini agaknya juga berlaku atau berfungsi sebagai “garis bawah” yang menggemakan orientasi tentang pendefinisian realitas yang berbeda—menempatkan visual lebih ke dalam dunia analitik daripada sekadar representasional. Mengamati unsur ini, secara khusus, konsekuensi indeksikal yang saya tangkap ialah pertaliannya dengan wacana seni abstrak ketimbang figuratif.
Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari gerakan seni abstrak ialah kehendaknya untuk berbicara mengenai dunia tempat kita hidup melalui sudut pandang non-alamiah, serta tantangannya untuk beranjak dari “penjara kepersisan”. Seni abstrak menggapai realitas dengan berangkat dari gagasan-gagasan spiritual, pada satu sisi, atau saintifik, di sisi yang lain, dan wacana gerakan ini melihat bagaimana bentuk seni (art form) bisa mempunyai karakteristik pengucapan atau pengungkapannya sendiri; karakteristik yang meninggalkan beban-beban untuk [harus] merepresentasikan sesuatu dari dunia, juga kemungkinannya untuk mencapai suatu penggambaran tentang yang tak dapat dilihat. Gaya ungkapnya lantas bertumpu pada keyakinan untuk memanifestasikan emosi dan hal-hal di luar indra penglihatan ke dalam visual (paradigma spiritual), atau mendeformasi wujud visual dari kenyataan menjadi langgam-langgam matematis (paradigma sains). Kalangan yang menolak kedua tumpuan ini (spiritual dan saintifik) memilih untuk bertumpu pada kualitas aksi yang langsung dan instan (menekankan unsur immediacy) dan fokus pada realitas gambar (pictorial reality). Wacana ini tampak pada karya-karya seni rupa dari nama-nama besar, seperti Paul Cézanne, Van Gogh, Henri Matisse, Pablo Picasso dan Georges Braque, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Franz Marc, Wassily Kandinsky, atau Kazimir Malevich. Mengambil contoh Kubisme, misalnya, persoalan visual adalah pendefinisian baru atas bentuk melalui logika geometris dan tentang potensi untuk menampilkan ragam sudut pandang secara serempak.[5] Dalam wacana avant-garde Rusia, lain lagi: yang dikejar bukan lagi dinamisasi visual pada bidang datar semata, tapi bagaimana dinamisasi itu mewujud secara meruang dan terimplementasi bahkan ke gerak aktual audiens.



Ragil ketika menampilkan karya seni performansnya, Self Portrait (2016). (Foto: Forum Lenteng).
Ragil tentunya bukan sedang memanjang-manjangkan wacana seni abstrak, karena apa yang ia buat adalah seni performans. Abstraksi visual dalam Self Portrait—garis-garis yang dilukis di tubuh serta refleksi bagian tubuhnya yang tersebar di cermin-cermin—bisa dilihat sebagai konsekuensi praktis dari inisiatifnya yang mengutip gaya ungkap sejumlah genre yang sudah umum dalam sejarah perkembangan seni rupa dunia. Tapi yang lebih penting di mata saya adalah penekanannya pada bahasa performatif: faktor penentu bagi keberlangsungan karya dengan visi “perubahan situasional, aktual, yang juga bersifat kini-dan-di-sini” pada diri-diri audiens. Salah satu yang membuat perlakuan artistik dalam Self Portrait bergema dengan seni abstrak ialah kehendaknya untuk menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami realitas. Jika seni abstrak menekankan realitas gambar (pictorial), karya Self Portrait-nya Ragil ini menekankan realitas performatif, yaitu penekanan tentang apa yang akan berlangsung, bagaimana hal itu dapat berlangsung atau dilangsungkan oleh peristiwa artistik karya, dan bagaimana semua itu dicerna oleh orang yang mengalami atau menyaksikannya. Lantas, kita patut bertanya, dalam keberlangsungan itu, apa yang menjadi fokus Ragil…? Saya berpendapat, sebelum menjelaskan apa dan bagaimana kejadiannya, fokus yang dimaksud adalah cara melihat ketimbang isi yang dilihat.
Sebagaimana dapat disimak pada Self Portrait-nya Ragil, refleksi visual tubuhnya dipecah ke dalam fragmen-fragmen, yaitu ke dalam bingkai-bingkai cermin. Anatomi dari permukaan bagian-bagian tubuh mengalami suatu proses pembagian. Hasil dari proses ini membuka peluang untuk menganalisis refleksi-refleksi tubuh Ragil dalam konteks sudut penampakannya. Posisi cermin, nyatanya, bukan hanya soal apakah berada di atas atau bawah, tetapi juga ke arah mana cermin itu dihadapkan untuk menangkap cahaya dan memantulkan bagian tubuh Ragil. Arah cermin ini, tentu saja, menentukan bagaimana pantulan bagian tubuh itu akan terlihat oleh penonton. Bersamaan dengan itu pula, refleksi cermin memainkan fungsi sebagai sarana untuk menciptakan multiperspektif terhadap objek tubuh aktual Ragil secara serempak.
Selain itu, yang tak kalah penting dibanding keberadaan cermin, ialah ruang kecil kamar mandi. Celah pintu adalah faktor pembatas area visual dari peristiwa yang ditampilkan. Meski begitu, celah ini (ambang pintu) bukanlah bingkai yang kaku dan mati karena ia bukan bingkai dari bidang datar. Celah tersebut faktanya mempunyai kedalaman ruang. Orang-orang di luar kamar mandi masih bisa mengejar visual-visual di balik dinding kamar mandi, selagi pintunya masih terbuka, dengan berpindah posisi: mendekat ke pintu, menjauhi pintu, bergeser ke posisi yang lebih menyamping (bukan berhadapan tegak lurus dengan celah pintu), dan ke posisi-posisi lainnya yang memungkinkan.
Self Portrait (2016) karya Ragil Dwi Putra. (Foto: Forum Lenteng).
Hal yang saya jelaskan di atas tak bisa kita abaikan karena, mau tidak mau, unsur “jarak pandang” menjadi variabel terpenting untuk memahami logika karya ini. Pengalaman melongok kegiatan Ragil melalui celah pintu adalah sebuah singularitas yang merangsang audiens untuk menjajal ragam kemungkinan cara melihat berdasarkan posisi dan arah pandangan mereka sendiri. Dengan segala aspek tersebut, kita pun bisa menyadari bahwa analisa atas tubuh yang ditawarkan oleh Self Portrait bukanlah analisa biologis (atau naturalis), melainkan analisa optik yang beratribusi dengan pengalaman melihat audiens di dalam suatu ruang dan antarruang—fenomenologis. Hal inilah yang lantas menegaskan bahwa tubuh yang dipersoalkan dalam Self Portrait bukan lagi hanya tubuh si seniman, tetapi juga tubuh audiens yang melihatnya.



Audiens melongok ke celah pintu kamar mandi untuk melihat dan mendokumentasikan kegiatan Ragil yang bercermin dan melukis garis di tubuhnya. (Foto: Forum Lenteng).
Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menggarisbawahi bahwa fragmentasi tubuh melalui pantulan cermin-cermin di dalam Self Portrait bukan merupakan ungkapan pasif (yang hanya memancing perilaku kontemplasi tradisional), tetapi menekankan keaktifan dalam proses menonton. Di sini, Self Portrait berdiri di atas paradigma konstruktivis untuk mengorganisasi proses pencerapan visual. Audiens karya akan mengalami perbedaan serta perubahan perseptual setiap kali berpindah posisi saat menyimak aksi Ragil di dalam kamar mandi. Pada bagian inilah kita bisa melihat pertaliannya dengan praktik seni abstrak di era avant-garde Rusia, di mana karya-karya kala itu mengkonstruksi visual menjadi sesuatu yang mengaktifkan gerak publik: penataan ruang sekaligus penataan objek visual di dalam ruang, meski tidak merepresentasikan apa pun (karena dihadirkan secara abstrak), justru menuntut penikmat karya untuk harus mengitari ruang demi bisa melihat karya secara utuh; dan setiap detik dari perpindahan gerak tubuh audiens akan menghasilkan pengalaman makna yang berbeda. Dalam kasus Self Portrait, refleksi cermin merupakan aparatus yang mengabstraksi tubuh, dan situasi dari proses pengabstraksian tersebut berkorespondensi dengan ruang yang ditempatinya. Kombinasi ini—abstraksi tubuh dan pemilihan ruang (sebagai area komplementer)—bekerja bagaikan Abstract Cabinet-nya El Lissitzky. Menurut saya, karya Ragil terbilang berhasil mengadopsi pendekatan karya tersebut ke dalam praktik seni performans.
Ilusi realitas yang dimainkan Ragil melalui cermin, untuk membicarakan tubuhnya, bukan dalam kerangka pikir yang berlandaskan pada gagasan representasional—bukan soal tubuh yang direpresentasikan, entah itu melalui pantulan di cermin ataupun melalui kejadian bercerminnya. Yang sebenarnya terjadi adalah di luar kerangka tersebut: pengorganisasian cara pandang, mengkonstruksi kemungkinan jamak bagi audiens dalam menangkap visualitas dari tubuh yang direfleksikan. Kembali memijakkan argumen saya ke pengertian dasar seni performans, kita bisa menyimpulkan bahwa, alih-alih hanya sajian representatif melalui tanda-tanda non-refleksif, Self Portrait adalah karya yang memproduksi kejadian interaktif antara tubuh seniman dan audiens dengan menempatkan ilusi optik sebagai tema yang memperantarainya. Self Portrait adalah abstraksi tubuh (si seniman) yang mengaktifkan (tubuh) audiens. *
Endnotes
[1] Dalam konteks ini, saya mengartikan “medium” dengan merujuk definisi yang digunakan oleh Dario Marchiori dalam Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives (Amsterdam University Press, 2013), hal. 85-86, yaitu “… sebuah perantara, sebuah sarana transmisi dan ekspresi. Dalam tradisi artistik, ia juga didefinisikan sebagai material atau teknik yang digunakan oleh seniman… yang juga bisa menstrukturkan gaya utama ataupun seni-seni yang tak umum…”. Definisi ini menegaskan bahwa medium bukan sekadar material yang digunakan oleh seniman, tetapi juga tentang bagaimana seniman memperlakukan material tersebut dalam rangka analisa artistik tertentu (yang juga dapat dianalisa oleh penikmat karya) demi mengungkapkan ekspresi. Dengan kata lain, dalam konteksnya sebagai medium, material yang digunakan seniman adalah pokok yang juga dibicarakan, bukan semata elemen pelengkap pada karya.
[2] Terutama yang dapat dipelajari adalah pada karya El Lissitzky tahun 1926/1927, berjudul Abstract Cabinet (atau Cabinet of Abstraction) yang dibuat untuk difungsikan sebagai realisasi dari apa yang ia istilahkan dengan “Demonstration Room”: suatu gagasan penyajian karya seni yang berupaya menciptakan ruang pamer yang menekankan kesadaran pengunjung atas pengalaman visual mereka dan kondisi dari ruang pamer itu sendiri.
[3] Dari istilah Bahasa Inggris: tactility, yaitu sebuah konsep yang berhubungan dengan kapabilitas untuk dapat disadari atau ditanggapi lewat rangsangan indra perabaan (sentuhan).
[4] Penjelasan komprehensif tentang gerakan Konstruktivisme, terutama terkait dengan topik yang saya nukil di tulisan ini, dapat dibaca dalam jurnal yang ditulis Benjamin H. D. Buchloh, “From Faktura to Factography”, October, Vol. 30, 1984, hal. 82-119.
[5] Pemaparan pada paragraf ini, sebagian besar, mengacu pada video edukasi berjudul “The Case for Abstraction” yang diproduksi dan dipublikasikan oleh The Art Assignment di YouTube tanggal 26 Juli 2017: https://www.youtube.com/watch?v=jkT1BVRfJI8